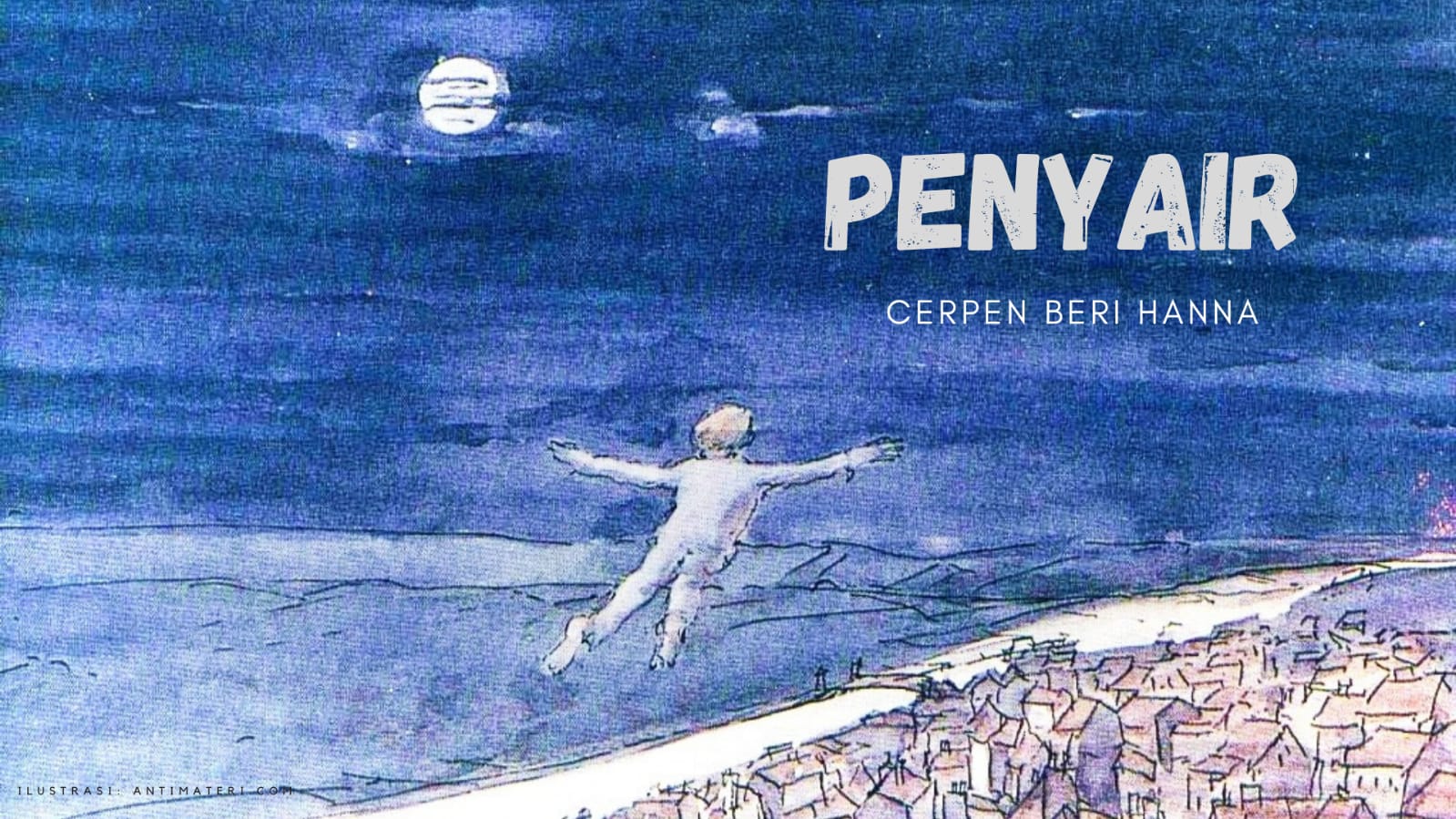Cerpen Beri Hanna
Setelah bertahun-tahun jauh dari rumah, akhirnya saya harus pulang. Menulis puisi di kota besar ternyata tidak menjanjikan. Tidak seperti yang saya harapkan; paling tidak mendapatkan pembaca, justru sangat berbanding terbalik dari itu. Orang-orang tidak suka dan tidak makan puisi. Bahkan uang kontrakan hingga rokok dan segelas kopi tidak pernah bisa dibayar dengan puisi.
Di ruang tunggu stasiun kota, beberapa saat sebelum kereta tiba, saya bertemu seorang perempuan. Beberapa bulan yang lalu, perempuan ini pernah saya lihat di sebuah cafe. Waktu itu ia duduk berdua dengan laki-laki yang terlihat lebih tua. Ia mengikat rambutnya seperti ekor kuda dan laki-laki itu tidak pernah melepaskan tatapannya dari mata si perempuan. Entah kenapa saya memperhatikan gerak-gerik mereka dan, menjadi lebih ingin tahu banyak apa yang dibicarakan.
Waktu pelayan datang menyodorkan menu, saya ingat apa yang saya pesan tidak berbeda dari yang ada di meja si perempuan itu. Sebelum pelayan pergi, saya minta pindah meja yang lebih dekat dari perempuan, dengan alasan supaya bisa merokok.
- Iklan -
Begitulah awalnya saya tahu perempuan ini sebenarnya bukan kekasih si laki-laki tua. Dia juga bukan anak atau saudaranya. Singkat cerita dari apa yang saya dengar, mereka berkenalan di sana, beberapa waktu sebelum saya tiba.
Pulang dari cafe dengan perasaan berbunga setelah puas melihat si perempuan dari jarak meja, saya menulis puisi untuknya dan berharap dapat dimuat koran nasional di minggu berikutnya. Barangkali saja si perempuan itu pembaca puisi—entah mengapa saya bisa yakin begitu—tentu dia akan tahu kalau sosok di dalam puisi itu adalah dirinya. Dan tentu saja, tidak menutup kemungkinan dia akan mencari tahu tentang diri saya. Namun, sayangnya puisi itu tidak pernah terbit.
Tapi kini di stasiun kota, saya kembali bertemu dengannya. Pernah saya tahu sebuah cerita, pertemuan yang terjadi lebih dari satu kali, bisa menjadi sebuah pertanda baik. Saya tidak begitu percaya atau pun penasaran akan sebuah tanda seperti apa pun. Tetapi, inilah pengalaman pertama saya bertemu dengan orang yang belum saya kenal untuk kedua kalinya. Saya merasa ingin menyapanya, karena saya dapat menduga, barangkali tidak akan ada kebetulan untuk pertemuan ketiga.
Saya mendekati perempuan ini dan sebelum saya memulai basa-basi, ia lebih dulu membuat saya heran.
“Sepertinya saya pernah lihat kamu,” katanya dengan suara seperti orang mengingat-ingat sesuatu.
Karena saya tidak siap dengan apa yang dikatakannya, saya juga mengucapkan hal serupa. Saya gugup sekaligus senang karena ternyata ia memperhatikan saya, waktu itu, di cafe.
“Saya pikir hanya saya yang melihat kamu.”
“Oh, saya pun berpikir gitu.”
Saya tersenyum, begitu juga dengan perempuan ini. Tidak lama setelah kami bercakap, kereta saya tiba. Alih-alih pergi naik kereta, saya malah berpura-pura bertindak seolah kereta yang tiba bukan tujuan saya. Tapi, karena pikiran saya bercabang dan percakapan dengan perempuan ini terhenti karena kita berdua seperti bingung dengan suara mesin menderu dan lalu lalang penumpang yang turun dari kereta, tiba-tiba saya berpikir, kalau tidak naik kereta berarti saya harus membeli tiket baru. Itu pun kalau masih tersedia kursi yang kosong. Andaikata sudah tidak ada kursi, tentu saya akan bingung, bahkan mungkin terlontang-lantung tidur di tempat yang tidak pernah saya pikirkan.
“Mau ke mana?” tiba-tiba perempuan ini bertanya. Saya kaget dan menjawab Tulungagung.
“Ini kereta terakhir ke Tulungagung,” lanjutnya seolah mengingatkan supaya saya kembali melihat tiket.
Saya tersenyum dan berterima kasih kepadanya karena sudah mengingatkan. Sebelum melangkah, entah kenapa saya perlu beralasan bahwa pendengaran saya kurang baik. Begitu juga dengan mata saya. Saya tidak bisa melihat tulisan nama kereta di gerbong. Untuk itu saya seharusnya berdekatan dengan petugas. Supaya saya bisa diarahkan dan tidak ditinggal kereta.
Perempuan ini tersenyum. Ia seperti yakin bahwa saya sedang berbohong. Memang saya tidak pandai berbohong. Seingat saya beberapa tahun yang lalu, waktu saya pergoki pacar saya selingkuh, saya bersikap seolah itu bukan sesuatu yang merugikan diri saya. Saya enggan menampakkan kekecewaan apa lagi marah-marah seperti orang hilang akal. Saya hanya tersenyum dan mengatakan bahwa saya kebetulan lewat setelah menemui dua orang wanita di tempat berbeda. Saya katakan juga kalau saya sangat percaya dengan adanya karma. Suatu kewajaran jika suatu hari nanti pacar saya selingkuh, terlebih dengan laki-laki yang lebih tua. Dan saya tidak heran, apalagi terkejut mendapati perselingkuhan itu terjadi di hari ini.
Dengan begitu, saya pikir pacar saya akan merasa runtuh lalu mengejar sambil memohon untuk kembali. Tetapi nyatanya, dia tahu saya bohong dan menertawai saya dengan selingkuhannya. Saya malu. Saya berjalan seperti tidak memiliki kepala. Di tengah suasana ramai, saya merasa seperti orang-orang menghina saya. Menertawakan saya. Hingga meludahi saya karena jijik dengan kebodohan berbohong. Mengaku-ngaku sesuatu yang mustahil saya dapatkan.
Memang ibu saya di kampung pernah menelepon, ibu bilang seharusnya saya bersyukur bisa punya pacar—padahal ibu tidak yakin, saya pernah dengar lewat orang-orang kampung ibu saya menertawai kebohongan saya punya pacar—meski pun nanti, pada akhirnya saya harus dikecewakan. Kekecewaan yang pernah dikatakan ibu serupa air liur yang ada di mulut saya. Begitu berdahak, saya harus siap jatuh sakit. Kembali bertahan dengan realitas bahwa takdir saya, mendapatkan kekecewaan. Saya sadar, setelah menutup telepon saya meludah dengan maksud membuang takdir kekecewaan ibu di kampung yang akan menertawai saya. Menertawai apa yang saya kerjakan dengan puisi-puisi saya.
Begitu naik kereta, saya melihat ke luar jendela. Perempuan itu masih berdiri menungu keretanya. Saya benar-benar merasa apa yang dikatakan oleh ibu bukan sekadar kata-kata. Seharusnya tadi saya bisa tanya nama perempuan itu, ke mana tujuannya, di mana saya bisa menghubunginya. Atau paling tidak saya serahkan puisi yang pernah saya tulis untuknya. Tetapi, lagi-lagi saya menelan kekecewaan, meski kadangkala saya harus meludahinya.
Dalam perjalanan saya memikirkan sesuatu yang akan ditanya oleh ibu. Saya tidak terbayang, pertanyaan semacam apa. Tetapi tentu, saya yakin, ibu tidak akan membaca puisi-puisi saya, terlebih yang saya tulis untuk perempuan itu. ***
Tentang Penulis:
*BERI HANNA, penulis lahir di Bangko. Jualan di @bukuodessa dan bergiat di Kamar Kata Karanganyar.