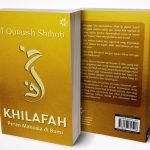Cerpen: A. Warits Rovi
Dari balik jendela kamar kos, aku memandangi kekar dahan rambutan bersanggul daun lebat. Jan dinding kusam yang kaca penutupnya sudah pecah menunjukkan pukul 08.23 pagi. Berdetak keras di samping sebatang tongkat yang kugantung pada setancap paku. Tongkat kayu itu bergambar helai-helai rambut panjang bergelombang sisa goresan mata duri carang. Ujungnya diberi tali sobekan kafan sebagai alat gantung. Tongkat itu pemberian Kiai Halim kepadaku ketika aku hendak berangkat ke kota ini. Itulah sebabnya, ketika melihat tongkat itu, aku jadi teringat kiai Halim. Ketika ingat Kiai Halim, dadaku serasa sejuk dan tenang, seolah ia mata air di hulu sungai yang selalu mengirim air ke hilir jiwa.
Di pagi yang senyap itu, kemudian aku teringat kepada ayah di kampung, yang lumpuh dan tuli, sudah empat tahun berkarib kesengsaraan di datar dipan tua yang reot dan penuh sawang laba-laba. Keluargaku sudah tidak mampu lagi untuk mengobatinya karena harta yang kami miliki sudah habis untuk pengobatan-pengobatan sebelumnya. Oleh sebab itulah aku harus tandang ke kota ini, bekerja sebagai jasa semir sepatu keliling atau kadang menyewa becak dan bekerja mengayuh becak meski dengan kondisi fisik yang tak kekar dan kurang berotot untuk ukuran pekerja kasar pada umumnya. Tapi kekuatan selalu ada, didorong oleh rasa cinta yang dahsyat untuk menghidupi keluarga, terlebih untuk bisa mengobati ayah.
Dulu, ayah seorang pengusaha kelapa yang sukses, tapi beberapa tahun kemudian ayah difitnah sebagai tukang sihir dan beternak tuyul oleh seseorang. Orang itu memprovokasi warga untuk berhati-hati dengan ayah, akhirnya warga tidak menjual kelapa lagi kepada ayah. Warga banyak yang antipati kepada keluarga kami. Hanya sebagian kecil kerabat termasuk Kiai Halim, guruku yang tetap bersikap baik kepada keluarga kami.
- Iklan -
Fitnah itu terus berlangsung dengan sadis mirip api melalap daun pisang kering berlumur bensin. Bisnis ayah menjadi lumpuh, sudah begitu, ayah dikeroyok massa saat mencoba untuk menjelaskan yang sebenarnya. Keroyokan itu membuat ayah lumpuh dan tuli. Oleh paman, ayah diobati ke berbagai tempat, mulai dari penanganan medis hingga penanganan dukun, tapi semua tak membuahkan hasil. Tanah dan perhiasan ibu banyak yang dijual untuk biaya pengobatan ayah.
Suatu hari, keluarga kami baru tahu, ternyata Kimun—tetangga kami—yang memfitnah ayah dan mengompori warga. Sontak keluargaku marah, terutama aku dan paman, hampir saja kami berdua membunuh orang itu, tapi dia sudah lebih dulu kabur ke luar pulau, akhirnya kami mengembalikan celurit bergantung kembali ke paku yang menancap di tembok. Hingga suatu pagi datanglah Kiai Halim menasihatiku dengan kalimat dan intonasi yang lembut. Ia menyarankanku supaya lebih baik bekerja jika ingin membahagiakan ayah, bukan dengan cara balas dendam.
Seminggu setelah itu, setelah melalui pertimbangan yang cukup, akhirnya aku pamit untuk bekerja ke kota ini. Aku harus meninggalkan keluarga yang wajahnya selalu mengirim jejak kerinduan ke dalam hati. Meninggalkan teman-teman di surau tempat aku mengaji kepada Kiai Halim.
Ya, bila ingat itu, dadaku terenyuh. Tanpa kusadari, pagi ini air mataku berlinang kembali. Ruangan kamar kos jadi saksi bahwa aku sedang dirajam kenangan yang menyakitkan. Aku terisak, mengiringi tiktok jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 09.05. Pagi ini aku agak siang untuk pergi menawarkan jasa semir. Mataku masih terpaku ke luar jendela, memandangi kekar dahan-dahan rambutan.
Di sela keterpakuanku menatap dahan kekar, seketika mata beralih pada seorang lelaki yang melintas di halaman kos; tubuhnya kurus dipayungi lebat rambut panjang yang dibiarkan tergerai hingga ke punggung, bibirnya tertutup lebat kumis yang hitam, sebentuk gambar tato merajah bagian bawah lengan kanannya. Ia berlalu dari halaman, menyeberang jalan dan membeli makanan di warung Bi Ijah. Aku mendekat ke jendela. Mengintai lebih rinci orang itu yang tengah sedikit berdesak-desakan dengan pembeli lain. Sekitar dua menit kemudian ia kembali menyeberang jalan dan melintas di halaman kosku dengan sebuah tas plastik berisi barang yang tadi ia beli. Sontak aku terperanjat, mataku diatur lebih fokus ke wajah orang itu.
“Huh!” aku mendengus.
Ketika melihat wajah lelaki gondrong itu, aku teringat masa laluku, seketika darahku naik, sekujur tubuhku terasa hangat, tangan mengepal kuat, gigi rapat bergemeretak, amarahku memuncak. Kulihat wajahku memerah dalam perut cermin yang menempel di dinding. Aku dendam kepada lelaki itu, dialah yang dulu menyebar fitnah di dusun hingga usaha ayah bangkrut dan keluargaku jatuh miskin. Rembetannya, aku harus bekerja di kota ini. Hampir saja aku membuka pintu untuk keluar menghajarnya, beruntung mataku sempat menatap tongkat di dinding, memandangi gambar helai-helai rambut panjang yang bergelombang, makna gambar itu lalu menghadirkan sosok kiai Halim, menghadirkan petuah-petuahnya tentang sopan santun.
Perlahan, emosi bisa kuredam. Lelaki itu ternyata masuk ke dalam kamar kos yang hanya terpisah dua kamar lain dari kamarku. Aku penasaran, apa lelaki itu benar-benar Kimun atau bukan.
#
Di sela-sela kesibukan keluar rumah untuk menemui orang-orang yang hendak menyemir sepatu, atau kadang juga untuk mengayuh becak, aku menyempatkan diri mengamati lelaki gondrong itu, ternyata ia hanya keluar saat pagi dan sore hari untuk membeli makanan. Dilihat dari raut wajah dan keadaan tubuhnya, dia seperti menderita sebuah penyakit. Mimiknya kerap meringis seperti menahan rasa sakit dan cemas. Bila diamati secara teliti, wajahnya nyaris menyerupai wajah Kimun, tapi lebih tirus dan tua. kadang aku menduga-duga; mungkin dia adalah Kimun yang sudah tua atau mungkin saudaranya, tapi kadang aku berkesimpulan; tidak mungkin.
Pada suatu pagi yang gerimis, akhirnya aku berkenalan dengan lelaki gondrong itu di warung Bi Ijah. Dugaanku benar, ia bernama Kimun, lelaki yang pernah memfitnah usaha ayah ketika dirinya baru berkeluarga ke desa kami. Ia hijrah ke kota ini demi menghindar amarah keluargaku, tapi kini ia jatuh miskin, dan hidup sebatang kara.
Seperti dugaanku, ia juga menderita penyakit kronis. Tubuhnya semakin kurus, tulang rahang dan pipinya mulai menonjol di antara balutan kulit keriput. Napasnya sering tersengal-sengal bagai motor tua menempuh tanjakan, ia sering batuk dan mendahak darah, bisanya cuma duduk sedih bersandar bantal. Bibirnya kering dan seluruh tubuhnya gemetar. Andai dendamku masih ada, sangatlah gampang bagiku untuk membunuh atau paling tidak menyakitinya.
Tato dan rambut gondrongnya sudah tak sesuai dengan keadaan tubuhnya yang sakit-sakitan. Ia kini hanya pasrah pada apa pun yang terjadi. “Setiap hari, ia baru bisa menikmati makanan jika ada orang yang mengantar,” tutur Bi Ijah suatu waktu.
Karena penasaran kepada cerita Bi Ijah, akhirnya diam-diam aku mengintip dia dari balik jendela kamar kosnya pada suatu sore. Aku sangat bahagia melihat dia dalam keadaan seperti itu. Serasa rasa sakit ayah dan keluargaku beberapa tahun lalu yang disebabkan ulahnya baru terbayar sore itu.
“Selamat menikmati kesedihan wahai durjana!” gumamku riang..
Aku bergegas pergi seraya berharap nanti malam atau besok, aku mendengar kabar kematiannya yang purna dalam kesengsaraan di kamar itu.
Setiba di kamar kos, tatapku terantuk pada sebatang tongkat yang bergantung senyap di dinding, masih dengan gambar rambut panjang berupa garis-garis bergelombang, tergores dari ujung hingga pangkal. Saat menatap tongkat itu, aku juga teringat makna filosofis dari gambar rambut panjang di tongkat itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Halim. “Ya Allah! Mestinya aku tidak bersikap begini kepada orang yang sudah tidak berdaya,” ucapku sembari mengelus dada dan menarik napas. Lantas aku balik menuju kosnya.
Setelah memberi salam, ia menyuruhku masuk, kakiku serasa menapak ruang penderitaan. Kamar itu sangat sunyi dan menguar bau apek dan pesing. Ia terbaring lemah di selembar spanduk bekas yang tergelar di lantai, berselimut sarung sambil menahan gigil, padahal sebagian tubuhnya disorot senja yang menyemburat kuning wortel dari kaca jendela. Sedang di sisinya, ada dua mangkuk berisi nasi basi beserta lauknya yang menumpuk, tepi mangkuk itu dikerubung semut dan lalat. Ia meringkuk tak berdaya. Dua tangannya bersedekap di dalam selimut.
Dalam situasi seperti itu, jika kuturuti keinginan nafsuku, begitu mudahnya untuk melampiaskan dendam sepuas-puasnya kepada orang yang dulu memfitnah ayah itu. Satu tonjokan tangan kiriku saja, sudah pasti bakal membuatnya sekarat.
Aku berperang dengan suara nafsuku. Makna gambar rambut panjang pada sebatang tongkat di dinding kos senantiasa kuhadirkan dalam ingatan, sehingga aku ingat Kiai Halim, dan mengurungkan niat balas dendam itu.
#
Akhirnya aku akrab dengan Kimun. Akulah yang kini merawatnya. kami saling bercerita perihal riwayat hidup kami masing-masing. Keakraban itu membuat Kimun menguak kejujurannya padaku.
“Akulah lelaki yang dulu memfitnah ayahmu itu, Fir. Aku rela kini kau balas salahku itu, bagaimana pun caranya. Jujur, aku ingin menebus dosaku,” suaranya lirih. Air matanya berlinang. Aku hanya diam, melirik wajahnya pelan. Sosok Kiai Halim dan tongkat itu masih bisa mengerem dendamku. Aku menggeleng lalu pamit pulang.
Setiba di kamar kos, kuraih sebatang tongkat pemberian Kiai Halim itu. Sejenak aku menimangnya di depan pintu. Mengamatinya dari ujung hingga pangkal. Gambar rambut panjang berupa goresan garis-garis bergelombang itu membuatku teringat makna gambar tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Halim; rambut panjang sebenarnya filosofi Madura yang berarti lemas dan lembut. Tetua Madura banyak yang bilang “selemas-lemasnya rambut kalau dicukur pendek akan tetap kasar, tapi sekasar-kasarnya rambut kalau dibiarkan panjang maka akan lemas dan lembut”. Itu artinya, seseorang yang pribadinya lembut tapi pikirannya pendek pasti kerap berbuat kasar, sedang seseorang meski pribadinya kasar tapi mau berpikir panjang, niscaya ia akan lembut. Dan untuk mengingatkanku tentang filosofi itu, Kiai Halim akhirnya menggambar tongkat pemberiannya itu dengan goresan rambut panjang bergelombang.
Aku tersenyum. Mencium tongkat itu seraya terpejam. Dan seketika terjadi keriuhan halaman. Bu Kos mondar-mandir memberitahu penghuni kos yang lain bahwa Kimun sudah meninggal. Aku bingung, mau berduka apa mau bahagia.
Rumah Ibel, 15.04.20
*A. WARITS ROVI, lahir di Sumenep Madura, 20 Juli 1988. Karya-karyanya berupa cerpen, puisi, esai dan artikel dimuat di berbagai media nasional dan lokal antara lain: Kompas, Tempo, Jawa Pos, Horison, Media Indonesia, Republika, MAJAS, Suara Merdeka, Seputar Indonesia, Indo Pos, Majalah FEMINA, Kedaulatan Rakyat, Pikiran Rakyat, dll. Juara II Lomba Cipta Cerpen ICLaw Pen Award 2019. Buku Cerpennya yang telah terbit “Dukun Carok & Tongkat Kayu” (Basabasi, 2018). Ia mengabdi di MTs Al-Huda II Gapura. Berdomisili di Jl. Raya Batang-Batang PP. Al-Huda Gapura Timur Gapura Sumenep Madura 69472.