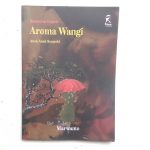Cerpen Halima Masyaroh
Agama, apa itu? Aku sama sekali tak menganggapnya penting. Di buku laporan pendidikanku sejak SD hingga SMA kolom agamanya berganti-ganti agama.
Di buku laporan pendidikanku saat SD pada deret agama di data diriku beragama Islam, saat SMP entah bagaimana jadi Protestan, gilanya lagi aku mencoba Agama Hindu untuk di buku laporan pendidikan SMA. Administrasi masih sangat morat-marit saat itu. Belum ada sistem pendataan daring yang akurat seperti sekarang. Bahkan orang tuaku tidak memiliki KTP.
Tak ada masalah agama apa pun itu di buku laporan pendidikanku, toh aku tidak pernah menjalankan ajarannya. Di sekolah seminggu sekali aku sama dengan teman-teman lainnya, kami mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan administrasi. Tapi aku masih ikut-ikutan kedua orang tuaku yang menganut dan menjalakan Agama Adat Penghayat.
- Iklan -
Agama apa pun yang ada di buku laporan pendidikanku, aku tidak meninggalkan ajaran turun-temurun dari keluargaku. Aku tetap menjalankan ibadah dan menyembah roh tertinggi yang kami percayai sebagai pencipta semesta. Kami pula menyakini roh abadi, roh alam dan roh orang mati. Semua kepercayaan dengan kekuatan gaib itu kami wujudkan dengan pemberian sesaji dan upacara kerohanian.
Hingga saatnya aku berusia 18 tahun, aku membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) selulus SMA. Aku hendak melanjutkan pendidikanku ke perguruan tinggi swasta di Kota Namlea, ibu kota Kabupaten Buru, Maluku. Anehnya, ini tak semudah kala aku mencantumkan agama di buku-buku laporan pendidikan saat di bangku sekolah. Aku dilanda dilema.
Tak cukup membutuhkan hari, bahkan berminggu dan berbulan pun tak cukup untukku memilih agama. Aku rela menunda mendaftar ke perguruan tinggi hanya karena sebuah agama dalam KTP. Saat sekolah, aku merasa agama bukanlah beban, namun seiring matangnya usia, aku tergugah untuk menekuni ibadah atas agamaku nanti. Sebagai anak dari orang tua yang memiliki kepercayaan penghayat, aku pun tidak sepenuhnya beribadah. Aku hanya ikut-ikutan saja dalam bertuhan. Ada kekosongan dalam jiwaku soal ketuhanan.
Untuk mengisi waktu karena menunda mendaftar di perguruan tinggi, aku bekerja menjadi pelayan toko kelontong di Mako, Ibu kota kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Tempat aku kerja berjarak sekitar 8 kilo meter dari kampungku, Waegernangan, Kecamatan Lolong Guba. Karena aku tak memiliki kendaraan motor pribadi, Tuan pemilik toko mempersilakanku untuk tinggal di kediamannya bersama karyawan-karyawan toko lainnya. Pak Haji Mustafa, begitu beliau disapa. Istrinya yang baik hati biasa kami sapa dengan sebutan Ibu Haji.
Pekerjaanku menata barang-barang dagangan dan melayani pembeli. Kadang Pak Haji Mustafa juga mempercayakanku untuk menjaga laci kasir jika beliau pamit menjalankan ibadah lima waktu yang disebut salat katanya.
“Nyalintang, ini Hari Minggu, kamu enggak pulang kampung untuk ke Gereja?” tanya Ibu Haji pada suatu Hari Minggu.
“Aku bukan penganut Kristen, Bu Haji,” sahutku sambil sedikit menunduk tanda hormat.
“Oh, Maaf. Ibu salah, ya, Nak,” Senyum ramah Ibu Haji masih dengan dialek Sunda yang kental.
“Tak apa, Bu Haji.”
Di sini, walau jauh bermil-mil dari Indonesia Bagian Barat, namun kita dapat menemukan begitu banyak orang dari Suku Jawa, Sunda, Madura dan suku-suku lainnya. Mereka didatangkan ke Pulau Buru pada tahun 1979 dalam program transmigrasi. Majikanku adalah salah satu dari mereka, yang didatangkan dari Garut, Jawa Barat.
Bersyukur sekali pada Tuhan, walau aku belum mengenal siapa Tuhan itu. Aku dianugerahi majikan dan rekan kerja yang baik, ramah, sopan dan perhatian. Walau statusku hanya karyawan, lauk-pauk makanku sama dengan yang dimakan Pak haji Mustafa dan Ibu Haji. Tak ada kasta walau kami berbeda suku dan keyakinan. Eh maaf, bahkan aku tak memiliki keyakinan saat itu.
“Nyalintang, timbangannya harus pas, ya. Tolong bungkus gula ini masing-masing satu kilo, jangan kurang sedikit pun. Kita enggak boleh curang pada pembeli,” perintah Pak Haji Mustafa yang dikenal jujur dalam berdagang.
“Baik, Pak Haji.” Sambil kubungkusi dan kutimbang gula dalam plastik-plastik bening itu.
Pak Haji Mustafa tak mengawasi pekerjaanku membungkus gula sore itu. Beliau pamit untuk ke masjid terdekat, Masjid Jami Assalamah yang berlokasi di tikungan jalan raya masuk Mako.
“Assalamualaikum.” Terdengar salam orang muslim dari depan toko.
“Waalaikum salam,” sahutku spontan karena sudah biasa mendengar majikan dan karyawan toko lainnya menyahut salam ala orang muslim.
“Maaf, Mbak. Ada Pak Haji Mustafa?” tanya seorang pria berkulit kuning langsat dengan senyum yang dihiasi lesung pipi. Demi Tuhan, senyum itu manis sekali.
“Eh, anu. Pak Haji masjid. Eh, Pak Haji ke masjid,” jawabku dengan kalimat yang berantakan.
“Oh Pak Haji ke masjid, ya, Mbak?” lelaki itu mengulangi kalimatku.
“Benar, katanya mau salat berjamaah. Salat ashar kalau enggak salah namanya,” ucapku dengan segenap kekuatan jantung yang debarannya berjarak lebih rapat dari degupan normal.
“Kalau Bu Haji, ada enggak, Mbak?” tanyanya lagi.
“Oh, kalau Bu Haji ada, sebentar, ya, aku panggilkan dulu.” Aku sedikit menunduk, sikap menghormati.
Tetapi sebelum aku beranjak dari toko untuk memanggil Ibu Haji ke rumah belakang, Ibu Haji sudah berada di pintu masuk toko. Ada mata berbinar dari wajah lembut Ibu Haji saat menatap pemuda paling tampan yang pernah aku lihat di dunia nyata itu.
“Arif?” Ibu Haji berlari dan memeluk lelaki muda itu.
“Ibu.” Seseorang bernama Arif itu membalas pelukan Ibu Haji.
Mereka berdua keluar toko menuju rumah belakang tempat majikan dan karyawan tinggal. Ibu Haji dan pemuda yang disebut Arif tadi berlalu tanpa peduli padaku yang masih terpaku dengan bibir agak menganga. Aku belum menguasai kondisi, antara kagum dengan ketampanan atau kebingungan dengan keakraban Ibu Haji dan Arif.
“Eh, itu tadi siapa?” tanyaku pada Rani yang dari tadi duduk dan senyum-senyum saja di depan laci kasir.
“Itu Kang Arif, putra sulung Pak Haji Mustafa. Dia baru pulang dari pesantren, makanya kamu baru lihat dia, kan?” ungkap Rani.
“Baru pulang dari pesantren? Pesantren itu kota di provinsi mana?” tanyaku sambil melipat dahi dan menggosokkan jari jempolku ke dagu tanda sedang berpikir keras.
“Yaa Salam … pesantren itu bukan nama kota, tapi tempat orang muslim menimba ilmu agama. Dia akan menjadi ustaz atau guru agama,” Rani menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah kumengerti.
“Oh, kukira Teh Zahra adalah anak sulung Pak Haji Mustafa. Ternyata Pak Haji punya anak cowok ganteng, ya?” ucapku nyengir menampakkan seluruh gigi taringku.
“Heh! Jangan kegenitan! Kang Arif itu alim sekali, bukan cowok sembarangan,” pesan Rani menciutkan hatiku yang baru saja hendak berbunga.
Parah sekali Rani itu, belum pernah hatiku semengembang ini, malah dibuatnya layu seketika. Selain mencari nafkah di toko ini, sepertinya aku juga akan mencari cinta. Ah, rasanya aku mulai kerasukan rasa yang datangnya dari entah berantah.
Pukul 6:30 WIT aku, Rani, Joko dan Darma sudah membuka toko dan merapikannya. Setiap Hari Minggu, Selasa dan Kamis, kami membuka toko lebih awal karena itu adalah hari pasaran di pusat kota Kecamatan Waeapo, yaitu Pasar Mako kompleks pertokoan di mana toko Pak haji Mustafa berada.
Kulihat dari kejauhan Kang Arif dengan mengenakan sarung sebagai outfit bawahannya pulang dari Masjid Assalamah. Kurapikan anak rambutku agar tampak lebih cantik saat Kang Arif tiba di toko. Rambut keritingku khas orang timur selalu tampak rapi dan terawat sejak aku bekerja dan berpenghasilan.
“Selamat pagi Kang Arif,” sapaku agak merunduk sopan.
“Selamat pagi Mbak Lintang, selamat bekerja,” balas Kang Arif dengan senyum teduh namun tanpa mata yang jelalatan dan berlalu menemui Pak Haji Mustafa.
“Selamat.” Kulipat satu jariku.
“Pagi.” Kulipat dua jariku.
“Mbak.” Kulipat tiga jariku.
“Lintang.” Kulipat empat jariku.
“Selamat.” Kulipat lima jariku.
“Bekarja.” Kulipat eman jariku.
Enam kata dari bibir Kang Arif menjadi sistem pendukung yang bekerja dalam mesin semangatku hari ini. Sistem pendukung semangat yang suatu hari nanti kuketahui adalah rasa jatuh cinta.
Entah kekuatan dari mana hingga menimbulkan keberanianku untuk membuntuti Kang Arif pada suatu petang atau biasa orang muslim menyebutnya magrib. Petang itu aku pamit pada Ibu Haji untuk membeli gorengan yang dijual di pertigaan sekitaran masjid.
Kubuntuti pria bersarung cokelat dan berkopiah hitam itu menuju masjid untuk salat berjamaah. Aku berada sekitar 20 meter di belakangnya. Mungkin Kang Arif punya firasat, hingga dia menoleh kebelakang dan membuatku gugup tidak karuan. Kang Arif menghentikan langkahnya, dia tampak menungguku melangkah mendekat. Tiba-tiba kakiku terbebani satu ton beras, berat sekali melangkah dalam gugup.
“Mbak Lintang mau ke mana?” tanyanya setelah jarak kami sekitar lima meteran.
“Eh, anu Kang. Aku, hmm aku mau beli gorengan.” Kugaruk kepalaku yang sama sekali tidak menjadi pemukiman kutu rambut.
“Oh mau beli gorengan. Aku titip sekalian, ya, Mbak Lintang. 10 ribu saja, tahu isi dan pisang goreng. Nanti jangan langsung pulang, tunggu aku di depan gerbang masjid, ya.” Kang Arif menyerahkan uang pecahan 10 ribuan.
Jika jantung ini bukan buatan Tuhan, mungkin sudah terlepas dari penyangganya. Entah berapa skala richter degupannya. Aku tak sanggup menghitung berapa kata yang tadi Kang Arif ucapkan untukku. Intinya seluruh kata itu masuk ke dalam sistem perasaanku.
Tentu tak kusia-siakan kesempatan ini. Sehabis membeli gorengan yang sebenarnya hanya modus belaka, aku menunggu Kang Arif di gerbang masjid. Dari pengeras suara terdengar seorang imam salat melafalkan kalimat yang kuketahui sebagai surat Al Fatihah, guru agamaku saat SD mengajarkannya. Teduh dan menenangkan suara sang imam salat magrib petang itu. Senangnya bagi mereka yang menyakini dan mengimani Tuhan. Sedangkan aku belum juga bertemu dengan Tuhan yang pas di hati.
“Mbak Lintang,” sapa Kang Arif membuyarkan lamunanku.
“Eh, iya Kang.” Aku salah tingkah.
“Mana gorengan pesananku?” Kang Arif menyodorkan tangan kanannya.
“Ini Kang.” Aku menyerahkan dua plastik kecil gorengan berisi tahu isi dan pisang goreng.
“Terima kasih, ya. Mbak Lintang pulang duluan, Pak Haji pasti sedang nunggu di toko. Aku mau bagi gorengan buat anak-anak ngaji, sekalian aku nunggu salat isya baru pulang.”
Huh! Kukira Kang Arif memintaku menunggu itu untuk pulang bersama. Campur aduk perasaanku sepulang dari gerbang masjid. Ada rasa berbunga pada Kang Arif, sekaligus rasa bingung pada ketidakjelasan Tuhan di hatiku.
Setelah kejadian menunggu Kang Arif di depan gerbang masjid itu, aku selalu gemetaran setiap mendengar imam salat membacakan Al Fatihah. Membeli gorengan adalah alasanku untuk izin keluar toko menuju lokasi dekat masjid demi mendengarkan suara imam masjid. Gemetar di awal Al Fatihah, kemudian ketenangan di akhirnya. Apakah aku sudah menemukan Tuhan?
Sekitar sebulan aku dirundung kegelisahan. Kuceritakan kegelisahan itu pada Rani, sesama karyawan di toko milik Pak Haji Mustafa.
“Kamu serius? Coba tanyakan kembali ke isi hatimu, Nyalintang! Jangan sampai kamu ingin memeluk Islam karena kamu jatuh hati pada Kang Arif sebagai muslim yang taat,” ujar Rani setelah kuungkapkan niat memeluk Islam.
Rani ada benarnya, aku memang sedang sangat jatuh hati pada putra sulung majikanku itu. Sebenarnya dahsyatnya getaran Al Fatihah lebih kencang daripada getaran saat melihat senyum Kang Arif. Tapi Rani tidak ada salahnya berpendapat demikian. Kuurungkan niat lekas memeluk Islam. Aku sibuk berpikir, meresapi dan menyakinkan diri.
“Hari ini toko tutup, ya. Kita ada acara masak-masak,” perintah Ibu Haji pada semua karyawan toko.
Semua mematuhi perintah tanpa bertanya mengapa. Beberapa tetangga juga datang untuk membantu masak-masak yang cukup banyak.
“Ran, ada acara apa, ya, ini?” tanyaku saat mengiris sebaskom bawang merah bersama Rani.
Rani tampak agak kikuk untuk menjawab pertanyaanku. Ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik bola mata Rani yang tidak bisa berbohong. Kukenal dia sebagai perempuan yang jujur dan polos.
“Calon besan Pak Haji Mustafa mau datang nanti malam,” sahut Rani pelan tanpa berpaling dari irisan bawang merah.
“Hah? Siapa yang mau menikah, Ran?” tanyaku mendekatkan sumber suaraku ke telinga Rani.
“Kang Arif,” jawab Rani singkat, ada rasa tidak tega di mata bulat Rani terhadapku.
“Aku enggak pernah mendengar Kang Arif punya pacar,” ujarku penuh selidik pada mata Rani yang tak kunjung menatapku.
“Kang Arif dan Neng Anissa memang enggak pacaran. Mereka melalui jalur taaruf. Pasti kamu mau bertanya taaruf itu apa, kan?” kali ini Rani menatap mataku yang mulai menatap tanpa arah.
Aku tak menjawab pertanyaan Rani. Aku bahkan tak mau tahu taaruf itu apa, yang pasti taaruf membuatku patah. Tanpa kuminta, Rani menjelaskan bahwa taaruf itu adalah perkenalan pria dan wanita yang serius membawa perkenalan itu ke jenjang pernikahan. Berbeda dengan pacaran dan hanya menjajaki hubungan yang pernikahannya entah kapan.
Ada setan kecil menyusup dalam urat-uratku. Marah dan patah sedang berkerja sama menghancurkan saraf-saraf yang menyalur ke dalam gumpalan hati. Sebelumnya aku tak pernah jatuh hati, dan baru kuketahui bahwa jika jatuh itu sesakit ini.
Dalam keramaian di rumah Pak Haji Mustafa, aku merayakan sunyi dan berlalu. Aku berlarian tanpa kuketahui harus ke mana, namun kaki-kaki letihku menuntunku menuju Masjid Jami Assalamah.
“Wahai Tuhannya orang muslim! Bolehkah aku yang bukan umat-Mu, mencintai hamba-Mu?” Aku berlulut di depan pintu gerbang masjid.
“Mbak Nyalintang?” sapa suara yang sama sekali tak asing, suara teduh milik pita suara Kang Arif.
Dia tepat di belakangku, aku yakin dia mendengar keluhanku tadi. Aku tertatih berdiri sambil menyeka kedua mataku, mengucek lebih tepatnya, agar tidak ketahuan sedang berlinang.
“Pertanyaanmu nanti akan kusampaikan pada Tuhanku, ya, Mbak,” ucap Kang Arif bahkan tanpa menatap mata sembabku, dia sangat menjaga pandangan.
“Terima kasih, Kang.” Aku pun berlalu tanpa sanggup menatap wajah teduhnya yang menyejukan bak hujan di musim kemarau.
Sejak itu aku pamit dari toko keluarga Pak Haji Mustafa. Aku pulang kampung dan berhenti bekerja. Aku memang patah dan kecewa terhadap Tuhannya orang muslim, tetapi aku selalu tergetar dan terpanggil oleh ayat Tuhan yang pernah kudengar di Masjid Jami Assalamah. Aku terpanggil untuk mengenal-Nya, maka aku melafalkan dua kalimat Syahahadat disaksikan pengurus masjid di kampungku.
Dengan terikatnya tali syahadat di leherku, mematahkan prasangka Rani bahwa aku tertarik pada Islam karena cintaku pada Kang Arif seorang muslim yang taat. KTP segera kuurus, Islam yang tertera pada deret agama. Recana berkuliah waktu itu, kuwujudkan segera. Aku menata hidup dan puing-puing perasaan.
Kutemukan atas jawaban Allah bahwa aku diperbolehkan mencintai hamba-Nya. Namun untuk memilikinya aku harus terlebih dahulu menjadi umat-Nya. Terbukti aku juga menikah di saat akhir semester kuliahku. Aku dinikahi oleh seorang duda yang istri dan anaknya tewas dalam kecelakaan.
***
Kutatap foto wisudaku bersama suami dalam satu pigura berukir. Suami yang kucintai lahir dan batin. Darinya aku semakin kenal akan Tuhan.
“Oma, sedang kangen Opa, ya?” tanya Aisyah cucu pertamaku yang masih berumur enam tahun.
“Iya, sayang,” jawabku sembari membelai rambutnya dengan tangan keriputku.
“Semoga Opa tenang di sisi Allah, ya, Oma. Opa husnul khatimah.” Senyum Aisyah sebagai pelipur dukaku atas kepergian suami untuk selamanya karena sakit yang diderita.
“Oh iya, dulu waktu masih muda, Oma memanggil Opa dengan panggilan apa?” tanyanya lagi sambil mengusap-usap foto wisudaku yang sedang didampingi suami.
“Kang Arif.”
Pulau Buru, Januari 2022
Tentang Penulis:
*HALIMA MASYAROH, seorang ASN di lingkup Pemkab Buru, Maluku. Penulis dari Pulau Buru ini jejaknya dapat diikuti pada akun Instagram @hamays_official