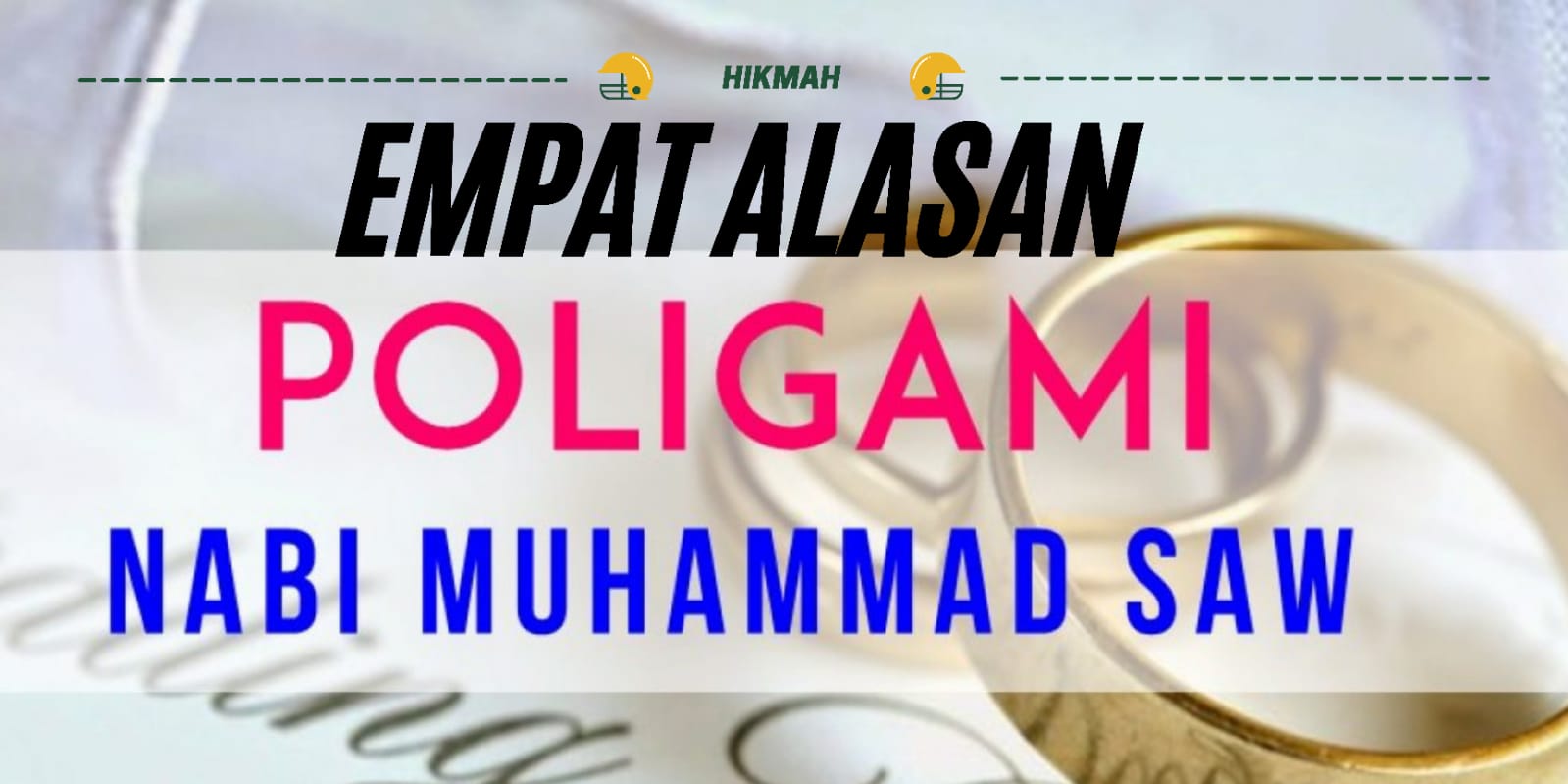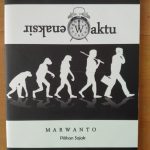Oleh Ahmad Rijalul Fikri
Isu Nabi berpoligami masih menjadi gorengan empuk pihak-pihak yang “alergi” dengan Islam. Mereka mengusung isu tersebut dalam upaya mendiskreditkan Rasulullah dan syariat Islam. Berbagai tuduhan pun mereka lontarkan, antara lain soal alasan Nabi berpoligami, menurut mereka, adalah karena hasrat seksual belaka.
Jelas itu tuduhan yang sangat tendensius dan mengada-ada. Sebagai Manusia Agung pembawa risalah Tuhan, tentu ada tujuan mulia di balik tindakan Nabi berpoligami. Mustahil seorang Nabi berpoligami secara serampangan, apalagi lantaran dorongan nafsu birahi.
Guna merespons ahwal itulah, Syekh Muhammad Ali al-Shabuni menuliskan sejumlah tanggapan argumentatif dalam bentuk makalah setebal 56 halaman. Judulnya, Syubuhaat wa Abaathiil haula Ta’addud Zaujaaat al-Rasuul Shallallaahu ‘alayhi wa Sallama. Di dalam makalah tersebut, ulama kelahiran Suriah itu mementahkan segala tuduhan buruk tak mendasar terkait praktik poligami Rasulullah.
- Iklan -
Dua fakta penting yang beliau beberkan pertama kali spesifik menepis anggapan Nabi berpoligami demi syahwat. Pertama, fakta bahwa Nabi baru melakukan poligami setelah memasuki usia senja, yakni dalam rentang usia 50 tahun ke atas. Kedua, fakta bahwa madu Nabi semuanya berstatus janda tua, kecuali Siti Aisyah satu-satunya yang perawan dan muda belia.
Berangkat dari dua fakta tadi, maka anggapan miring terhadap poligami Nabi benar-benar tidak benar. Sebab, jika benar demi nafsu syahwat, tentu Nabi sudah berpoligami sejak usia muda dan memadu dara-dara muda saja. Hal ini amat mudah untuk Nabi lakukan, mengingat daya tarik Nabi sedari muda yang berintegritas, berparas rupawan dan berasal dari keluarga terpandang.
Lantas, apa sebetulnya alasan yang mendasari Nabi berpoligami?
Ada banyak alasan mengapa Nabi berpoligami dan Syekh Ali al-Shabuni mengategorikannya ke dalam empat aspek, yaitu aspek pendidikan, aspek agama, aspek sosial, dan aspek politik.
Aspek pendidikan
Menurut sosok mufasir lulusan Universitas Al-Azhar Mesir itu, aspek pendidikan menjadi alasan utama Nabi berpoligami. Bahwa Nabi hendak mengkader istri-istrinya sebagai ulama perempuan, yang bakal lebih leluasa mendidik para sahabat dari kalangan perempuan, tentang hukum-hukum syariat secara detail.
Pasalnya, mayoritas mereka sungkan bertanya langsung kepada Rasulullah. Lebih-lebih permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengalaman mereka selaku perempuan, semisal haid dan nifas. Sementara Nabi sendiri, di antara akhlaknya adalah punya rasa malu yang luar biasa besar. Karena itu, untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, Nabi pun malu menjelaskan kepada mereka secara lugas, dan terpaksa menyensor penjelasannya menggunakan bahasa kinayah.
Lalu, alasan krusial lainnya berkaitan dengan periwayatan hadis. Sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an, hadis mencakup segala ihwal hidup Rasulullah, baik itu yang berbentuk ucapan, tindakan, maupun persetujuan. Sedangkan tidak ada orang yang dapat diandalkan untuk merekam tingkah laku Nabi secara intensif sampai ke ruang-ruang privat Nabi, selain istri-istri Nabi. Jadi, selain sebagai ulama perempuan, istri-istri Rasulullah juga termasuk muhaddits perempuan yang merawikan hadis dari Rasulullah secara langsung dan penuh intimasi.
Aspek Agama
Masyarakat Arab pra-Islam atau biasa disebut kaum jahiliah, memiliki tradisi adopsi yang bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi yang telah berlangsung lama dan terjadi turun-temurun itu bernama bid’atut-tabanni. Praktiknya, mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, serta melimpahkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban yang berlaku bagi anak kandung. Padahal, syariat Islam tidak mengamini praktik adopsi seperti itu.
Pada masa sebelum ditahbiskan sebagai Nabi, Allah Swt. juga menakdirkan Nabi Muhammad mengadopsi Zaid bin Haritsah. Itu sebabnya orang-orang jamak memanggil anak itu dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kemudian, Nabi menikahkan anak angkatnya tersebut dengan putri bibinya, Zainab binti Jahsy al-Asadiyah. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan keduanya kandas di tengah jalan. Begitu pula dengan panggilan Zaid bin Muhammad, tidak lagi diperbolehkan selepas turunnya wahyu, yaitu QS. Al-Ahzab (33) ayat 5.
Setelah beberapa lama berselang Allah Swt. memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, yang notabene mantan istri anak-angkatnya. Berdasarkan tradisi adopsi yang berlaku saat itu, pernikahan antara Nabi dan Zainab tidak diperkenankan. Tak ayal, orang-orang jahiliah ketika itu ramai membicarakan pernikahan tersebut. Atas itu Allah Swt. menguatkan hati Rasulullah dengan menurunkan ayat 37 dari surah Al-Ahzab berikut ini.
… dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.
Melalui ayat ini, tersingkaplah alasan Nabi menikahi Zainab adalah murni atas nama agama, yakni atas perintah Allah Swt. dalam rangka menganulir tradisi adopsi ala masyarakat Arab jahiliah tersebut.
Aspek Sosial
Aspek yang ketiga ini tampak jelas dalam pernikahan Nabi dengan putri dari kedua sahabat karibnya. Adalah Siti Aisyah binti sayidina Abu Bakar al-Shiddiq dan Siti Hafshah binti sayidina Umar al-Faruq. Mereka berdua sahabat terkemuka dengan loyalitas ganting terhadap perjuangan dakwah Nabi. Dengan mempersunting anak kesayangan mereka, maka hubungan sosial Nabi bersama mereka bertambah erat, kuat, dan akrab.
Begitu juga sebaliknya, pernikahan tersebut menjadi kemuliaan atau keistimewaan tersendiri bagi dua tokoh khulafaurasyidin itu, karena mereka jadi punya hubungan semenda dengan Rasulullah. Sama halnya dengan dua tokoh khulafaurasyidin yang lain, yaitu sayidina Utsman bin ‘Affan dan sayidina ‘Ali bin Abu Thalib. Keduanya juga merasa terberkati, karena telah diambil mantu oleh Rasulullah.
Aspek Politik
Diakui atau tidak, pernikahan menjadi medium efektif memuluskan jalan dakwah Islam pada masa itu. Siasat Nabi menikahi putri para pemuka kabilah-kabilah yang selama ini keras menentang dakwahnya, terbukti berhasil menjinakkan hati mereka. Hingga akhirnya mereka kemudian berbondong-bondong masuk Islam.
Setidaknya Syekh Ali al-Shabuni menyebutkan tiga sosok perempuan yang diperistri oleh Nabi secara politis. Pertama, Juwairiyah binti al-Harits (kepala suku Yahudi-Musthaliq). Kedua, Shafiyah binti Huyay (kepala suku Yahudi-Quraizhah). Ketiga, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan (salah satu pemuka Kaum Quraisy-Makkah).
Alhasil, sama sekali bukan karena gelora syahwat Nabi berpoligami. Apa pun ahwal kehidupan Nabi tidak ada tujuan lain selain untuk kejayaan Islam serta sebagai teladan bagi umatnya, tidak terkecuali perihal alasan Nabi berpoligami.
Maksudnya, bahwa poligami Nabi mengandung teladan bagaimana cara memperlakukan istri yang berusia jauh lebih tua; bagaimana cara memperlakukan istri yang masih berdarah muda; bagaimana cara memperlakukan istri yang berasal dari strata sosial lebih rendah; bagaimana cara memperlakukan istri yang notabene mualaf dari agama lamanya; bagaimana cara memperlakukan istri-istri yang berlatar suku-bangsa berbeda dan seterusnya.
Demikianlah spirit atau hikmah yang seyogianya dapat dipahami dari poligami Nabi. Bukan malah poligami Nabi dimanipulasi sebagai dalih atau justifikasi atas selera berpoligami. Justru tindakan begini yang melanggengkan stigma negatif atas Rasulullah dan syariat Islam. ***
*AHMAD RIJALUL FIKRI, Mahasantri Ma’had Aly dan Mahasiswa S-2 PPs Universitas Ibrahimy Situbondo, Jawa Timur.