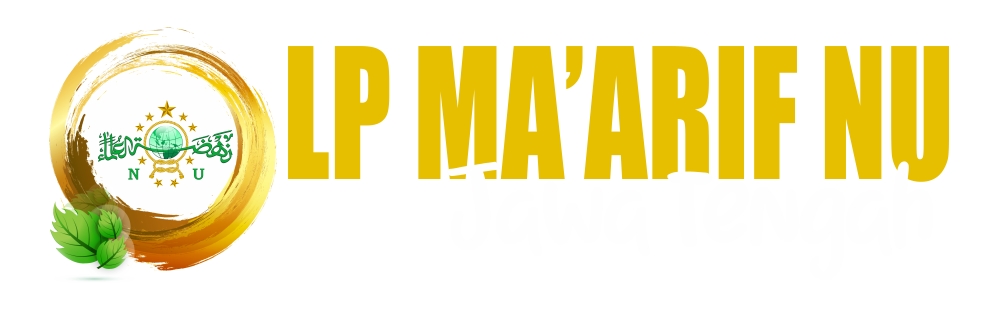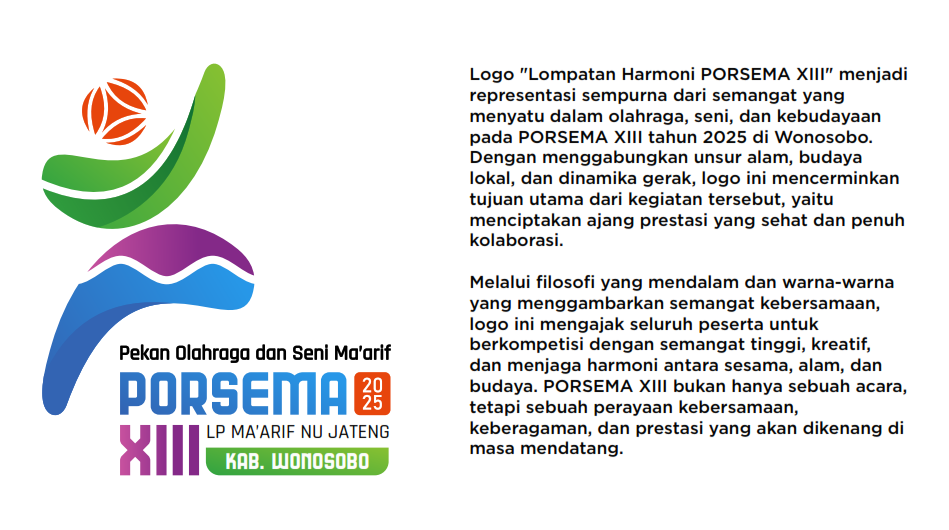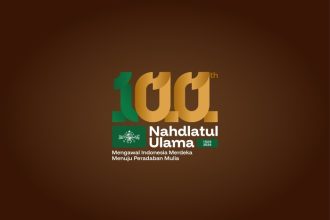Oleh Gunoto Saparie
Di suatu pagi yang tenang di sebuah desa di Madura, D. Zawawi Imron menulis puisi tentang ibunya. Ia tidak menyebut Tuhan secara gamblang, tetapi dalam setiap baitnya, kita seperti mendengar seorang anak kecil mengaji sambil menahan tangis. Kesusastraan Indonesia modern, meskipun telah menjauh dari pesantren dan surau sebagai pusat gravitasi, masih menyimpan denyut Islam yang samar tetapi dalam—seperti gema adzan yang tidak selalu terdengar, tetapi selalu ada.
Islam dalam kesusastraan Indonesia modern bukanlah khotbah. Ia lebih seperti kabut: hadir tanpa bentuk, menyusup ke sela-sela kata, dan menyampaikan keyakinan yang lebih subtil daripada seruan mimbar. Ia tidak sekadar bicara tentang syariat, tetapi tentang pengalaman eksistensial menjadi manusia yang percaya—dan yang meragukan, kadang-kadang, tapi tetap mencari.
Lihatlah puisi-puisi Abdul Hadi W.M., misalnya. Ia menulis seperti seorang sufi yang tersesat di lorong perpustakaan. Bahasanya mistik, kiasannya padat, dan imajinasinya sering melampaui batas kitab dan fiqih. Dalam puisinya, Islam adalah jalan kesunyian: “aku lewati malam dan cahaya bersamamu / yang tak bernama, yang tak bertempat.” Di sini, Islam hadir bukan sebagai sistem sosial, tapi sebagai ruang kontemplasi. Ia berjarak dari retorika, tetapi dekat dengan batin.
- Iklan -
Seperti puisi berjudul “Tuhan, Kita Begitu Dekat” karya Abdul Hadi di bawah ini.
Tuhan
Kita begitu dekat
Sebagai api dengan panas
Aku panas dalam apimu
Tuhan
Kita begitu dekat
Seperti kain dengan kapas
Aku kapas dalam kainmu
Tuhan
Kita begitu dekat
Seperti angin dengan arahnya
Kita begitu dekat
Dalam gelap
Kini aku nyala
Pada lampu padammu
Demikian juga Emha Ainun Nadjib. Lebih flamboyan. Lebih teatrikal. Tapi tetap seorang penyair yang percaya bahwa Tuhan harus dibela—bukan dengan pedang, melainkan dengan laku dan kata. Dalam puisinya, “Tuhan pun Bertanya”, ia mengajak pembaca berdebat dengan Yang Mahakuasa. Sebuah keberanian yang khas dari seorang santri yang membaca Nietzsche secara diam-diam. Ia menjadikan Islam bukan pagar, tapi jendela. Kita diajak melihat dunia, dengan Al-Qur’an di tangan kiri dan novel Dostoyevsky di tangan kanan.
Simaklah puisi berjudul “Tahajjud Cintaku” karya Emha di bawah ini.
Mahaanggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan
Mahaagung ia yang mustahil menganugerahkan keburukan
Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya
Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya takditerima
Kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita
Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara
Katakan kepadaku adakah neraka itu kufur dan durhaka
Sedang bagi keadilan hukum ia menyediakan dirinya
Ke mana pun memandang yang tampak ialah kebenaran
Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang
Mahaanggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan
Suapi ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan
Tuhan kekasihku tak mengajari apa pun kecuali cinta
Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hatinya
Ada juga Mustofa Bisri. Gus Mus. Dalam puisinya, Islam sering tampil dalam wujud paling lembut: doa ibu, linangan air mata, dan kelakar santri yang jenaka. Puisinya mengingatkan bahwa iman bukan sekadar akidah, tetapi juga rasa. Kesedihan, kerinduan, cinta—semuanya bisa menjadi jalan ke Tuhan. Dalam puisi-puisinya, Islam bukan perkara menang dan kalah, tapi bagaimana memahami penderitaan orang lain. Itu sebabnya, Gus Mus menulis puisi seperti menulis surat kepada langit yang sepi.
Bagaimana dengan prosa? Cerpen-cerpen Djamil Suherman atau Muhammad Fudoli lebih banyak bicara tentang tubuh umat: kemiskinan, keterpinggiran, dan pergulatan batin orang kecil dalam menghadapi perubahan zaman. Islam, dalam cerita-cerita mereka, kadang tampak ringkih, kadang keras, tapi selalu hadir sebagai penopang nilai. Mereka menulis bukan untuk menggambarkan surga, tetapi kegelisahan manusia yang ingin mencapainya.
Ali Audah, dengan nada lebih intelektual, membawa narasi Islam ke medan perdebatan ide. Cerpennya tak hanya menyajikan kisah, tetapi juga tafsir. Ia seperti sedang menulis tafsir sosial—tentang bagaimana iman diuji di pasar, di pengadilan, dan di ruang keluarga.
Apakah penting identitas Islam dalam kesusastraan Indonesia modern?
Barangkali pertanyaan itu bisa dibalik: Mungkinkah kesusastraan Indonesia modern lepas sama sekali dari Islam, dalam pengertian kultural? Islam bukan hanya agama mayoritas; ia adalah lanskap sejarah, bahasa, dan memori kolektif yang membentuk imajinasi kita. Bahkan penyair sekuler pun, tanpa disadari, sedang berdialog dengan sesuatu yang Islam juga telah ikut membentuk.
Islam di tangan para sastrawan bukan semata sistem nilai, tetapi bahan baku estetika. Ia bisa menjadi metafora, kritik sosial, atau alat untuk menyelami absurditas hidup. Dalam karya mereka, Tuhan sering hadir sebagai pertanyaan, bukan jawaban. Dan mungkin di situlah kesusastraan menemukan keutamaannya—bukan untuk mengafirmasi iman, tetapi untuk menggugatnya, mengelusnya, menertawakannya, lalu diam.
Seperti doa yang tak pernah selesai.
*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Satupena Jawa Tengah