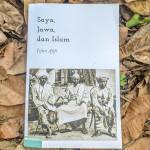Oleh : Era Ari Astanto
Aku tidak tahu kapan ibu mulai bicara dengan tembok. Barangkali sejak aku menikah. Barangkali jauh sebelumnya. Yang aku tahu, sejak aku keluar dari rumah kecil itu untuk menjadi istri, dinding-dinding di rumah ibu menjadi saksi bisu suara-suara yang tak pernah aku dengar lagi.
“Ibu sudah tua, Ni,” katanya suatu sore ketika aku sedang menyiapkan barang-barangku. Suaranya serak, seperti tanah kering yang retak menahan hujan. “Kalau kau pergi, ibu bicara pada siapa lagi?”
Aku tertawa kecil, mencoba menepis kepedihan yang perlahan merayap. “Ada radio, Bu. Dengarkan ustaz-ustaz di sana. Nanti ibu juga lupa kalau aku tidak ada.”
- Iklan -
Pernyataanku tak seindah maksudnya. Radio? Apa itu layak menggantikan aku? Tetapi, aku menghibur diri bahwa itulah takdir perempuan—meninggalkan rumah yang membesarkan, demi membangun rumah tangga sendiri.
Hari itu adalah hari terakhir aku mendengar suara ibu tanpa jeda. Hari terakhir aku melihat senyumnya yang tulus, sebelum waktu menjadikannya siluet yang perlahan pudar di ingatan.
*
Dulu, di sebuah pagi yang berembun, aku pernah bertanya pada ibu, ketika ia tengah mengurai tikar pandan yang baru saja selesai dijemur.
“Bu, katanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi, kalau perempuan menikah, bukankah dia harus patuh pada suaminya?”
Ibu berhenti, menatapku dengan mata yang selalu tampak menyimpan rahasia. “Kau tidak akan memahami jawabannya sekarang, Ni,” katanya pelan, sambil mengusap rambutku. “Tapi nanti, ketika waktunya tiba, kau akan tahu bahwa surga itu bukan soal siapa yang kau patuhi, tapi pada siapa kau menyerahkan hatimu.”
Aku tidak mengerti apa yang dimaksud ibu saat itu.
“Suami itu titipan, Ni. Ibu, rumah ini, masa kecilmu—semua ini asalmu. Jangan pernah lupa dari mana kau berasal.”
*
Sore ini, di pelataran surau, aku duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, menunggu suamiku selesai berjamaah. Udara sore membawa aroma tanah basah, bercampur dengan wangi kapur barus dari kain-kain putih yang bergelantungan di tiang jemuran. Aku memandang jalan, berharap menemukan sesuatu yang menarik untuk mengisi kekosongan pikiranku.
Yang datang bukanlah jawaban, melainkan perempuan tua, bungkuk, dengan bungkusan plastik robek di tangan.
“Ibu, apa kabar?” tanyaku. Entah kenapa aku memanggilnya begitu, meskipun aku tahu bukan dia ibuku.
Ia berhenti di depanku, memandangku dengan mata yang keruh, basah oleh air yang belum sempat jatuh. “Kabar baik, Nak. Tapi ibu tak yakin berkabar baik, anak-anak ibu pergi semua.”
Kata-katanya menghujam dadaku seperti duri yang tumbuh diam-diam.
“Ibu bicara tentang anak ibu, bukan saya,” sahutku, mencoba meluruskan maksudnya.
Perempuan tua itu hanya tertawa kecil, lalu melangkah pergi. Namun, tawa itu terus terngiang di telingaku, bahkan ketika azan maghrib bergema.
*
Aku mengaduk gulai ayam di dapur rumah kami. Suamiku duduk di ruang tamu, membaca koran seperti biasa.
“Kau lupa mencuci sepatuku di depan,” katanya, tanpa mengalihkan pandangan dari halaman berita politik.
Aku diam saja, mengaduk pelan. Kupikir, jika aku menunggu cukup lama, ia akan lupa tentang sepatu itu. Tetapi sepatu itu lebih dari sekadar alas kaki. Itu adalah simbol baginya: apakah aku istri yang patuh atau hanya perempuan yang gagal memahami kodratnya.
“Istri itu harus menuruti suami. Jangan sampai kelak aku tidak ridha. Sebab, kau tahu artinya, kan? Neraka menunggumu,” katanya suatu kali, dengan nada seolah-olah ia sedang membaca kitab suci.
Aku mencoba percaya. Tapi malam itu, suara ibu lebih keras dari biasanya.
“Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan suami, Ni,” suara itu bergema di dalam kepalaku.
Aku menghentikan adukan sendokku. Ketika aku menoleh, gulai ayamku sudah gosong.
*
Setelah lima tahun, aku pulang ke rumah ibu tanpa suamiku. Hatiku dipenuhi kegelisahan yang membungkus setiap langkahku. Aku mengetuk pintu, tetapi yang membukakan adalah seorang perempuan muda yang asing.
“Maaf, Anda siapa?”
Aku tercekat. Pertanyaan itu menusuk lebih tajam daripada yang aku bayangkan.
“Rumah ini rumah ibu saya,” jawabku cepat, mencoba menguasai diri.
“Oh, yang dulu tinggal di sini? Kami membelinya tahun lalu.”
Aku terdiam, membiarkan udara sore menampar wajahku.
“Ibu saya tinggal di mana sekarang?” tanyaku akhirnya, dengan suara yang hampir pecah.
Perempuan itu menggeleng pelan. “Maaf, saya tidak tahu. Waktu kami beli, rumah ini kosong. Kami membeli melalui perantara.”
Kosong. Kata itu berputar-putar di kepalaku seperti lonceng kematian. Aku berdiri di depan rumah itu, memandangi tembok-tembok yang dulu menjadi tempat ibu bersandar, berbicara, menangis. Kini, tembok itu membisu, seolah lupa pernah ada kehidupan antara aku dan ibu di dalamnya.
Aku melangkah menjauh dari rumah itu dengan hati yang berdesir. Setiap langkah terasa seperti menggiringku ke jurang yang lebih dalam. Di pojok gang, aku berhenti, mencoba mengendalikan napas. Pandanganku terantuk pada seorang lelaki tua yang duduk di warung kecil. Ia memandangku lama, seperti mengenali wajahku.
“Ani, ya?” tanyanya.
Aku mengangguk, meskipun hatiku tak yakin siapa dia.
“Aku teman ibumu dulu,” katanya, suaranya berat oleh beban waktu. “Waktu ibumu sakit, aku pernah melihat dia berjalan ke pasar sendirian. Kau tahu apa yang dia beli?”
Aku menggeleng pelan.
“Sarung tangan. Dia bilang, tangannya tak cukup kuat lagi untuk mencuci lantai. Tapi aku tahu itu bukan soal kekuatan. Dia terlalu rindu padamu. Dia pikir, dengan bekerja lebih keras, pikirannya akan lupa.”
Kata-kata itu menghujam hatiku seperti batu yang jatuh di permukaan air. Wajah ibu membayang, tangannya yang dulu kokoh kini tampak gemetar dalam ingatanku.
“Mengapa tak ada yang memberitahuku?” tanyaku, lebih pada diriku sendiri daripada padanya.
“Karena ibumu tak pernah mau mengeluh. Katanya, anak perempuan punya surga baru yang harus dijaga.”
Aku terus melangkah, mengenang apa pun tentang ibu hingga aku tiba di depan sebuah masjid. Sejenak, aku menyapukan mata ke setiap bagian beranda masjid. Di masjid, aku menemukan ibu-ibu yang dulu sering duduk bersama ibu setiap sore. Ia menyambutku dengan senyum tipis.
“Ibumu sekarang tinggal di panti, Nak,” katanya pelan, seolah takut aku akan menangis di tempat.
“Kenapa?”
“Ia bilang, anak-anaknya terlalu sibuk untuknya. Tapi aku tahu, ia tidak ingin menjadi beban.”
Aku tidak menangis. Tidak di depan perempuan itu. Tapi dalam perjalanan pulang, tangisku pecah, menggema di dalam tubuhku yang kosong.
*
Di panti, aku menemukan ibu sedang menyapu halaman. Rambutnya memutih semua. Punggungnya lebih bungkuk daripada yang aku ingat. Ia berhenti ketika melihatku, memandangku lama seperti mencoba mengenali siapa aku.
“Kamu siapa?” tanyanya akhirnya, suaranya lemah.
Aku merasa ada jurang yang terbentang di antara kami.
“Bu, ini Ani. Anak ibu.”
Ia mengangguk perlahan, tapi matanya tetap menyimpan keraguan. Tangannya gemetar ketika menyentuh pipiku. “Ani? Oh, Ani… Maaf, ibu lupa. Aku tak melihatmu terlalu lama.”
Air mataku nyaris mengalir, tetapi aku menahannya, takut ibu akan melihat.
*
Aku mengajak ibu kembali ke rumahku. Suamiku menyambut dengan wajah datar, tanpa sapaan. Malam itu, kami makan malam bertiga dalam diam yang lebih berat dari keheningan.
Setelah makan, ibu memintaku duduk bersamanya di teras.
“Ibu senang akhirnya bisa melihatmu lagi, Nak,” katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. “Meskipun hanya untuk waktu yang sebentar.”
“Sebentar? Ibu akan tinggal di sini selamanya,” kataku, mencoba meyakinkannya.
Ibu hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip doa yang lelah. “Ibu tahu, Nak. Kau akan pergi lagi. Kau harus ingat satu hal: suami itu tempatmu berlabuh, tapi ibu adalah tempatmu berasal.”
Kata-katanya menusukku seperti belati.
*
Dua minggu kemudian, ibu meninggal di rumahku. Aku memandang tubuhnya yang terbujur kaku, merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku, sesuatu yang tidak akan pernah kembali.
“Aku akan mengubur ibu di sini,” kataku pada suamiku.
Ia memandangku dengan wajah tanpa ekspresi, seperti sedang menilai keputusanku.
“Terserah kau,” katanya akhirnya.
Di pemakaman, aku berdiri di samping nisan ibu, memandangi namanya yang terukir di atas batu. Aku merasa tubuhku seperti batu itu: kaku, dingin, tak bernyawa.
Ketika aku beranjak pergi, suara ibu terdengar lagi di dalam kepalaku, lembut, seperti bisikan angin.
Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kata-kata itu terus mengikuti setiap detak jantungku.
Malam itu, suamiku bertanya, “Kenapa kau menangis di depan makam ibumu tadi?”
Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawaban. Tapi yang aku temukan hanyalah kelelahan yang tak pernah ia pahami.
“Ibu adalah surga,” kataku akhirnya.
Ia tertawa kecil, seolah aku sedang bercanda. “Tapi sekarang ibu sudah tiada.”
Aku tersenyum pahit. “Surga tidak pernah tiada, hanya kadang kita lupa di mana mencarinya.”
Ia terdiam. Untuk pertama kali, aku merasa ia tidak punya jawaban untukku.
*
Aku tidak tahu kapan suara ibu berhenti bergema di dalam kepalaku. Yang tersisa hanyalah doa yang panjang untuknya, merambat dalam diam. Aku tahu, surga ada di sana—di bawah telapak kaki ibu, dan aku telah menginjaknya tanpa sadar.
Era Ari Astanto, penyuka bika ambon ini lahir di Boyolali. Saat ini bekerja di sebuah penerbitan buku pelajaran di Solo dan aktif di MYF Randhu Jembagar Boyolali. Novel terbarunya Sesepuh dan Sebuah Dukuh (Diomedia).