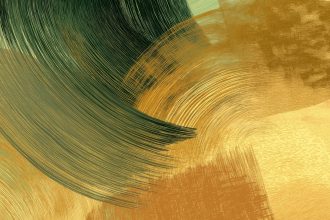Oleh Arinda Sari
Aku tersudut di sini. Di emper toko alat tulis terbesar di kotaku. Berbaur bersama debu musim kemarau, suara kernet yang melolong-lolong nyaring, aroma keringat orang-orang yang berkelebat lewat, dan bau busuk dari got mampet di dekat emper. Seragam pressbody-ku sudah kucel, rambut kuikat seadanya dengan jepit plastik murahan berbentuk kupu-kupu. Kunaikkan kaos kaki hingga selutut berharap agar mata-mata nakal itu tak semakin melotot. Yeah, itu masih mending daripada mengumpankan diri pada penuhnya angkot, lalu harus rela menjadi sasaran empuk colak-colek sabun yang menjijikkan itu. Oleh karenanya aku lebih suka menunggu angkot kosong meski harus telat sampai di rumah.
Di usiaku yang ke-16 ini aku sering mengkhayalkan seandainya ayah membelikanku sebuah motor. Motor second pun tak masalah asal bisa jalan. Sayang, permintaanku belum dikabulkan. Sungguh, keinginanku itu bukan tanpa alasan. Bukan sekadar ingin gaya-gayaan. Aku tak suka berada dalam kerumunan, bercampur baur laki-laki dan perempuan serupa pepes teri dalam kukusan. Panas, gerah, dan selalu ada secuil kesempatan dan kesempitan bagi tangan-tangan iseng.
Ketika keluhanku itu kuutarakan pada Nania beberapa hari lalu, ia tersenyum. “Kayaknya memang sudah saatnya kita melindungi diri dengan jilbab,” tukasnya.
- Iklan -
Hah? Jilbab? Kita?
Loe aja kali! Protesku dalam hati. Eh, tapi bukankah gadis itu memberi solusi? Logis juga sebenarnya. Tak serta merta menyalahkan mata orang yang menatap jalang, tapi menjadi bagian orang yang tidak menjadi ‘sebab’ liarnya pandangan mata itu.
Lantas tiga hari kemudian, kerongkonganku tercekat—tak bisa minum sebab ini bulan Ramadhan—melihatnya melangkah anggun di koridor kelas. Rambut smoothing bak iklan sampo itu telah tertutup oleh kerudung putih polos dengan renda warna biru muda di tepi-tepinya. Bros mungil berbentuk bunga lili tersemat, memberi kesan rapi. Postur tubuh jangkungnya membuat ia semakin memesona. Ia serupa bidadari. Semua mata menatapnya melangkah seakan gerakan slow motion. Jilbabnya melambai ringan. Ia telah mengucapkan selamat tinggal pada seragam lengan pendek lengan ketat dan rok selutut yang makin hari makin naik saja.
Nania. Ah, ternyata kalimatnya kemarin tak hanya isapan jempol. Ia serius. Dan perubahan itu terpampang nyata di hadapanku. Hatiku berdesir.
Nania. Rasanya sulit mempercayai sepasang mataku sendiri—semoga mataku tidak benar-benar rabun. Tak ada angin, tiada hujan. Apa gerangan yang membuat ia tiba-tiba berubah? Ataukah memang sudah lama ia merencanakan lalu merealisasikan di bulan mulia ini? Apa motivasi terbesarnya? Ingin kubelah batok kepalanya hingga menemukan alasan terkuatnya untuk memutuskan mengenakan tutup kepala itu.
Nania. Rasanya baru kemarin kami bercekakak-cekikik membicarakan kakak kelas cute yang ternyata aktivis rohis, atau saat berdebat tentang salon X atau Y yang paling oke untuk rebonding rambut, atau saat kami berburu celana jeans semi ketat dengan model cut bray yang sedang trending pada zaman itu.
Ah, tak pernah aku se-kepo ini padanya.
Lambat laun aku menyingkir. Mencoba tahu diri. Siapa tahu Nania malu memiliki teman sepertiku yang masih mengumbar aurat, masih boncengan sama cowok, juga membaca zodiak di majalah remaja. Dalam pandanganku, cewek yang memutuskan berjilbab itu adalah sosok yang sedang otw menyempurnakan diri. Sopan, tidak suka berkoar-koar, kalem, sederhana, pintar mengaji, aktivis remaja masjid, dan tidak pacaran. Kemungkinan jumlahnya satu berbanding seratus bahkan seribu mengingat gadis seusia kami seumpama mawar yang sedang mekar-mekarnya.
Aku semakin tersudut, manakala beberapa teman dari kelas lain juga merubah total penampilannya. Dari yang terkesan urakan menjadi anggun berwibawa. Dari yang mini-mini menjadi terhijab sempurna. Aku masih jauh dari itu. Jauh sekali. Aku seperti anak bebek yang tersuruk-suruk belepotan mengejar induknya menuju kolam.
Di puncak rasa ingintahuku yang meletup-letup, kutanya pada kak Zein, seorang aktivis masjid. Menurutku ia rohis keren dan gaul. Asyik diajak bertukar pikiran.
“Jilbab itu wajib bagi muslimah yang sudah akil baligh.”
Hanya sepuluh kata, delapan belas suku kata, dan empat puluh lima huruf tersebut yang membuatku terkesiap, diam, kehabisan kata di hadapannya. Kalimat itu sakti, bertenaga, membius hingga membuatku teramat malu. Menjerembabkanku pada kenyataan paling getir bahwa aku tahu tapi tak mau tahu. Aku adalah si kutu buku yang sudah khatam segala genre novel, ensiklopedia, segala rupa buku-buku. Pernah kubaca ayat tentang perintah berjilbab tapi hanya kuanggap sepintas lalu. Persis ketika ada seekor lalat hinggap di hidungku lalu kuusir sekenanya dengan mengibaskan tangan. Lalat itu pun pergi dengan mudahnya.
Hari-hari setelahnya aku menangisi diri. Miris dan sedih manakala melihat pantulan wajahku di cermin. Rambut indah hitam membingkai seraut wajah putih tanpa jerawat. Alis serupa semut berbaris yang susah payah dibentuk dengan dikerik atau dicabut. Kulit mulus berhias bulu-bulu halus yang kata teman-teman cowok, so seksi. Untuk apa itu semua? Apakah setiap inci tubuhku yang terbuka dan mengundang decak kagum, berpotensi menanamkan dosa? Apakah aku akan tetap merutuk sebal pada mata-mata nakal jika akulah sebenarnya yang memancing tatapan haram itu? Apakah jika nanti aku berjilbab, hatiku bisa berlepas dari ujib, riya, sombong, dan buruk sangka?
Aku tergugu. Berat. Berat sekali ya Allah.
Hidayah itu sepertinya masih jauh dan enggan menyapaku padahal aku selalu jatuh cinta pada ilmu. Nyatanya banyaknya ilmu, tak lantas membuatku menjadi bijak dan menemukan cahaya petunjuk. Aku seperti terjebak dalam ruang sempit lift, seorang diri, tergeragap, meraba-raba panik mencari cahaya dan jalan keluar. Benarkah jilbab menjadi solusi terbaik seperti yang dikatakan Nania tempo hari?
Namun, jika tak menutup aurat hari ini, lalu kapan? Sedang umur tak ada yang tahu. Alangkah memilukan jika hijab pertama seorang perempuan adalah lembaran kain kafan. Mau tak mau, suka tak suka, sudah kewajiban bahwa aurat yang harus ditutup. Mumpung ada kesempatan. Ada kalanya, harus ada paksaan untuk tujuan kebaikan.
Bismillah. Kukenakan pakaian panjangku. Plus jilbab segi empat rawis yang menurutku mirip taplak meja. Tampak sedikit aneh di awal. Aku kehilangan poni anak-anak rambut yang menjuntai hingga pundak, tapi bukankah malah rapi?
Gerah? Tentu saja. Matahari pukul dua belas siang begitu terik membakar. Alhamdulillah tak lagi membakar kulitku sehingga aku tak perlu repot-repot mengoleskan sunblock di wajah, lengan, dan kakiku. Bukankah malah bisa berhemat?
Opini orang? Sangat beragam. Kalau keluargaku support, tapi belum sohib ajaib-ajaib itu. Dari yang terperangah tak percaya, heboh, sampai mengira aku kesambet. Aku sedikit bisa menterjemahkan apa yang terlintas di kepala mereka tentang jilbab: kuno, kayak emak-emak, nggak gaul, nggak asik! Tapi aku bersyukur masih ada yang mengucap selamat dan mendoakan. Aku harus bersabar melalui proses panjang ini dengan segala tantangan di depan. Yah, meski baru tahap menggugurkan kewajiban.
Dengan hijab yang kupakai ini, ada tanggung jawab, beban, sekaligus amanah berat di pundak. Aku takut jilbabku hanyalah akan mencoreng nama baikku dan orangtuaku jika aku sembrono. Aku malu sebab masih merasa ‘berat’ mengenakannya jika berada di lingkungan rumah. Ribet memang, kalau ke warung harus ganti. Kalau ada tamu, langsung belingsatan masuk ke dalam kamar. Aku kesal sebab bacaan qur’anku tak kunjung membaik. Aku masih kelepasan ngakak, nyemil pakai tangan kiri, bersalaman sama non mahram, berdebat dengan cowok yang rese. Aku gagap ketika harus mengubah kebiasaan, meninggalkan apa yang kusukai, demi menyesuaikan diri dengan jilbabku. Ternyata, semua tak semudah yang kubayangkan. Aku kelelahan
“Kita ini manusia, bukan malaikat,” ucap Nania. “Wajar melakukan kesalahan.”
“Allah menyediakan ruang bagi manusia untuk berikhtiar. Sabar di tiap jengkal prosesnya. Jangan menghukum dirimu terlalu berat.” Kali ini suara kak Zein terngiang, memantul-mantul di lorong hatiku yang senyap. Ingin kumenyangkal dengan argumenku tapi mulutku terkunci. Jelaslah sudah bahwa aku mengalami ketakutan berlebihan atas penilaian orang kalau cewek berjilbab tidak patut begini begitu, tak elok, tak sinkron antara perilaku dan jilbab, memalukan dan sebagainya. Masih diribetkan tentang pandangan manusia. Hijrahku belum menyeluruh. Ternyata ada yang harus kuubah yaitu niatku yang belum 100% karena Allah. Belum lillahi ta’ala.
Ya, Nania dan Kak Zein benar. Aku beruntung memiliki mereka yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Mengingatkan bahwa kita harus terus memperbaiki diri, memantaskan diri menjadi hamba-Nya yang beriman. Kugigit iman itu dengan geraham, takkan melepaskannya sampai kapan pun.
Belum genap setahun, ketika aku sudah mulai istiqomah dengan jilbabku, dengan perubahan-perubahan kecil yang bisa kubilang signifikan dengan ibadahku, tatkala aku harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dunia mendadak berhenti senada dengan detak jantungku. Kugumamkan istighfar dengan gumpalan rasa campur aduk hingga membuat tubuhku bergetar. Kucari-cari seribu alasan agar hati dan pikiran tak sempat secuilpun mentunaskan prasangka. Aku kembali tersudut. Dua insan sedang berboncengan mesra di tengah gerimis bulan November.
Mereka, Nania dan Kak Zein. (*)
ARINDA SARI, penulis buku, blogger. Tengah merintis gubug baca Arinda Shafa. Alumni bahasa dan sastra Inggris UNNES. Bergiat di komunitas Penulis Ambarawa (Penarawa). Tinggal di Semarang.