Cerpen Imam Syafi’i
Kemarin saya dan Rustam bermain gasing beluluk di halaman dekat langgar. Musim hujan yang biasanya membawa angin kencang sering merontokkan calon buah kelapa itu ke tanah. Angin kencang adalah mimpi buruk bagi para penderes. Selain batang kelapa yang licin saat dipanjat, air nira pun menjadi lebih masam dan buruk kualitasnya. Mimpi buruk itu tentu tidak berlaku bagi kami. Musim penghujan justru momen untuk memanen kesenangan. Selain puluhan beluluk yang berguguran, tiap musim hujan, mata air dadakan muncul di celah-celah bebatuan di kebun rumah kami. Tidak jarang, muncul juga kalen-kalen di sepanjang jalan berbatu yang menjadi akses satu-satunya di dusun kami. Biasanya, saya, Rustam, Rudio, dan Sardi membuat sumur-sumuran kecil dari mata air itu, atau membendungnya menjadi sebuah danau mini. Untuk rakitnya, kami buat dari batang daun singkong yang dijejer-jejer dan ditusuk dengan lidi di kedua ujungnya.
Tidak jarang, teman-teman perempuan saya seperti Wasri, Rahayu, dan Tarti juga ikut bermain. Mereka sering membuat pawon-pawonan dan membawa wajan kecil untuk masak-masakan. Berbeda dengan set mainan masak-masakan ala anak kota, masak-masakan kami benar-benar seperti memasak sungguhan. Biasanya Wasri kebagian membuat pawon, Rahayu mendapat bagian mencari daun singkong untuk dimasak dan Tarti ditunjuk untuk membawa wajan dan bumbu dapur karena kebetulan Emaknya membuka warung kecil di depan rumah. Adapun saya dan teman-teman laki-laki mendapat tugas mencari kayu bakar dan menyalakan api dengan klari.
Sore ini, kami memutuskan membendung aliran air yang keluar dari celah-celah batu di depan rumah Yung Kitam. Kami memang terbiasa memanggil wanita tua dengan sebutan ‘biyung’. Aliran mata air yang membentuk kalen di depan rumah Yun Kitam cukup deras dan jernih. Terdapat pula sebuah cekungan yang terbentuk dari bekas galian tanah sehingga sangat cocok untuk dijadikan bendungan. Hampir satu jam kami belepotan lumpur. Belum jernih benar memang airnya, tapi sebentar lagi pasti akan jernih.
- Iklan -
Melihat kami bermain-main di depan rumahnya, Yung Kitam datang menghampiri anak-anak sambil membawa sepiring timusan yang baru matang. Beberapa gelas dan teko kecil dari kuningan juga ikut dikeluarkan.
“Ayo, kalian cuci tangan dulu. Aku sudah bikin timusan buat kalian,” ucap Yung Kitam.
Saya, Rustam, Rudio dan Sardi serentak meringis. Alasan kami membuat bendungan di depan rumah Yung Kitam bukan hanya karena airnya deras dan cocok untuk bendungan, tapi tentu saja kami berpikir untuk mendapat jajanan gratis. Sudah jadi rahasia umum kalau Yung Kitam gemar sekali memberi jajanan kepada anak-anak yang bermain di depan rumahnya. Kabarnya, Yung Kitam memang suka dengan anak-anak.
“Lho, kok pada diam saja begitu. Cepat sana pada cuci tangan.”
Kami beranjak untuk mencuci tangan di bendungan yang baru kami buat.
“Eee …, jangan cuci tangan di situ. Airnya masih kotor,” ujar Yung Kitam. “Cuci tangan di padasan belakang,” Yung Kitam menunjuk padasan miliknya.
Kami berlari ke arah padasan dan kembali beberapa saat kemudian. Yung Kitam sudah menuangkan teh ke dalam empat cangkir kecil. “Ayo, dimakan. Dihabiskan saja kalau kalian suka.”
“Terima kasih, Yung,” ucap kami serentak.
Tanpa malu-malu, saya dan teman-teman mengambil timusan yang kelihatan enak itu. Rudio dan Sardi sempat berebut karena mengambil timusan yang sama.
Yung Kitam hanya tersenyum. “Sudah, jangan rebutan. Itu masih banyak, kok. Kalau kalian suka, besok aku bikin lagi.”
“Beneran, Yung?” ucap Rudio dengan mata berbinar.
Yung Kitam mengangguk. “Iya, asal kalian habiskan kalau nanti aku bikin lagi.”
“Pasti, Yung. Pasti kami habiskan,” ucap Rustam sambil menyambar satu timusan lagi. Padahal timusan yang ada di mulutnya saja belum habis.
“Yung …,” ucap Rustam.
“Iya?”
“Yunge tidak marah kami membendung air seperti ini?”
“Tentu saja tidak. Buat apa aku marah?”
“Anu, Yung, kemarin kami bikin sumur-sumuran di dekat kebun Wak Lihun, terus kami dimarahi karena katanya ayam Wak Lihun mati terperosok dan akhirnya mengapung di sumur-sumuran kami.”
Yung Kitam tertawa untuk beberapa saat. “Tidak. Aku tidak akan marah. Lagipula aku sudah lama tidak punya ayam. Sudah dijual sama si Darso.”
Kami merasa lega mendengarnya.
Yung Kitam bangkit meninggalkan kami untuk membereskan rumah dan menyapu halaman.
“Kalau sudah habis, taruh saja di lincak depan, ya?”
“Nggih, Yung.”
Kami kembali asyik menikmati timus buatan Yung Kitam.
“Yung kitam baik hati, ya?” Ucap Rudio.
Kami mengangguk. Ungkapan Yung Kitam baik hati memang sering terdengar dari mulut anak-anak seusia kami. Tidak satu-dua kali kami mendapat jamuan jajanan yang enak-enak, melainkan hampir setiap kami bermain di depan rumahnya pasti Yung Kitam akan berbaik hati menyediakan makanan. Selain suka memberi makanan, jika sedang tidak sibuk Yung Kitam bahkan mau duduk dan bermain bersama kami. Yung Kitam bahkan dengan senang hati ikut menemani Wasri dan kedua temannya, mengajari mereka bumbu untuk masak-masakan, mengajari kami menyalakan api, juga senang mencicipi hasil dari masak-masakan kami.
“Enak sekali,” komentar Yung Kitam.
“Apa benar enak, Yung?” tanya Wasri dengan mata berbinar. Kebetulan saat itu dia-lah yang memasak.
Yung Kitam mengangguk. “Enak. Hanya kurang asin sedikit,” ujar Yung Kitam sambil terkekeh, “Besok, kalian harus rajin belajar memasak. Supaya kalau nikah nanti, bisa masak yang enak buat suami kalian.”
Wanita tua berumur hampir tujuh puluh tahun itu memang baik hati. Selain telah menjanda lama, Yung Kitam juga hidup sendirian. Sulasti dan Tijah, kedua anak perempuannya lebih memilih hidup bersama suami mereka. Kabarnya Sulastri tinggal di Jakarta bersama dua anaknya. Suaminya pengusaha tekstil sukses di Tanah Abang. Tijah hidup di Lampung mengikuti suaminya yang bekerja sebagai pegawai syahbandar. Kabar yang sampai ke dusun kami, sudah belasan tahun Tijah tidak memiliki anak sehingga memutuskan untuk mengadopsi anak dari salah satu panti asuhan di sana.
Meski hanya tinggal lima ratus kilometer dari dusun kami, kenyataannya Sulastri jarang pulang ke rumah. Mulai dari alasan kesibukan, hingga alasan belum ada waktu senggang. Tijah lebih jarang pulang lagi. Mungkin baru dua atau tiga kali dia pulang sejak pertama kali pergi ke Sumatera, dua puluh tahun yang lalu. Mungkin karena itulah Yung Kitam menyukai anak-anak. Dia merindukan cucunya yang sudah lama bertemu.
Yung Kitam memang baik. Saat musim mangga, sering dia membagikan secara cuma-cuma hasil panennya. Dia meminta anak-anak seusia saya untuk duduk di lincak, sedangkan Yung Kitam memanen sendiri mangga dari pohonnya dengan bantuan galah bambu. Yung Kitam juga berbaik hati mengupaskan mangga dan menyajikannya kepada kami. Mangga akan habis dalam hitungan menit. Meski begitu, Yung Kitam tidak segan mengupaskan mangga lagi dan lagi. Dia tidak akan berhenti sebelum kami mengatakan kalau perut kami sudah sakit akibat kebanyakan makan mangga.
Jika musim rambutan lain lagi. Yung Kitam akan meminta salah satu dari kami memanjatnya, lalu teman yang lain bagian mengumpulkan rambutan yang dijatuhkan kawannya. Pernah kami mengumpulkan sampai satu karung penuh ukuran 100 kilo. Kami memakannya sampai tidak kuat lagi. Pulangnya, Yung Kitam masih membekali kami dengan satu keresek penuh rambutan.
Yung Kitam memang baik. Begitu pula yang saya dengar dari orang para emak di dusun. Yung Kitam sering membagi-bagikan hasil kebun dan sawah miliknya. Mulai dari jagung, kacang panjang, singkong, daun lumbu, sampai melinjo. Dia juga tidak pernah melarang jika tetangga-tetangganya kehabisan bumbu dapur dan meminta kepadanya.
“Gali sendiri di perkarangan belakang, Ras,” ucap Yung Kitam suatu ketika saat Yu Ras meminta kencur.
Kebun Yung Kitam memang luas. Tidak berlebihan jika saya menyebut kebun Yung Kitam adalah yang paling luas di antara kebun milik warga dusun. Tidak hanya luas, tapi tumbuhan di kebun Yung Kitam juga lengkap dan bervariasi. Mulai dari tumbuhan buah-buahan, sayuran kebun, hingga palawija dan bumbu dapur.
***
Ingatan tentang kebaikan Yung Kitam tetap saya bawa sampai saat ini. Setelah lulus SMP, keluarga saya pindah ke ibu kota Kabupaten. Sampai lulus SMA dan akhirnya bekerja di salah satu sekolahan sebagai staf, saya tetap mengingat setiap kebaikan Yung Kitam yang begitu membekas.
Setelah hampir dua puluh tahun meninggalkan dusun, saya rindu sekali ingin mengunjungi teman-teman lama. Selain mengunjungi beberapa kawan masa kecil, tentu saja saya merindukan kabar tentang Yung Kitam. Suatu hari, saya memutuskan mengunjungi Rustam yang kabarnya sudah menjadi pegawai kecamatan. Saya sengaja pergi sendirian dan tidak memberi kabar kepada istri saya di rumah. Setelah beramah-tamah, temu kangen, dan tentu saja obrolan seputar nostalgia masa kecil, saya menanyakan kabar Yung Kitam kepada Rustam.
“Bagaimana kabar Yung Kitam, Rus?”
“Baik. Yung Kitam masih sehat.”
“Wah, dia sudah hampir sembilan puluh tahun, tapi masih tetap sehat. Syukurlah.”
Rustam terdiam beberapa saat. Air mukanya tampak berubah keruh.
“Kenapa, Rus?”
“Tidak apa-apa,” kilah Rustam.
“Sejujurnya aku kangen sekali timusan Yung Kitam, Rus. Aku kangen sekali dengan tehnya. Aku kangen makan rambutan, makan mangga. Pokoknya aku kangen sekali. Beruntung ya, Rus, kamu masih bisa sering bertemu dengan Yung Kitam,” cerocos saya tanpa menyadari wajah Rustam yang semakin keruh.
“Eh, ngomong-ngomong, Yung Kitam masih suka menjamu anak-anak kan, Rus?”
Rustam mendesah. Terlihat beban berat ada di wajahnya.
“Rus ….”
Rustam mendesah lagi. “Sudah tidak, Ram. Yung Kitam sudah berubah sekarang. Yung Kitam sudah tidak seperti dulu lagi.”
“Maksudmu bagaimana, Rus? Aku tidak mengerti.”
“Sejak Yu Sulastri dan kedua anaknya pindah ke sini dan tinggal bersama Yung Kitam, tabiat Yung Kitam mulai berubah. Tidak lagi baik kepada anak-anak. Tidak juga kepada warga lain.”
“Lho, kok bisa? Bukannya bagus jika Yung Kitam tinggal dengan anak dan cucu-cucunya?” tanya saya dengan nada heran.
“Justru di situ masalahnya, Ram. Yu Sulastri memagar keliling rumah dan pekarangan Yu Kitam. Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan di dusun kita. Kata Yu Sulastri, itu dilakukan untuk jaga-jaga siapa tahu ada yang berniat jahat masuk ke rumah mereka. Meski awalnya Yung Kitam tidak setuju, toh akhirnya tembok keliling dengan teralis besi tetap dibangun juga. Kamu bisa lihat sendiri nanti. Dengan teralis itu, hampir dipastikan kita tidak bisa melihat rumah Yung Kitam lagi. Apalagi, di gerbang teralis dipasangi juga mika berwarna gelap.”
“Tapi kenapa harus ditembok keliling dan diteralis, Rus?”
Rustam mengangkat bahu. “Aku tidak tahu, mungkin begitulah budaya Jakarta. Budaya orang-orang yang percaya tembok bisa melindungi mereka dari bahaya.”
“Lalu, bagaimana dengan Yung Kitam?”
“Seperti yang aku katakan tadi, Yung Kitam mulai berubah sejak rumahnya ditembok keliling dan diteralis. Dia pernah kena marah anaknya hanya karena Yung Kitam mengajak anak-anak kecil memanen rambutan. Sepertinya Yu Sulastri tidak senang dengan hal itu. Yung Kitam juga mulai dilarang keluar rumah dan bergaul dengan warga. Katanya tidak usah keluar kalau tidak ada kepentingan, begitu katanya.”
“Dan Yung Kitam menurutinya?”
“Tentu saja tidak. Yung Kitam masih sering memberikan makanan dan jajanan kepada anak-anak, juga masih sering memberi kepada tetangga. Tapi, sejalan dengan waktu, Yu Sulastri semakin tidak suka dengan tindakan Yung Kitam. Puncaknya, suatu hari uang dan beberapa perhiasan Yu Sulastri hilang. Geger besar terjadi, pasalnya hari saat kehilangan itu terjadi, Yung Kitam yang habis memanen kacang hijau mengajak anak-anak kecil untuk menikmati koyah yang dibuatnya. Yu Sulastri marah besar, murka sekali dia. Anak-anak kecil menjadi pihak tertuduh, dan Yung Kitam menjadi pihak yang bersalah karena mengajak anak-anak itu. Kejadian itu bahkan menyeret Pak Kasdamin, ketua RT baru untuk campur tangan. Anak-anak di interogasi, tapi tidak ada satu pun dari mereka yang merasa mengambil uang atau perhiasan. Mendengar penuturan anak-anak, Pak RT dengan hati-hati bertanya, barangkali Yu Sulastri lupa menaruh uang dan perhiasannya. Apa jawabannya? Yu Sulastri mendamprat habis Pak Kasdamin dan juga berbicara macam-macam tentang warga dusun. Perkara itu tidak selesai dan menjadi awal perubahan sikap Yung Kitam.”
Saya menyenderkan punggung ke kursi. Saya tidak menyangka akan begini ceritanya.
“Sejak saat itu, “ lanjut Rustam, “Yung Kitam kerap marah-marah jika ada anak-anak yang mendekati pagar rumahnya. Dia sudah tidak lagi mengajak anak-anak untuk makan timusan di rumahnya. Kemarin saja, Rasdi, anakku yang baru berumur tujuh tahun pulang dengan sedih karena bendungan yang dibuat oleh dia dan teman-temannya di depan gerbang dibongkar paksa oleh Yung Kitam. Bikin jelek pemandangan katanya. Anakku juga dimarahi habis-habisan dan dilarang main didekat gerbang lagi.”
“Sampai sebegitukah?” ujar saya hampir tidak percaya.
“Tidak hanya sampai di situ. Beberapa waktu yang lalu, Robiah, anak Wasri dan beberapa teman-temannya juga bermain masak-masakan di bawah pohon dekat gerbang. Sebenarnya mereka tidak dekat sekali dengan gerbang. Hanya saja, asap pawon-pawonan mereka masuk ke halaman rumah Yung Kitam. Yu Sulastri mencak-mencak karena pakaian yang sedang dijemurnya bau asap. Yung Kitam keluar menemui anak-anak itu dan tanpa basi-basi mengobrak-abrik mainan mereka. Robiah dan teman-temannya menangis mendapat perlakuan seperti itu. Rasdi yang menceritakannya padaku.”
Saya mengusap wajah yang terasa pias. Saya benar-benar tidak menyangka.
“Mau dengar kata anak-anak tentang Yung Kitam sekarang?” tanya Rustam
“Apa?” kata saya penasaran
“Kata mereka Yung Kitam itu Nenek Lampir Pemarah.”
Mendengar itu, saya mengurut kening. Anak-anak sudah tidak mengenal lagi Yung Kitam yang senang menyajikan timusan hangat dan teh, Yung Kitam yang selalu menemani dan memuji anak-anak main masak-masakan, atau Yung Kitam yang selalu baik hati kepada semua orang. Sudah tidak ada lagi sosok Yung Kitam seperti itu di mata anak-anak. Tidak ada lagi.
“Ram …. ”
“Iya, Rus.”
“Apa Yung Kitam akan menutup usia dengan julukan tidak baik itu?”
Saya terdiam. Tidak bisa menjawab. Pikiran saya melayang ke mana-mana. ***
*IMAM SYAFI’I, saat ini sedang berjuang menyelesaikan program studi Pendidikan Bahasa Arab, fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN SAIZU Purwokerto. Memulai belajar menulis sejak 2016, tapi baru mulai mengirimkan naskah-naskahnya pada awal 2021. Laki-laki yang memiliki hobi membaca, menulis, serta traveling itu bercita-cita menjadi seorang penulis yang rendah hati dan editor di salah satu penerbitan buku di Indonesia.









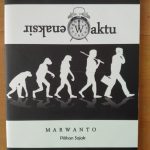



Lumayan enak dibaca.