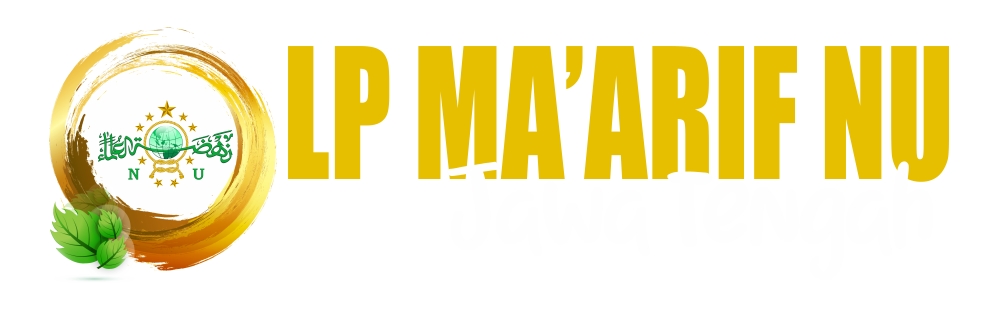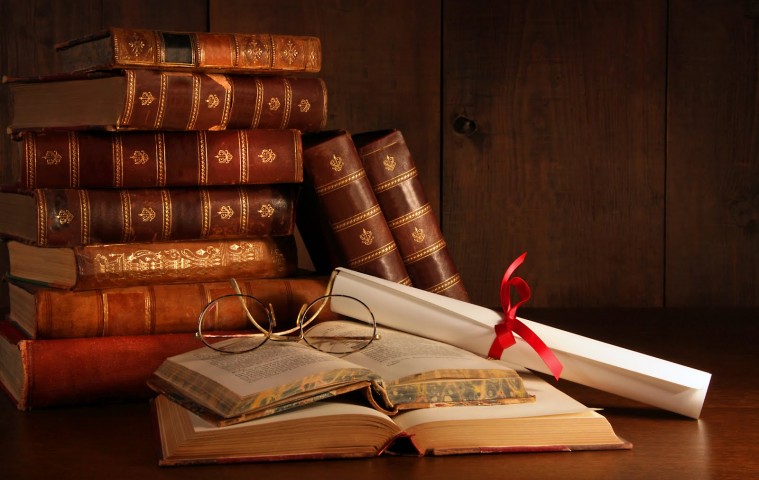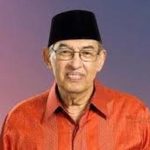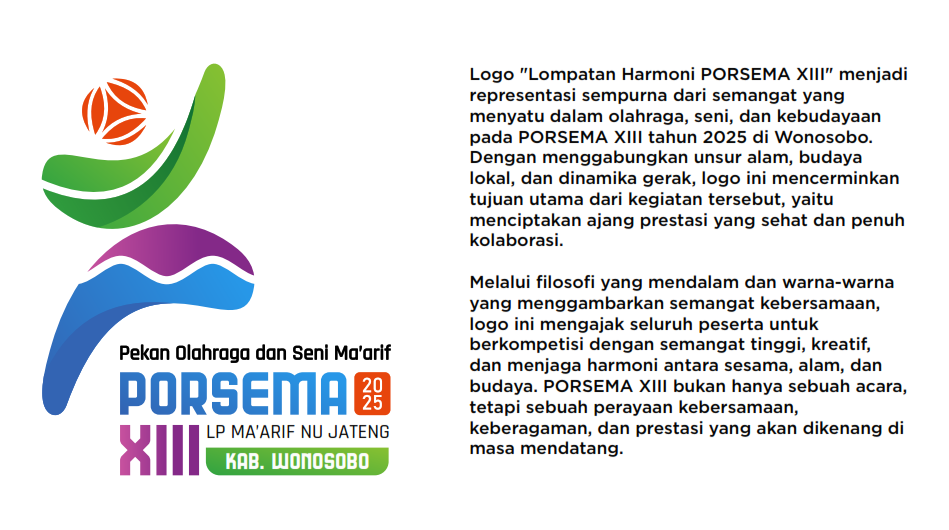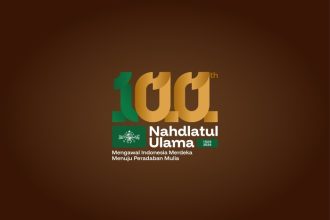Oleh Gunoto Saparie
Sesungguhnya cukup menarik untuk melihat peran pesantren tradisional (atau pesantren “salaf”) di Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang sampai saat ini masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar utama dalam pengajaran kitab kuning (karya intelektual muslim klasik). Bahasa Jawa dinilai lebih lengkap dan komprehensif menggambarkan status gramatikal struktur bahasa Arab dalam kitab kuning yang diajarkan dibandingkan dengan bahasa lain. Dengan kata lain, dalam hal ini bahasa Arab kitab kuning dipandang lebih representatif kalau diartikan dengan bahasa Jawa.
Pemertahanan bahasa merupakan defense terhadap adanya tendensi pergeseran bahasa. Ia merupakan kesadaran akan suatu bangsa untuk mempertahankan identitas, sebuah sistem nilai untuk bangsa. Pemertahanan diperlukan ketika terdapat tendensi dalam sebuah pergeseran bahasa. Sebagai salah satu objek kajian sosiolinguistik, gejala pemertahanan bahasa sangat menarik untuk dikaji. Konsep pemertahanan bahasa lebih berkaitan dengan prestise suatu bahasa di mata masyarakat pendukungnya (Crystal, 1988).
Pondok pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam di Indonesia yang paling tua usianya dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dawam Rahardjo mengungkapkan bahwa pesantren adalah suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Pesantren merupakan tempat dimana anak-anak muda belajar secara lebih mendalam dan lebih lanjut tentang ilmu agama yang diajarkan secara sistematis, langsung dari bahasa Arab serta mendasarkan pembacaan kitab-kitab klasik hasil karya ulama-ulama besar.
- Iklan -
Pesantren salaf adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah hanya ditetapkan untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengamalkan pengajaran pengetahuan umum.
Salah satu ciri khas dalam sistem belajar mengajar di pesantren salaf adalah metode bandongan dan sorogan. Bandongan adalah suatu metode pengajaran dengan cara guru/kiai membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa Arab (baca: kitab kuning) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, sedangkan para santri mendengarkan sambil memberi catatan pada halaman-halaman kitab yang sedang dibaca. Metode sorogan adalah para santri membaca kitab, sementara kiai atau ustad menyimak sambil mengoreksi atau mengevaluasi bacaan seorang santri satu persatu (ada yang dilakukan bersama-sama) (Dhofier, 1982).
Akan tetapi, penggunaan bahasa Jawa hanya terjadi pada pesantren yang menggunakan pendidikan belajar mengajar dengan menggunakan metode bandongan dan sorogan. Ia tidak terjadi pada pesantren yang mengunakan bahasa pengantar bahasa Arab dengan selingan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa melalui metode sorogan dan bandongan di pesantren sampai saat ini masih tetap dipelihara oleh masyarakat pendukungnya.
Tradisi penerjemahan bahasa asal ke dalam bahasa Jawa menggunakan aksara pegon. Bahasa Jawa yang digunakan untuk memberi makna kitab-kitab yang dipelajari oleh santri disebut bahasa Jawa-Kitabi. Dari segi bahasa terjemahan bahasa Jawa-Kitabi mengacu pada tata bahasa Arab. Penggunaan bahasa Jawa-Kitabi dalam komunitas pesantren sejak dulu hingga sekarang masih tetap dilestarikan. Bahasa Jawa-Kitabi tidak mengenal tingkatan. Bahasa Jawa di pesantren bercorak campuran antara bahasa Jawa krama dan ngoko. Secara historis bahasa Jawa dialek pesisir merupakan embrio bahasa tutur pesantren yang akhirnya dalam bentuk korpus tertulis menjadi bahasa Jawa-Kitabi.
Penerjemahan kitab-kitab kuning ke dalam bahasa Jawa memiliki kekhasan yang unik. Kekhasan itu berupa tulisan miring ke bawah dalam bahasa Jawa di bawah dan di antara huruf asal (baca: Arab). Bahasa yang dipakai cenderung menggunakan bahasa Jawa Ngoko sekalipun tidak menutup kemungkinan bercampur dengan bahasa Jawa Krama untuk terjemahan yang berbentuk prosa.
Memang, sejak Islam masuk ke Jawa, masuk pula kitab-kitab yang berisi ajaran Islam. Kitab-kitab tersebut banyak dikembangkan di pesantren-pesantren. Awal mulanya kitab-kitab itu berbahasa Arab sebagaimana asalnya. Dengan pertimbangan agar ajaran-ajaran itu lebih mudah dipelajari masyarakat luas, kitab-kitab itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Akan tetapi, jika dicermati, penggunaan bahasa Jawa itu memiliki kekhasan tersendiri. Terkadang ditemukan bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab pesantren itu ternyata tidak lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari.
Dalam kitab-kitab itu sering digunakan kata-kata yang arkais, yaitu kata-kata kuno yang tak lazim digunakan. Kata-kata tersebut di antaranya anging ‘kecuali’, dihin, dingin ‘dahulu’, ingsun ‘aku’, sira ‘kamu’, lamun ‘jika’, tuhu ‘sungguh’. Dalam kitab-kitab itu ditemukan pula kata-kata yang memiliki fungsi khusus, misalnya apa, sapa, dan utawi.
Pertanyaan pun muncul ke permukaan: Mengapakah tidak ada pesantren salaf yang memberikan makna harafiah dengan menggunakan bahasa Indonesia? Agaknya memang harus diakui, kosa kata bahasa Indonesia tidak sekaya bahasa Jawa, sehingga, sepanjang pengetahuan saya, sampai sekarang belum ada orang yang memberikan makna kitab kuning dengan bahasa Indonesia.
*Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah