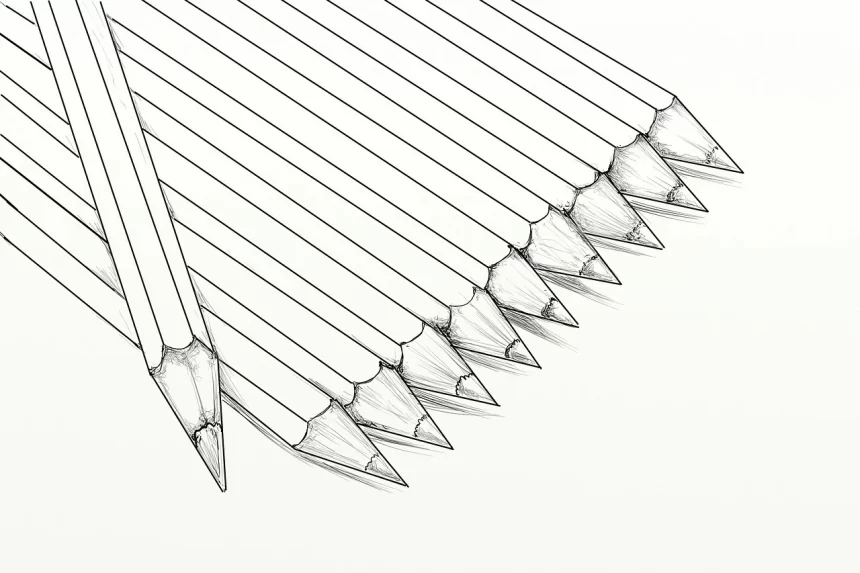Oleh: Depri Ajopan
Hari ini terakhir aku merevisi naskahku. Aku yang tidak mau diganggu didatangi biang kerok itu lagi.
“Untuk apa kau menulis novel, itukan cerita bohong.” Aku tak terpelanting ocehan bodoh seperti itu. Aku yang tak mau kalah menyampaikan padanya seperti seorang pemidato.
“Menulis karya sastra, bukan berarti menulis kebohongan, dan membaca karya sastra bukan berarti mencicipi kebohongan.” Ia menjawab raunganku dengan meloncongkan bibirnya ke depan, bermaksud mencemeehku.
- Iklan -
“Apa untugnya menulis novel, berhayal dan terus berhayal,” ia tertawa. Entah apa yang lucu, dari kata-kataku yang geram. Aku benci sikapnya itu. Aku harus membalasnya,
“Novel itu fiksi bukan fiktif. Itu dua hal yang berbeda,” ia tertawa lagi mengejekku.
“Ya, tapi subtansinyakan tetap dari imajinasikan?”
“Dari pada kau seorang wartawan, penulis berita politik, yang sibuk mencari kesalahan orang. Kau tidak bisa berimajinasi tak terbatas sepertiku.”
“Aku bukan menulis berita politik saja, berita lain juga aku bisa,” ia membesarkan dirinya.
“Pokonya, kau cuma bisa menulis berita berdasarkan peristiwa yang terjadi, yang lain tidak.”
“Siapa bilang, selain menulis berita di media khusus, aku bisa menulis esai, opini. Sudah banyak aku mendapatkan honor dari media lain. Menulis novel pun aku sanggup, tapi untuk apa?” Ia menggeleng-gelengkan kepala, dan terus menghujatku.
“Kalau kau bisa menulis novel yang bagus, aku siap berhenti berkarya, kaulah yang jadi penerusku untuk mengejar cita-citaku itu.” Aku menantangnya. Aku harap ia tersinggung dengan kata-kataku yang sengaja menusuk jantungnya, dan tidak cukup sampai di situ, aku masih merong-rongnya.
“Kau pikir dengan lahirnya tulisan-tulisanmu yang penuh kasus itu, bisa merubah negeri ini
dan membuat jera para koruptor.”
Aku tak melihat kemarahan memancar pada wajahnya. Ia begitu tenang menghadapiku. Melihat ia bersikap santai, aku yakin ia teguh dalam pendiriannya, dan tak mau merubah sikap mengikuti jejakku. Ia tak goyah mendengar seranganku, dan ia tak berkata sepatahpun. Aku tak menghiraukannya lagi, aku sibuk merevisi novelku kembali, sebentar lagi aku kirim ke Jakarta, mengikuti lomba menulis novel di salah satu penerbit di sana.
* * *
Untuk menenangkan pikiran, aku ke luar sebentar. Duduk berpangku tangan di sebuah bangku panjang seperti patung bisu, memandangi rerumputan hijau yang menari-nari diterjang angin, dan aku berhayal.
“Kenapa kau duduk di sini? Kau ingin mencari inspirasi untuk tulisan-tulisanmu yang tak berguna itu?” Biang Kerok itu datang lagi mengajakku berdebat, dan aku sengaja mengalihkan pembicaraan.
“Aku ingin menikah, kalau bisa tahun ini. Tapi aku juga bingung.”
“Pasti karena kau belum punya uang.” Aku mengangguk.
“Aku tidak mau sawah kami dijual untuk biaya menikah,” ia tertawa mendengar penjelasanku, sampai telingaku bergetar mendengarnya. Aku belum dapat solusi darinya melainkan cemoohan melulu merupakan tawa yang menyiksa batin pendengarnya. Dasar biang kerok, hatiku berbicara.
“Makanya, kalau ingin mendapatkan uang banyak jangan jadi penulis novel. Tapi jadilah seorang pengusaha.”
“Kau juga kan seorang penulis.”
“iya, tapi tidak sepertimu.”
“Maksudmu?”
“Kau kan menulis untuk mencari uang. Sementara aku menulis bukan karena uang. Menulis adalah kebutuhan hidupku. Menulis kesenangan bagi diriku. Mau dapat uang atau tidak tak jadi soal.”
“Bohong kalau kau menulis tidak mengharapkan uang. Buktinya honor tulisanmu cair kau menerimanya terus,” aku mulai menghidupkan platukku menghujatnya.
“Siapa juga yang tak butuh uang. Hanya orang munafik yang mengatakan ia bekerja tak butuh uang, tapi mereka yang bekerja semata-mata karena uang sehingga menghalalkan segala cara adalah lebih munafik lagi. Lagiankan aku tak pernah memintanya. Paling tidak, aku tidak seperti mereka penulis yang lupa diri.”
Semakin jauh omongannya, aku semakin tidak memahaminya. Apa maksudnya penulis yang lupa diri, aku pun tak ingin bertanya. Ia sendiri yang berkomentar lebih dalam lagi.
“Meskipun tulisan-tulisanku sering dimuat di media nasional, baik media cetak dan media online. Aku tetap mengirm tulisan-tulisanku ke koran-koran lokal yang jelas-jelas honornya kecil. Bahkan walaupun aku tahu tidak berhonor sama sekali, aku tetap mengirim tulisanku yang bernilai.”
“Kau ingin mengatakan tulisanku tidak bernilai.”
“Siapa bilang.”
“Tadi kau bilang tulisanku tidak berguna.”
“Jangan ambil hati dengan kata-kataku. Harusnya kau makin semangat.”
“Terus, apa maksudmu berkata begitu?” Ia tak mau berkomentar tentang itu, dan ia bilang
seperti memberi pesan padaku,
“Naskahmu terlalu sering ditolak. Kirimlah ke penerbit yang kamu yakin bisa menerimanya, walaupun penerbit kecil. Mungkin royaltinya tidak seberapa, tapi sebagai penulis pemula kau mulai dikenal orang.” Aku yang sensitif dengannya, merasa ia menyinggungku sebagai penulis pemula yang sering mengirim naskah novel ke berbagai penerbit. Setelah menunggu waktu yang cukup lama 4 sampai 5 bulan, aku dapat pesan singkat berupa penolakan naskah. Setelah direvisi aku kirim lagi ke penerbit yang berbeda. Aku yang sudah lama menunggu, dapat informasi naskahku ditolak lagi. Nasibku menerobos penerbit mayor belum pernah berhasil. Naskahku yang baru, yang sebentar lagi akan kukirim, paling lambat dua hari ini ke email penerbit untuk mengikuti lomba, semoga bisa jadi pemenang. Jika aku kalah, ia semakin leluasa menyerangku.
* * *
Empat bulan aku menunggu. Naskahku yang berjudul Aku Turut Berduka Cita Atas Pernikahanmu, tidak jadi pemenang, walaupun naskah itu layak terbit. Informasi buruk tentang kegagalanku jadi pemenang si biang kerok itu sudah tahu. Aku harus siap-siap mendapat cemoohan yang lebih keras lagi daripada sebelumnya.
“Dari sekian banyak naskah yang masuk. Dan yang mengirim begitu banyak penulis-penulis yang sudah matang, lalu kau berharap jadi pememnang. He….he…he…. kau tidak akan bisa menyentuh bintang-bintang kalau cuma dengan menulis novel, walaupun kau jadi pemenang.” Ia sengaja datang menemuiku di sebuah warung tempat aku biasa nongkorong setelah lelah berimajinasi dalam kamar.
“Walaupun tidak jadi pemenang, tapi naskahku layak terbit. Sebentar lagi akan dicetak, masuk ke toko-toko buku besar.” Aku yakin, ia terluka mendengar penjelasanku sebagai pembelaan bagi diriku.
“Kalau cuma layak terbit dan dicetak. Kau sendiri bisa melakukan itu di penerbit lain dengan biaya yang terjangkau. Terbitkan saja di penerbit indi,” ia memang tak mau kalah.
“Keputusanmu tahun ini untuk menikah bagimana jadinya?” Kenapa pertanyaannya tiba-tiba meloncat seperti itu. Aku yakin ada yang tidak beres pada dirinya. Apa ia sakit hati mendengar naskahku layak terbit? Mungkin ia sudah mengaku kalah setelah mendengar penjelasanku, mengenai naskahku yang terbit di penerbit mayor lewat seleksi yang super ketat.
“ Belum tahu,” pikiriranku mulai kacau. Aku melihat langit runtuh menimpaku.
“Orang mana perempuan yang malang itu?” dia selalu membuatku jengkel.
“Aslinya Jawa Tengah,” tapi ia tak jauh tinggal dari sini,” jawabku.
”Usianya berapa?”
“Tiga puluh dua tahun.”
“Terlalu tua untukmu. Seharusnya kau mendapatkan seorang gadis muda yang cantik jelita. Kau kan pemuda tampan, tapi itulah cinta tak mengenal usia.” Aku tak tahu apakah ia benar memujiku, atau bermaksud menghujatku.
“Apa sebelumnya perempuan itu pernah menikah?”
“Dia ditinggal mati suaminya.”
“Pantas.”
Aku jelaskan sekilas tentang sejarah pertemuanku dengan Gresi, perempuan yang sanggup mengganggu pikiranku, dan merusak aktivitasku ketika berkarya.
“Aku kenal perempuan itu. Cocok sih untukmu. Ayahnya seorang penyair kampung. Aku pernah mewawancarainya dulu, tapi beliau sekarang sudah meninggal. Ibunya juga mencintai sastra, pasti ia menerimamu,” aku menganggap itu lelucon yang sama sekali tidak lucu. Aku yakin ia hanya membual, dan mengejekku sebagai penulis sastra.
“Gresi sudah punya anak?”
“Belum.”
“Jadi dia belum punya anak. Sementara dia pernah menikah. Kau tidak takut dia bermasalah?”
Aku menggeleng. Dia bisa memberiku keturunan atau tidak, itu bukan hal yang menurutku harus aku pikirkan.
“Bagaimana kalau seandainya kau yang bermasalah, tidak bisa memberi keturunan?” Aku tak menggubris. Ia mengerti aku jengkel dengan pertanyaan yang meragukan kejantananku.
“Aku yakin keluargamu tidak setuju, diakan janda. Kau masih perjaka.”
Ternyata apa yang ia khawatirkan benar. Begitu tajam pemikirannya dibanding aku. Awalnya Ibu dan keluargaku tidak setuju. Dengan usahaku yang gigih, pelan-pelan akhirnya aku bisa melunakkan hati mereka, walaupun memakan waktu tiga bulan setelah novelku terbit, dan masuk ke toko-toko buku. Tentang mereka yang mencemoohku seorang perjaka tapi dapat janda, aku tak peduli. Aku menikah dengan orang yang menurutku tepat dan ia perempuan baik. Ia mencintaiku dan aku pun sangat mencintainya. Setelah itu aku tak mau tahu.
* * *
Waktu terus bergerak. Sebulan kemudian, saatnya aku siap-siap melamar perempuan itu. Sebelum berangkat aku memohon doa dari Ibu. Setelah ia memberi restu, ia menatap poto ayah yang setia terletak didinding. Airmatanya jatuh ke lantai mengingat kenangan indah dengan suaminya yang tak mungkin terulang lagi. Mereka akan bertemu pada kehidupan yang kedua.
“Tunggu dulu kawan,” biang kerok itu memanggilku ketika aku dan seorang yang dianggap penting dalam adat kami, menunggu bus di depan rumah. Ia tahu aku mau pergi melamar Gresi. Apakah ia mendukungku, atau kedatangannya hanya membuat gaduh suasana. Ia memelukku seolah memberi semangat, dan berbisik di telingaku mengatakan sesuatu,
“Sesampai di sana, bilang saja sama Ibu Gresi kau seorang novelis, kau pasti diterima di keluarganya. Kalau perlu, untuk meluluhkan hati ibunya yang mencintai sastra, bawa saja bukumu yang baru terbit itu satu eksmplar sebagai bukti kau seorang sastrawan. Pas menikah nanti, jadikan saja buku itu maharnya. Aku sudah membaca tulisanmu, bagus kok,” baru kali ini ia membuat senang hatiku. Aku merasa ada perubahan drastis pada dirinya yang mulai mencintai karya sastra. Aku yang berdebar-debar bergidik mendengar pengakuannya.
“Aku juga membaca berita-beritamu di media itu, bagus”, aku membalasnya.
* * *
Aku datang ke rumah itu bersama Mamakku1 mengikuti kebiasaan yang terjadi di kampungku, walaupun ini bukan aturan adat yang diwajibkan. Mendatangi rumah Gresi yang belum pernah sekali pun aku menginjak lantainya, membuatku deg-degan.
“Pekerjaanmu apa?” Aku tak menyangka itu pertanyaan pertama yang dilontarkan Ibu Gresi yang sinting. Minuman belum diletak di atas meja. Aku merasa diintrogasi. Mamakku yang duduk terpaku mengerjab-erjabkan mata, sambil menelan ludah. Ia merasa belum saatnya untuk membela hak-hakku.
“Bertani kecil-kecilan di kampung Buk,”
“Kau petani kecil, berani melamar putriku. Kau tahu apa pekerjaan putriku, dan almarhum suaminya dulu. Kau tidak pantas untuk putriku.” Aku yang dibanding-bandingkan merasa terluka. Mamakku langsung berdiri.
“Keluarga edan dan sombong,” itulah yang keluar dari mulutnya, menyerupai bisikan. Kemudian ia bergegas pergi meninggalkanku. Aku tahu ia berharap aku mengikutinya, dan ia pasti menungguku di luar.
“Selain bertani, dia juga seorang penulis sastra Bu. Dia seorang novelis. Ini ada bukunya sudah terbit.” Gresi yang dari tadi diam menyaksikan kegetiran itu angkat suara. Ibunya yang galak mengangguk-anggukkan kepala.
“Terserah kalian saja, kapan mau resepsi pernikahannya diadakan. Aku harap tidak usah pakai adat kita Gresi. Atau adat mereka yang berbelit-belit itu. Nikah seperti di kota saja,” mendadak ibunya tenang dan tersenyum melihatku. Aku yang masih bingung teringat kata-kata terakhir si penulis berita itu.
Sesampai di sana, bilang saja sama Ibu Gresi kau seorang novelis, kau pasti diterima di keluarganya.
Aku yang menganggap ia musuh bebuyutanku selama ini, merasa berdosa. Aku harus berterimakasih, dan minta maaf padanya, karena ia sahabatku, bukan lawanku seperti anggapanku selama ini.
Catatan:
- Mamak di sini maksudnya Saudara laki-laki Ibu, bukan ibu kandung. Di daerah saya Sumatera Barat Mamak sangat berperan dalam pernikahan keponakannya.
DEPRI AJOPAN, lulusan Pesantren Musthafawiyah Purba-Baru, Mandailing Natal, Sumatera Utara.Menyelesaikan S-1 Program Studi Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. Menulis fiksi dan diterbitkan di sejumlah media. Novel terbarunya Pengakuan Seorang Novelis sudah terbit. Ia bergiat di Komunitas Suku Seni Riau dan mengajar di Pesantren Basma Darul Ilmi Wassa’dah, Kepenuhan Barat Mulya, Rokan Hulu, Riau, sebagai guru Bahasa Indonesia.