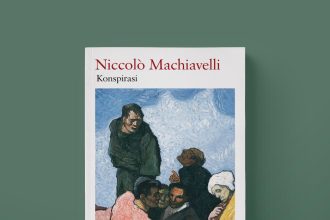Oleh Mufti Wibowo
Judul : Logika, Bahasa, & Modus Kuasa
Penulis : St. Tri Guntur Narwaya
Tebal : xxviii + 480
Cetakan : pertama, 2021
Penerbit : Basabasi
Bahasa yang lebih galib dipahami sebagai alat komunikasi sehari-hari, terasa marwahnya ketika disandingkan dengan dua entitas lain dalam frasa judul buku Narwaya ini, logika dan modus kuasa. Setiap entitas memiliki bahasanya. Dari bahasa itu pulalah, kita bisa menemukan katakter atau identitas khasnya. Orang Jawa, misalnya, menyebut bahasa sebagai busana. Dengan begitu, bahasa adalah alat yang bisa menjelaskan: siapa pemiliknya, logika atau ideologi apa yang bekerja di dalamnya, dan kepentingan apa balik kerjanya.
Narwaya, melalui Logika, Bahasa, & Modus Kuasa, menguraikan perkembangan ilmu logika dari masa lalu hingga kiwari. Maka, dia merasa perlu menyebut nama wingit dari era Yunani: Aristoles, yang punya andil besar dalam perkembangan ilmu logika hingga memungkinkan perkembangannya hingga sekarang, terutama dalam disiplin matematika dan fisika. Hingga nama besar dari pemikir posmodern, seperti Foucault.
- Iklan -
Berdasarkan pembacaan atas berbagai wacana (baca: bahasa) dalam rentang kesejarahan itu, pembaca bisa mendapat proyeksi umum mengenai pemikiran-pemikiran yang menjadi corak khas—sekaligus menunjukkan dialektikanya—yang mewakili semangat zaman; abad pertengahan yang dikuasai dominasi mitos, abad modern yang diinspirasi pemikiran Descrates, hingga panji-panji dekonstruksi kaum posmodern.
Lebih dari itu, buku ini akan menunjukkan jalan kepada pembaca hingga sampai pada pokok cacat logika yang “tabu” itu. Cacat logika ternyata tidak melulu terjadi karena ketidaktahuan pembuat wacana, tetapi bisa karena kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan itulah yang akan merujuk pada modus dan motif di baliknya.
Sementara itu, buku ini menyebut sedikitnya ada 29 bentuk kecacatan logika. Satu di antara praktik cacat logika yang terjadi adalah argumentum ad popullum. Ia adalah jenis proposisi argumentasi yang dibangun dengan cara membangkitkan emosi atau simpati massa melalui klaim hasutan dengan cara memberikan alasan-alasan pernyataan seolah-olah itu bertujuan untuk kepentingan atau bersifat umum, padahal sebaliknya (hal. 305). Ini biasa dilakukan oleh politisi pada masa kampanye demi tujuan keterpilihan. Tapi, politisi itu melupakan janji politiknya setelah memperoleh kekuasaan.
Pada kasus yang berbeda, bentuk cacat logika mengacu kepada pihak berwenang. Hal ini kerap muncul oleh pelontar penyataan menggunakan aspek otoritas untuk dijadikan dasar argumentasi (hal. 319). Kita bisa menemukan pernyataan itu misal pada kasus negara (melalui agen organiknya) memerintahkan warga relokasi tempat tinggal atau tanah ladangnya karena pemerintah akan membangun infrastruktur yang akan bermanfaat bagi orang banyak.
Dua bentuk cacat logika dalam membangun argumentasi di atas kemudian mengingatkan saya pada kurikulum yang berlaku di sekolah-sekolah, hari ini. Anak-anak bangsa disebut dituntut menguasai 4 kecapakan hidup era kiwari, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Terasa ironis tentu, sebab, yang gagal dalam membangun logika justru “pemegang otoritas”. Seolah fenomena itu hendak mengafirmasi bahwa bangsa Indonesia masih mengalami cacat literasi, yaitu ketidakmampuan memahami isi wacana alih-alih bukan buta aksara.
Keharusan mengurai pemikiran abstrak dan kompleks tentu berpotensi membikin dahi pembaca berkerut. Mengantisipasi itu, tampak usaha penulis untuk meminimalkan penggunaan kata kajian lalu menggantinya dengan padanan kata yang relatif populer. Jika harus menyebut hal minor dalam buku ini adalah faktor teknis belaka dalam penyuntingan, hal yang berpotensi mengganggu itu yaitu cukup banyaknya salah ketik, selain ketidaksesuaian penomoran halaman pada daftar isi.
*Mufti Wibowo, lahir dan berdomisili di Purbalingga; penulis buku Catatan Pengantar Tidur.