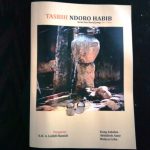Cerpen S. Prasetyo Utomo
TAK perrnah diduga Broto bila ia mesti menghadap Abah Ajisukmo yang sudah sangat dikenal selama bertahun-tahun. Ia singkirkan perasaan sungkan untuk bertandang ke pesantren, menghadap Abah Ajisukmo. Laksmita, istrinya, yang pagi-pagi sekali, usai salat subuh, memintanya datang pada kiai setengah baya berhidung mancung, beralis tebal, dengan mata cemerlang meneduhkan. Laksmita yang hamil tua, menyetir mobil. Broto masih dalam keadaan lunglai, lemas, tanpa tenaga, usai pingsan ketika turun dari panggung pertunjukan tari semalam di hotel baru milik sang juragan.
Laksmita membawa pulang Broto tengah malam itu juga, setelah siuman dan melakukan beberapa pemeriksaan di ruang gawat darurat rumah sakit, yang berakhir mencengangkan: pemilik padepokan itu dinyatakan sehat. Ia kelelahan. Berhari-hari ia berlatih menari dan mengurusi padepokan. Kurang istirahat. Hanya sedikit tidur.
Semua orang mengatakan Broto terkena tenung. Terutama di padepokan, tersebar kabar, ia terkena santet usai menari di hotel baru milik sang juragan. Berkembang pula dugaan: siapa yang mengirim tenung pada Broto? Apa persoalan di antara mereka? Betapa sakti dukun pengirim santet itu, hingga Broto bisa pingsan saat turun dari panggung tari! Beruntung, Broto tak mati malam itu juga!
- Iklan -
***
SEPERTI Jumat pagi sebelumnya, Abah Ajisukmo menyelenggarakan pengajian di pesantrennya. Zikir bersama, dan kiai setengah baya itu menerima tamu di pendapa rumahnya. Abah Ajisukmo berjubah putih berserban putih bersila di tengah-tengah tamu yang duduk melingkar di karpet. Abah Ajisukmo tersenyum, memandangi sekilas tamu-tamunya yang datang dari jauh, dengan berbagai kepentingan. Mereka bersabar, menunggu giliran menghadap Abah Ajisukmo.
Laksmita mengajak suaminya ke pesantren Abah Ajisukmo, yang diyakini orang-orang – tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai penjuru daerah – memiliki kekuatan mistis menyembuhkan orang terkena tenung. Broto sepenuhnya sadar. Ia hanya merasakan tubuh yang lunglai setelah siuman dari pingsan. Ia merasa sehat. Hanya perlu istirahat. Tetapi ia tak mau mengecewakan istrinya yang dengan kandungan membuncit menemaninya duduk bersimpuh di pendapa rumah Abah Ajisukmo. Zikir bersama tamu-tamu yang berdatangan dari daerah-daerah yang jauh, hingga memenuhi pelataran pesantren. Dalam beberapa malam ini Broto memang selalu bermimpi zikir di pendapa rumah Abah Ajisukmo bersama banyak orang yang tak dikenalnya.
Telah lama Broto mendengar ketenaran Abah Ajisukmo. Orang-orang dari daerah yang jauh berdatangan meminta restu pada kiai itu. Ada juga yang datang untuk didoakan sembuh sakit, terbebas dari santet, dan mohon dukungan agar menjadi pejabat. Broto – pemilik padepokan – yang terbiasa dikelilingi para cantrik di pendapa rumahnya, kini harus menahan diri menunggu giliran menghadap Abah Ajisukmo.
Di depan Broto duduk bersila seorang lelaki setengah baya, yang dikenal orang-orang sebagai gubernur – yang mencalonkan diri kembali untuk berkuasa. Di hadapan Abah Ajisukmo, calon gubernur itu menunduk, tak berani menatap sepasang mata yang cemerlang, bening, di bawah lengkung alis yang tebal.
Calon gubernur itu menyalami Abah Ajisukmo, mencium tangannya, dan berkata dengan suara bergetar, “Mohon restu, agar saya jadi gubernur untuk kedua kali.”
Abah Ajisukmo tersenyum. Menatap tajam calon gubernur itu. Tidak mengangguk. Tidak menggeleng. Tidak berkata apa pun. Terdiam. Agak lama.
“Dulu memang Abah menyampaikan pesan, saya jadi gubernur hanya sekali,” kata calon gubernur itu. “Sekarang saya kembali meminta restu Abah untuk pencalonan gubernur sekali lagi.”
Tidak mengatakan apa pun, Abah Ajisukmo tertawa. Mungkin menertawakan kerakusan calon gubernur itu. Tetapi calon gubernur itu tak merasa ditertawakan. Ia menanti pesan Abah Ajisukmo. Kiai berjubah putih berserban putih itu tidak mengucapkan kata apa pun. Ia mempersilakan calon gubernur itu untuk bergeser, agar Broto dapat memperoleh giliran bersalaman dengannya. Calon gubernur itu beringsut melewati Abah Ajisukmo, dan belum juga berpamitan, menunggu restu.
Broto menyalami Abah Ajisukmo. Mencium tangan kiai. Abah Ajisukmo menampakkan wajah yang bahagia. “Kau pingsan tadi malam? Jangan khawatir. Kau tak sakit. Kau hanya lelah. Kalau tak keberatan, datanglah ke pesantrenku tiap Jumat pagi begini. Kau bisa zikir bersama jamaahku. Kau akan bugar seperti sediakala.”
Seorang santri yang duduk di belakang Abah Ajisukmo membawa segelas air. Abah Ajisukmo memejamkan mata. Berdoa. Ketika sepasang matanya yang cemerlang itu terbuka, Abah Ajisukmo berpesan, “Minumlah!”
Tenang, pelan, Broto meminum air bening yang telah dihembus doa Abah Ajisukmo. Ia merasakan kesegaran di sekujur tubuhnya. Lalu, ia merasakan tubuh yang kembali bertenaga. Hatinya lebih tenteram. Ia mencium tangan kiai dan berpamitan. Abah Ajisukmo berpesan, “Kalau kau datang lagi kemari, tutuplah kepalamu!”
Dalam perjalanan pulang kali ini Broto yang mengemudikan mobil. Ia menemukan kegairahan baru, yang memandang dunia dengan ketenangan jiwa. Tak menempuh perjalanan jauh, mobil yang dikendarainya sudah mencapai pelataran padepokan. Para cantrik yang melihat Broto mengendarai mobil, terpukau, dan berbisik-bisik: Abah Ajisukmo menyembuhkannya dari serangan santet. Laksmita yang mendampingi Broto hanya tersenyum-senyum. Tak berani menolak anggapan orang-orang.
Bergegas Broto memasuki kamar, dan mencari-cari sarung dan peci. Di depan cermin ia mematut diri. Ia tak pantas berpeci. Ia mencari blangkon. Mengenakan blangkon itu. Ia merasa pantas dengan blangkon di kepalanya. Mengenakan pakaian lurik, dan berkain. Ia ingin memenuhi keinginan Abah Ajisukmo, menutup kepalanya dengan blangkon.
Ketika Broto keluar dari kamar dengan blangkon, lurik, dan kain, tampak sebagai sosok pribadi yang baru – mungkin inilah penampilan yang dibayangkan Abah Ajisukmo.
***
JUMAT pagi. Dengan mengenakan blangkon, lurik, dan berkain, Broto datang ke pendapa rumah Abah Ajisukmo. Ia zikir bersama tamu dari berbagai tempat untuk mencari ketenangan jiwa. Ia berada di antara teman-teman zikirnya dari berbagai kota. Banyak orang tak dikenalnya, mungkin datang dari tempat tinggal yang jauh. Abah Ajisukmo menampakkan kebahagiaannya melihat Broto bersila di pendapa, usai zikir. Calon gubernur beringsut mendekati Abah Ajisukmo, mencium tangan dan meminta restu. Abah Ajisukmo tertawa. Calon gubernur itu berpesan dengan penuh harap, penuh keyakinan, “Kalau aku menang, akan kupugar pesantren ini!”
Abah Ajisukmo membiarkan calon gubernur itu berlalu, meninggalkan pendapa dengan harapan yang berpendar dalam sepasang matanya: ia akan menang sebagaimana lima tahun lalu. Tiba giliran Broto berpamitan. Ia menyalami Abah Ajisukmo, dan seperti gerak tanpa sadar, ia mencium tangan itu.
***
DALAM pertemuan Jumat pagi di pesantren Abah Ajisukmo, Broto hadir tanpa didampingi istrinya, yang subuh dini hari tadi diantarkannya ke rumah sakit untuk melahirkan anak kedua. Pendapa dan pelataran pesantren penuh orang dari berbagai daerah. Berzikir. Mereka datang dengan berbagai kepentingan. Mereka pulang dengan wajah yang tenteram. Ia tak melihat kehadiran calon gubernur. Ketika Broto menyalami Abah Ajisukmo dan mencium tangannya, ia dengar kiai itu berkata tenang, “Calon gubernur itu tak datang lagi kemari. Ia tak terpilih. Kalah. Dulu sudah kukatakan, kesempatannya jadi gubernur cuma sekali. Tapi dia nekat.”
Tiap wajah tamu Abah Ajisukmo menampakkan berbagai perangai dan harapan. Broto melihat ketenangan. Broto merasa bahwa istrinya telah mempertemukannya dengan Abah Ajisukmo untuk menenteramkan perasaan. Di pendapa inilah ia bertemu banyak orang, kadang pejabat, kadang pengusaha ternama, kadang bekas narapidana, yang tak pernah diduga persoalan hidup mereka. Wajah mereka tenang setelah bertemu Abah Ajisukmo.
Wajah Abah Ajisukmo tampak ceria berhadapan dengan Broto.
“Segeralah ke rumah sakit. Anak perempuanmu sudah lahir. Ia akan tumbuh sebagai gadis cantik dan penuh pengabdian seperti ibunya,” kata Abah Ajisukmo.
Dada Broto berdegup dengan detak yang kencang, tak beraturan.
***
Pandana Merdeka, November 2020
*S. Prasetyo Utomo, lahir di Yogyakarta, 7 Januari 1961. Menyelesaikan program doktor Ilmu Pendidikan Bahasa Unnes pada 9 Maret 2018 dengan disertasi “Defamiliarisasi Hegemoni Kekuasaan Tokoh Novel Kitab Omong Kosong Karya Seno Gumira Ajidarma”.
Semenjak 1983 ia menulis cerpen, esai sastra, puisi, novel, dan artikel di beberapa media massa seperti Horison, Kompas, Suara Pembaruan, Republika, Koran Tempo, Media Indonesia, Jawa Pos, Bisnis Indonesia, Nova, Seputar Indonesia, Suara Karya, Majalah Noor, Majalah Esquire, Basabaasi.
Menerima Anugerah Kebudayaan 2007 dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk cerpen “Cermin Jiwa”, yang dimuat Kompas, 12 Mei 2007. Menerima penghargaan Acarya Sastra 2015 dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Menerima penghargaan Prasidatama 2017 dari Balai Bahasa Jawa Tengah.
Kumpulan cerpen Bidadari Meniti Pelangi (Penerbit Buku Kompas, 2005), dibukukan setelah lebih dari dua puluh tahun masa proses kreatifnya. Cerpen “Sakri Terangkat ke Langit” dimuat dalam Smokol: Cerpen Kompas Pilihan 2008. Cerpen “Penyusup Larut Malam” dimuat dalam Pada Suatu Hari, Ada Ibu dan Radian: Cerpen Kompas Pilihan 2009 dan diterjemahkan Dalang Publishing ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Midnight Intruder” (Juni 2018). Cerpen “Pengunyah Sirih” dimuat dalam Dodolitdodolitdodolibret: Cerpen Pilihan Kompas 2010. Novel terbarunya Tarian Dua Wajah (Pustaka Alvabet, 2016), Cermin Jiwa (Pustaka Alvabet, 2017). Kumpulan cerpen yang terbaru adalah Kehidupan di Dasar Telaga (Penerbit Buku Kompas, 2020).