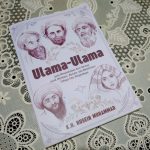Cerpen Latif Nur Janah
Pagi milik Halimah berawal dari kokok ayam jantan di pekarangan rumahnya. Ia adalah perempuan beranak satu yang enggan diboyong anaknya ke kota. Setelah mengambil air di tempayan untuk berwudu, langkah Halimah menuju dipan di kamar sebelah barat. Dua rakaat sembahyang ia lakukan diiringi derit dipan dan suara burung dari kebun. Mukena yang ia kenakan senada dengan warna rambutnya yang mulai keperakan. Garis-garis di dahinya pun mengukuhkan bahwa telah banyak asam garam kehidupan yang telah ia telan.
Ia menyalakan kompor, hendak merebus sedikit air untuk menyeduh teh. Kebiasaan yang selalu ia lakukan sebelum bersiap ke sekolah. Di saat seperti itu, ia selalu teringat Hamid, anaknya yang kini bertugas di Manokwari sebagai seorang polisi. Di sela suara air mendidih itu, kenangan saat Hamid masih sekolah dulu selalu terlintas. Halimah pernah diajak Hamid tinggal bersamanya, namun ia menolak. Ada sesuatu yang menahannya di kampung halaman yakni sekolah yang berdiri di dekat perbatasan.
Sekolah itu, dulunya ia dirikan bersama mendiang suaminya. Murid pertama mereka adalah Hamid dan empat orang lainnya. Lamban laun, banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah itu. Tidak lain karena sekolah negeri baru bisa dicapai setelah melewati sepuluh kilometer perjalanan darat dan menyeberang sungai. Belum termasuk risiko jika musim hujan yang menyebabkan aliran sungai meluap-luap.
- Iklan -
Demi tak mau melihat kampungnya menjadi terbelakang, Halimah dan suaminya mendirikan sebuah bangunan beratap seng, dibantu beberapa warga. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, suaminya akan membersihkan lantai tanahnya dengan sapu lidi, membersihkan sarang laba-laba, kemudian menggelar tikar pandan sebagai alas duduk. Setelah Hamid, sekolah itu menjelma anak kedua bagi Halimah dan suaminya.
Anak kedua itu pun lantas beranak-pinak. Murid-murid Halimah semakin banyak. Kini, sekolah itu bahkan sudah bertembok bata, mempunyai empat guru, dan memiliki meja kursi meskipun sampai sekarang belum negeri. Namun bukan itu yang membuat sekolah itu semakin berdiri kokoh. Hati Halimah-lah tonggak yang membuatnya tak pernah goyah.
Pagi milik Halimah berakhir dengan suara doa yang menggema dari balik dinding kelas. Halimah menutup doa anak-anak dengan ucapan salam, lantas berjalan pelan ke arah pintu keluar. Satu persatu muridnya bersalaman penuh takzim. Bersama seorang guru perempuan lain ia merapikan meja kursi, menghapus papan tulis, lantas menyapu seluruh lantai. Semua itu adalah bagian dari hari-hari Halimah. Tanpa itu semua, seolah ada celah dalam menjalani harinya.
Sesampai di rumah, sebelum ia sempat duduk di balai-bala rumahnya, seorang pegawai kantor pos muncul dari balik pagar bambu yang dikelilingi bunga menur. Dengan senyum amat sopan, ia memberikan sepucuk surat kepada Halimah. Surat dari Hamid.
Dalam surat itu, layaknya ibu dan anak yang jarang sekali bertemu, pertama kali yang Hamid tanyakan tentu kabar ibunya. Pertanyaan yang hanya sebaris itu saja, membuat Halimah selalu tak mampu membendung tetesan yang mengalir dari matanya. Titik-titik kecil kerinduan menjelma kerikil yang terasa sekali menyandung sanubarinya.
Lewat surat itu juga, Hamid berkabar bahwa akan ada seseorang yang datang mengunjunginya. Seseorang itu tak lain adalah teman Hamid sendiri, juga bekas murid Halimah semasa perjuangan membangun sekolah di kampung itu.
***
Ihsan berdiri termangu di depan sebuah rumah. Di antara sekian banyak perubahan yang terjadi di kampung itu yang ia lihat sepanjang jalan, satu-satunya yang masih bertahan adalah rumah itu. Jejeran bunga menur yang memagari bagian depan rumah itu membuatnya tersenyum simpul. Ia pernah bersembunyi di balik rimbun menur pada suatu siang saat bermain dengan Hamid. Sampai-sampai tubuhnya membengkak terkena ulat bulu.
Di ujung pintu, berjarak beberapa meter, Halimah berdiri dengan senyum teduh. Matanya tak lepas dari sosok yang berada di dekat bunga-bunga menur miliknya. Berdiri tegap dengan selengkung senyum manis, Ihsan tapak sangat berwibawa. Apalagi postur tubuhnya yang tinggi tegap sangat serasi dengan setelan kemeja dan celana yang ia kenakan, meskipun kemeja panjang berwarna biru laut itu digulung sebatas siku.
Ihsan Wicaksana adalah teman masa kecil Hamid. Ia adalah bekas Murid Halimah yang paling menonjol dibanding teman-temannya. Selain memang, ia anak tunggal dari seorang pengepul cengkeh di kampung itu, Ihsan adalah satu-satunya kuda hitam Hamid di kelas.
“Selamat pagi, Bu,” ucap Ihsan santun. Harum menur yang semerbak mengiringi pertemuan guru dan murid itu.
Halimah pun membalas senyumnya, “Selamat pagi, Pak Bupati, mari silakan masuk,” ajak Halimah tak kalah sopan.
Kali ini, Ihsan tersenyum canggung mendengar sapaan ‘Pak’ dari gurunya sendiri, meskipun yang memanggil justru tak canggung sama sekali. Halimah sudah terbiasa seperti itu jika bertemu dengan bekas murid-muridnya yang datang ke rumah. Banyak dari mereka yang lantas meminta foto bersama dengan pose yang aneh-aneh. Apalagi murid perempuan. Dengan semangat, mereka lantas menceritakan jika foto itu diunggah ke media sosial dan banyak teman-teman lain yang berkomentar.
“Begini, Bu, tentu Hamid sudah mengatakan jika saya ingin memberi sesuatu untuk sekolah tempat saya dulu menuntut ilmu. Selain bersilaturahmi dengan Ibu tentunya.”
“Oh ya? Jadi Pak Bupati mau mengajar di sekolah?” Ihsan tahu, Halimah sedang berkelakar. Sapaan untuknya memang terasa risi lama-lama. Namun begitu, tawa mereka pecah bersamaan.
“Oh, jika ada waktu, barangkali saya akan sering berkunjung ke sana, tetapi…”
“Kalau yang Pak Bupati maksud tentang pembangunan sekolah, seperti yang ditulis Hamid dalam suratnya, saya kira sekolah belum begitu membutuhkan, mengingat bangunan sekolah saat ini masih kokoh. Lagi pula, yang saat ini saya butuhkan adalah seorang guru pembantu,”
Kata-kata Halimah membuat Ihsan surut. Niatnya untuk mengambil hati gurunya itu, nyatanya menemui sedikit kerikil tajam. Dalam hati, ia mengumpat sebab bisa mengendus aroma penolakan yang dilakukan Halimah.
“Begini, Bu, jika Ibu merasa apa yang akan saya lakukan terlalu berlebihan, izinkan saya memberi sedikit tanda terima kasih. Satu bangunan kamar mandi saya kira tidak terlalu berlebihan.” ucap Ihsan.
Halimah terdiam beberapa saat. Banyak hal yang ia pikirkan. Jauh sebelum Ihsan datang dan setelah menerima surat dari Hamid, ia memang sudah menduga akan ada suatu maksud dari kedatangan bekas muridnya itu. Jika saja Ihsan bukan siapa-siapa, barangkali ia bisa menerima maksud itu dengan mudah, tanpa beban sebagaimana menerima sokongan dari seorang pejabat daerah.
“Ibu bisa memikirkannya beberapa waktu.” ucap Ihsan berusaha memecah kekakuan suasana.
Halimah berusaha tersenyum, “Baiklah.” jawabnya pelan.
Pertemuan dua orang itu tidak lebih dari satu jam. Setelah menghabiskan satu gelas teh dan berpamitan, Ihsan bergegas pulang. Sepanjang jalan, di dalam mobil ia teringat bagaimana ketelatenan Halimah saat mengajar dulu. Masih lekat di benaknya, Halimah bahkan pernah menjadi buruh petik cengkeh di kebun orang tuanya di saat libur sekolah. Ia dan Hamid akan bermain sepanjang hari di kebun itu.
Bagaimana? Sebuah pesan tertera di layar ponsel Ihsan. Dari seorang anggota tim suksesnya.
Lancar.
Syukurlah.
***
Halimah tiba di sekolah dengan wajah masam. Meskipun anak-anak bergantian mencium tangannya dengan takzim, pandangannya tertuju pada gundukan pasir dan beberapa karung semen yang berada di ujung halaman. Seorang tukang yang baru saja selesai menurunkan pasir itu dari bak truk, tersenyum ketika melihat kedatangannya. Ia mengatakan jika semua bahan itu dari Pak Ihsan. Bupati yang saat ini tengah menjabat dan hendak menjadi kandidat di pemilihan berikutnya.
Pagi yang biasa rekah di halaman sekolah, kini terasa redup bagi Halimah. Bayang-bayang Ihsan selalu hadir di matanya. Ia tak pernah lupa, orang tua Ihsan pun, yang saat ini tinggal di kota yang sama dengan Ihsan, dulunya ikut berjibaku mendirikan sekolah itu. Bagaimana jika Ihsan memang benar-benar ingin memberi sedikit tanda terima kasih untuknya? Rasanya sangat tak pantas jika ia menolak niat baik itu.
Kemelut hati Halimah di pagi itu, sedikit tersibak oleh kedatangan pegawai pos yang mengantar surat Hamid. Selain kabar ibunya tentu saja, Hamid menanyakan tentang kedatangan Ihsan. Hamid memang tak terlalu sering menghubungi ibunya lewat telepon jika tak ada sesuatu yang sangat mendesak. Semua lantaran sinyal yang susah didapat. Lagi pula, Halimah sendiri lebih suka membaca deretan kalimat di dalam surat daripada harus membaca lewat pesan singkat di layar ponsel yang tulisannya amat kecil.
Ibunda, saya bertemu dengan Yudi beberapa hari yang lalu. Salam takzim darinya untuk Ibunda.
Kalimat penutup di surat Hamid itu membuat ingatan Halimah melayang kembali. Ihsan sejenak hilang dari pikiran. Yudi? Bukankah Ihsan, Yudi, dan Hamid memang selalu bersama saat sekolah dulu. Ya. Yudi-lah nama anak lelaki yang sering menangis ketika Ihsan dan Hamid mendapat nilai bagus. Yudi-lah yang kerap tak mau ditinggal ibunya ketika mengantar ke sekolah. Ialah murid yang menuntut kesabaran Halimah lebih panjang, ketulusan Halimah lebih luas. Oh, betapa Halimah merasa sangat berdosa sampai-sampai ia tak ingat dengan Yudi. Terlebih, ia adalah teman Hamid, anaknya sendiri.
Suatu pagi, saat Halimah baru saja turun dari sembahyang, seseorang datang dengan tergopoh ke rumahnya.
“Bu,” panggilnya dengan suara parau.
“Ya, siapa?”
“Saya, Bu. Bu…”
“Ya, sebentar,” Halimah melongok lewat pembatas kain yang menutupi kamar.
“Oh, Bu Nia, ada apa sepagi ini datang kemari?” tanya Halimah.
“Ibu harus ke sekolah sekarang juga,”
“Ada apa, Bu?”
Bu Nia semakin terlihat resah. Guru muda yang menemani Halimah mengajar di sekolah itu, rupanya tak sanggup menjelaskan apa yang justru ingin sekali ia katakan sebelum ke rumah Halimah tadi.
“Mari, Bu,” Bu Nia berbalik badan. Halimah menyusul di belakang. Degup jantung Bu Nia hampir-hampir tak beraturan. Resah tak mampu lagi ia sembunyikan manakala suaranya mulai bergetar.
Di pagi yang sedikit berangin itu, bentangan tali berwarna kuning melingkari sekolah mulai dari pagar halaman hingga belakang bangunan. Bahan bangunan kiriman Ihsan yang teronggok di pojok, dililit beberapa tali berwarna kuning itu.
Lutut Halimah lemas. Apalagi suara isak Bu Nia tak mampu ditahan lagi. Dari sebuah koran yang terbit hari itu, dikabarkan bahwa sekolah tempat Halimah mengajar mendapat sokongan dana dari hasil korupsi pejabat daerah setempat. Saat ini, pejabat tersebut sedang dalam pemeriksaan polisi. Beberapa anak terpaksa pulang setelah mengetahui sekolah ditutup sementara. Wajah Ihsan terpampang jelas dalam halaman depan koran hari itu. Hari itu, sepotong pagi benar-benar tenggelam di halaman sekolah.
Tiga hari setelah itu, di suatu sore yang diiringi gerimis tipis, seseorang datang ke rumah Halimah. Setelah pemeriksaan yang dilakukan kepadanya, hari-hari Halimah terasa semakin nelangsa. Mengharapkan kepulangan Hamid tentu bukan hal yang mudah. Tetapi sosok yang kini berdiri di ambang pintu itu mengingatkan Halimah pada Hamid sebab perawakan mereka yang hampir sama. Hanya saja, barangkali kulit Hamid sedikit lebih gelap.
Seseorang itu mengembangkan senyum sembari sedikit menundukkan kepalanya. Ketika melihat Halimah mengernyit, senyumnya justru semakin lebar seolah menertawakan kebingungan pemilik rumah. Namun, kemudian ponsel Halimah bergetar. Meski awalnya ia enggan menjawab panggilan itu, dengan isyarat tangan, tamu itu menyuruh Halimah untuk menjawab teleponnya.
“Sudah sampai, Bu?” suara Hamid terdengar putus-putus.
Halimah justru berbalik kepada tamunya. Diiringi senyum yang kini terkembang di bibir kedua orang di ambang pintu itu, ada sebuah kenangan masa lalu yang lambat laun tergambar di ingatan Halimah. Yang kini berada di hadapannya, lantas menjabat dan mencium tangannya berulang-ulang, tak lain adalah anak yang dulunya sering menangis jika Hamid mendapat nilai bagus. Sesuai surat Hamid beberapa waktu sebelumnya, ia memang bekerja menjadi seorang pengacara profesional.
“Izinkan saya mendampingi Ibu,” kata Yudi penuh takzim.
Halimah mengangguk. Ia tak mampu berkata-kata meskipun matanya berkaca-kaca.[]
Gemolong, 2020
*LATIF NUR JANAH, lahir dan besar di Gemolong, Sragen. Menulis fiksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Cerpennya berjudul Sidomukti Setengah Jadi terpilih sebagai juara pertama lomba menulis cerpen yang diadakan oleh Bea Cukai Banyuwangi (2019). Novel digitalnya berjudul Pundung menjadi juara kedua kompetisi menulis novel di platform Storial.co (2019). Beberapa tulisannya juga dimuat di media cetak maupun online.