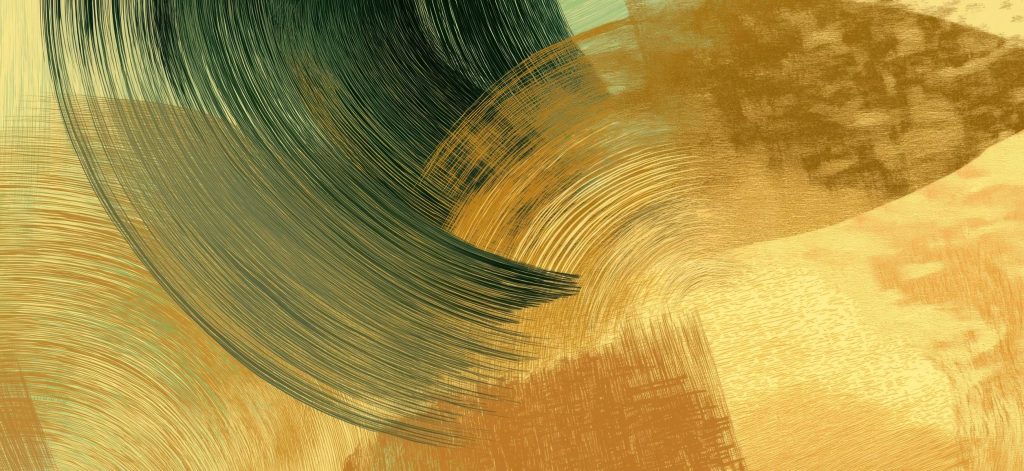Oleh : Mohammad Afin Masrija
Tak ada yang lebih menakutkan bagi petani selain langit yang membatu.
Di Sumbermulyo, tanah telah lama kehilangan ingatan tentang air. Retakan-retakan di sawah menjalar seperti urat di punggung orang tua. Padi menguning sebelum waktunya, jagung berdiri kurus seperti anak yatim, dan sumur-sumur tinggal cerita. Ancaman gagal panen bukan lagi wacana, ia telah berdiri di depan pintu, mengetuk dengan keras.
“Kalau sampai sebulan lagi begini, habis kita semua,” gumam Pak Mulyo, petani tua yang sehari-hari menjaga sawah sambil mengunyah tembakau. Ia menepuk tanah retak di dekat kakinya.
- Iklan -
“Kita ini salah apa sampai langit pelit begini?” sahut Bu Rahmi, yang baru saja menjerang air setetes pun tak keluar dari ceretnya. Suaranya getir.
“Lihat ini, Pak! Sawah saya retak sampai ke akar padi!” teriak Gino sambil menepuk pipinya yang panas.
Kepala Desa Gimrin berkacak pinggang menatap luasnya sawah yang merekah. “Ini serius. Kalau tidak ada hujan, tahun ini kita akan kelaparan. Ternak mati, padi habis… kita sudah kehabisan akal.”
Kecemasan menjadi udara sehari-hari. Orang-orang mudah tersinggung, mudah curiga, mudah putus asa. Di pasar, dagangan berantakan karena tak ada yang mau membeli hasil sawah yang layu. Di rumah-rumah, anak-anak menangis karena sumur kering, dan ternak terus melenguh lapar.
Akhirnya, dalam musyawarah desa yang berlangsung singkat namun panas, mereka sepakat: shalat istisqa. Doa bersama. Bahkan ritual adat pun akan disertakan. Semua jalan akan ditempuh, asal hujan turun.
Lapangan desa disulap menjadi tempat sujud massal. Ulama-ulama terkenal didatangkan. Ada yang berjubah putih bersih, ada yang bersorban besar, ada yang suaranya merdu seperti imam masjid televisi.
Doa-doa panjang dilangitkan. Tangan-tangan terangkat, air mata jatuh ke tanah yang kering.
“Ya Allah… hamba-Mu ini lemah… kami tak mampu lagi,” isak seorang kiai sepuh, suaranya bergetar.
“Amin… amin,” jamaah menyahut serempak, tapi langit tetap biru. Awan tak singgah. Angin pun malas bergerak.
Beberapa hari berlalu. Hasilnya nihil. Kepala desa, Gimrin, terlihat semakin lesu. Setiap malam ia tidur dengan rasa bersalah—merasakan tanah, sawah, dan ternak yang seolah memintanya untuk melakukan sesuatu, sesuatu yang lebih dari sekadar doa dan ritual biasa.
Hari berikutnya, mereka mencoba jalur lain. Dukun-dukun sakti diundang. Ada yang datang dari lereng gunung, ada yang mengaku pernah “menurunkan hujan” di desa sebelah. Kemenyan dibakar. Asap mengepul. Ada kemenyan biasa, ada pula yang bunyinya meletup-letup seperti kembang api tahun baru.
“Semoga hujan turun, ya!” gumam dukun tua sambil mengibaskan tangan,
“Inilah kemenyan langit, khusus untuk memanggil awan!”
“Ini kemenyan paling mahal,” kata seorang dukun dengan nada meyakinkan.
“Kalau ini gagal, saya berhenti jadi dukun.”
Namun langit tetap keras kepala. Tak setetes pun air jatuh. Beberapa warga mulai menggerutu:
“Kalau begini terus, sawah kita habis… dan mereka bilang bisa menurunkan hujan? Hahaha, lucu sekali!”
Tawa getir bercampur cemas. Malam-malam di Sumbermulyo semakin panjang, semakin sunyi.
MIMPI GIMRIN
Pada malam keputusasaan itu, Gimrin—kepala desa Sumbermulyo—terlelap dengan kepala penuh beban. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Seekor burung beo berwarna hijau menyala hinggap di jendela.
“Gimrin… kalau mau hujan, carilah Kyai Mimbar,” kata burung itu fasih.
“Siapa Kyai Mimbar?” tanya Gimrin dalam mimpi.
Burung itu hanya terkekeh, lalu terbang sambil mengulang-ulang, “Kyai Mimbar… Kyai Mimbar…”
Gimrin terbangun dengan dada berdebar, seolah mimpi itu membawa tanggung jawab nyata.
Pagi harinya ia bertanya ke sana-sini. Nama itu akhirnya mengarah ke kecamatan sebelah. Gambaran yang ia dapat jauh dari bayangan ulama: seorang pria berdada bidang, rambut acak-acakan, sarung sering ngeper, tingkahnya ngawur seperti pemain ludruk.
“Lho, serius itu?” tanya Pak Mulyo ragu-ragu.
“Kalau ngawur, bukannya tambah kacau saja?”
Namun kepala desa tak menyerah. Ia menyimpulkan bahwa Kyai Mimbar adalah seorang pria dengan penampilan seperti pemain ludruk—rambut acak-acakan, dada bidang, dan tingkahnya ngawur.
“Kalau dia yang dimaksud burung beo itu, mari kita coba,” kata Gimrin.
“Masalah hasil pikir nanti!”
Maka berangkatlah kepala desa beserta beberapa perangkat. Kyai Mimbar tinggal di rumah sederhana. Ia menyambut rombongan dengan senyum lebar.
“Lho, ramai-ramai begini, ada hajatan apa?” tanyanya santai.
“Kami dari Sumbermulyo, Kyai,” kata Gimrin sopan.
“Kami mohon panjenengan memimpin doa istisqa.”
Kyai Mimbar menatap rombongan, matanya setengah terpejam.
“Waduh… saya ini belum pernah memimpin jamaah sebesar ini. Lagipula, bacaan saya… tidak fasih seperti ulama.”
Gimrin menunduk, matanya sedikit berkaca.
“Kami tidak akan mempermasalahkan bacaan. Kami hanya ingin panjenengan pimpin doa!.”
Permohonan itu akhirnya meluluhkan Kyai Mimbar. Ia menghela napas panjang sambil menatap wajah-wajah penuh harap.
“Baiklah… tapi saya butuh waktu tiga hari untuk mempersiapkan. Selama itu, banyak membaca shalawat.”
“Tapi ingat.. aku tidak menjanjikan hujan”
“Iya .. yi”
Selama tiga hari itu, penduduk Sumbermulyo berkumpul setiap sore untuk membaca shalawat, memanjatkan doa-doa kecil di rumah masing-masing, sambil sesekali menatap langit yang tak kunjung berubah. Anak-anak menari di halaman, mencoba “mengajak hujan”, sementara orang tua menunduk, menahan putus asa.
Hari ketiga tiba. Shalat istisqa digelar lagi di lapangan, semua tampak lancar dan khusuk. Beberapa berdatangan dari desa tetangga, penasaran dengan kabar Kyai Mimbar. Tangan-tangan terangkat, kepala tunduk, harapan begitu tebal di udara hingga hampir bisa diraba.
Awalnya doanya lancar tidak ada yang aneh, semua khusyuk dan khidmat. Sampai tiba-tiba…
“Tik tik tik bunyi hujan di atas genting…”
“Amin” dengan wajah bingung.
Suara itu meluncur dari mulut Kyai Mimbar—fals, sumbang, tanpa dosa.
Jamaah terperangah. Sejenak hening. Lalu:
“Lho? “Apakah… Kyai sedang bercanda?” bisik Bu Hartini ke sebelahnya.” bisik seorang ibu tua.
Beberapa jamaah menahan tawa, ada yang menahan marah, ada yang spechles—bingung tak tahu harus bereaksi apa.
“…airnya turun tidak terkira…” lanjut Kyai Mimbar, masih dengan nada fals.
“Sepertinya… ya. Tapi jangan menentang, Bu, mungkin ini bagian dari rencana Kyai,” jawab suaminya sambil mengucek mata.
Angin tiba-tiba berhembus, membawa aroma tanah basah. Awan gelap berkumpul.
“…cobalah tengok pohon dan ranting…” katanya sambil menoleh ke samping, matanya menyorot ke jamaah.
“Astaghfirullah!” seru tetua di barisan depan.
“…pohon dan ranting basah semuanya…”
Lalu—“BREESSSS!”
Hujan turun dengan derasnya. Lapangan seketika berubah menjadi lautan lumpur dan sorak sorai. Orang-orang berteriak, menari, menangis. Mereka lupa pada doa, lupa pada bacaan, bahkan lupa pada Kyai Mimbar yang berdiri tersenyum sinis di depan.
“Subhanallah! Hujan!” teriak Bu Rahmi sambil menangkupkan tangan ke langit.
“Alhamdulillah!” jawab Pak Mulyo.
Seorang pemuda menjerit, “Alhamdulillah! Akhirnya hujan!”
Seorang ibu menepuk pipinya, “Astaghfirullah… terima kasih, Ya Allah!”
Seorang anak kecil melompat, memutar-mutar payung, sambil tertawa terbahak-bahak.
Seorang pemuda menari-nari di tengah genangan air, melempar topinya ke udara.
Di tengah kegembiraan itu, Kyai Mimbar memungut sandalnya, menunduk, dan pergi pelan-pelan. Tak ada yang memperhatikan. Yang tersisa hanya hujan—dan cerita yang akan diceritakan turun-temurun: bahwa kadang langit tak menunggu doa yang fasih, melainkan hati yang jujur—meski bernada palsu.
Orang-orang berlarian ke sawah, meraba-raba tanah, menepuk-nepuk batang padi. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Suasana kacau tapi bahagia. Bahkan Pak Mulyo, yang biasanya pemalu, memeluk tetangganya dan berteriak,
“Akhirnya kita selamat!”
Sedangkan Kyai Mimbar? Ia sudah jauh, berjalan pelan di jalan setapak menuju hutan kecil di belakang rumahnya. Sesekali ia tertawa sendiri. “Hujan… akhirnya hujan juga. Tapi tidak ada yang tahu… siapa Kyai Mimbar yang sebenarnya.”
Di rumah-rumah, lampu-lampu redup berkelap-kelip karena malam mulai menjemput, dan air hujan menetes di atap. Kisah ini akan menjadi legenda, tapi Kyai Mimbar—si manusia biasa dengan nada fals—tidak pernah ingin disebut pahlawan. Ia hanyalah saksi kecil bahwa kadang keajaiban datang melalui cara yang paling absurd.
Mohammad Afin Masrija, lulusan S2 HTN dan S1 Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alumni PP Miftahul Falah Kediri dan Wahid Hasyim Yogyakarta. Guru dan pembina jurnalistik di MAN 2 Kota Kediri. Tulisannya dimuat di Duta Masyarakat, Memorandum, Majalah Aula, Majalah Mimbar, Pronesiata, MPAjatim, dan GresikSatu.