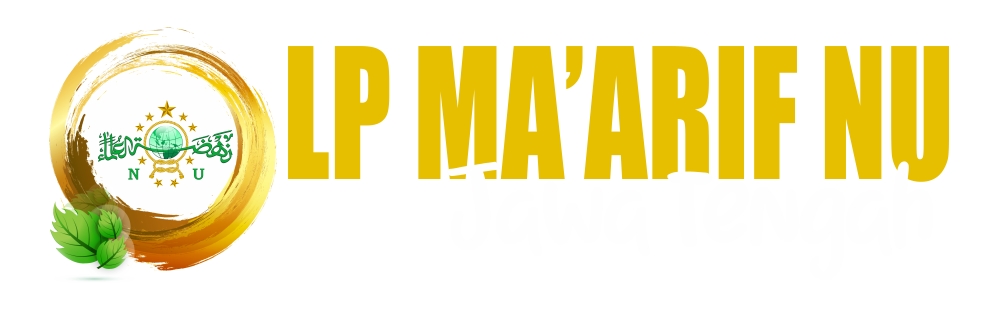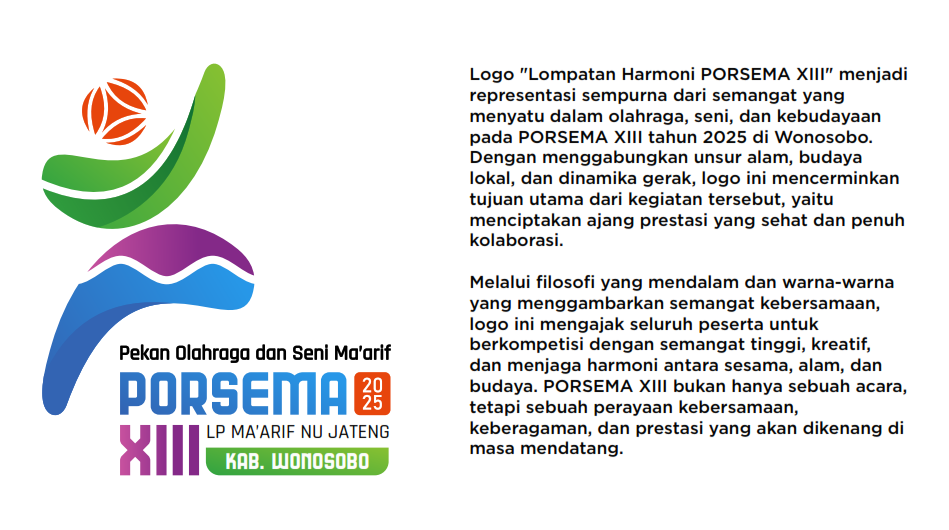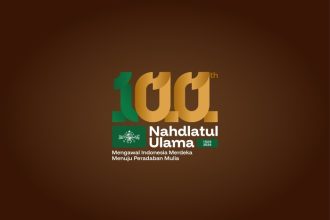Oleh Taufiq, S.Pd.I., Alh
Wisuda, dalam sejarah panjang dunia pendidikan, pada awalnya adalah prosesi seremonial yang sakral. Ia menjadi simbol keberhasilan akademik, menandai berakhirnya satu jenjang pendidikan dan dimulainya perjalanan intelektual yang baru. Namun, dalam beberapa dekade terakhir—khususnya di Indonesia—makna wisuda mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Dari momen penghargaan atas proses belajar, wisuda kini kerap menjelma menjadi ajang pamer, prestise sosial, dan beban finansial yang tidak sebanding dengan nilai edukatif yang diharapkan.
Fenomena ini semakin mencolok ketika kita melihat tren penyelenggaraan wisuda di tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP). Anak-anak yang baru saja lulus dari kelas enam, atau bahkan dari kelompok bermain, kini diarak ke panggung mengenakan toga layaknya sarjana. Mereka dipotret, diberi sertifikat kelulusan, bahkan dirayakan dalam pesta mewah dengan panggung dekoratif dan fotografer profesional. Pertanyaannya: apa sebenarnya yang sedang kita rayakan?
Pada mulanya, wisuda adalah bentuk transisi intelektual. Ia bukan sekadar perayaan kelulusan, tetapi pengakuan bahwa seseorang telah menuntaskan pendidikan tinggi dengan kemampuan berpikir kritis, penelitian, atau keahlian profesional tertentu. Wisuda sarjana, magister, dan doktor bukan hanya menyimbolkan kelulusan, tetapi juga mencerminkan pertumbuhan akademik yang penuh tantangan.
- Iklan -
Namun, belakangan ini, makna tersebut mulai kabur. Wisuda di tingkat dasar dan menengah tak lagi mencerminkan pencapaian akademik, melainkan lebih kepada pemenuhan ekspektasi sosial. Sekolah—baik negeri maupun swasta—sering menjadikan wisuda sebagai bagian dari “paket layanan pendidikan”, bahkan sebagai ajang promosi untuk menarik calon siswa baru. Semakin mewah acaranya, semakin tinggi pula “prestise” sekolah di mata masyarakat.
Dalam konteks ini, wisuda bergeser dari bentuk apresiasi menjadi komoditas. Ia bukan lagi tentang pendidikan, melainkan tentang gengsi dalam pertunjukan simbolik yang lebih mengutamakan penampilan daripada substansi. Ketika nilai-nilai seremonial melebihi makna akademik, kita perlu bertanya ulang: di mana letak nilai edukatif dari semua ini?
Salah satu dampak nyata dari “komodifikasi wisuda” adalah beban finansial yang harus ditanggung oleh orang tua. Biaya sewa toga, fotografi, konsumsi, penyewaan gedung, hingga suvenir bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per siswa. Dalam beberapa kasus, biaya tersebut bahkan menjadi syarat keikutsertaan wisuda, tanpa mempertimbangkan latar belakang ekonomi keluarga.
Bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah, hal ini tentu menjadi tekanan tersendiri. Tak sedikit orang tua yang merasa terpaksa membayar demi “harga diri anak”, agar tidak merasa dikucilkan dari teman-temannya. Mereka tidak ingin anaknya menjadi satu-satunya siswa yang tidak ikut foto bersama atau tidak mendapat piala simbolis. Maka, meskipun berat, mereka berusaha mencari jalan—bahkan jika harus berutang.
Ironisnya, pendidikan seharusnya menjadi ruang yang inklusif dan egaliter. Ketika wisuda menjadi ajang eksklusif yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu secara finansial, kita justru menciptakan ketimpangan baru dalam dunia pendidikan. Bukankah seharusnya sekolah menjadi tempat yang menyatukan, bukan memisahkan berdasarkan status ekonomi?
Wisuda mewah di jenjang pendidikan dasar juga berkontribusi pada pembentukan budaya konsumtif sejak dini. Anak-anak dibiasakan untuk mengukur keberhasilan dari apa yang dikenakan, bagaimana mereka tampil di panggung, atau seberapa megah acaranya. Ini mengaburkan pemahaman anak terhadap esensi belajar.
Alih-alih bangga karena telah belajar membaca, menulis, berhitung, atau membangun karakter, anak-anak justru mulai mengasosiasikan kelulusan dengan perayaan dan hadiah. Tanpa disadari, ini menjadi bentuk edukasi tak langsung bahwa yang penting adalah hasil yang bisa dirayakan, bukan proses belajar yang penuh perjuangan. Padahal, pendidikan dasar seharusnya menanamkan nilai kerja keras, disiplin, rasa ingin tahu, dan kolaborasi.
Ketika wisuda hanya ditekankan sebagai seremoni tanpa muatan reflektif terhadap proses belajar, maka nilai-nilai pendidikan yang hakiki dapat terkikis. Bukan hanya orang tua dan sekolah, masyarakat juga memiliki andil dalam mendorong pergeseran makna wisuda ini. Di era media sosial, prosesi wisuda menjadi konten yang dinanti. Foto anak mengenakan toga, dihujani bunga dan balon, disebarkan sebagai bukti kesuksesan. Tanpa disadari, ini memperkuat anggapan bahwa wisuda adalah indikator status sosial.
Apa dampaknya? Orang tua saling membandingkan. Sekolah berlomba-lomba membuat prosesi yang lebih spektakuler. Anak-anak didorong untuk tampil “sempurna” di hari wisuda. Semua ini membuat wisuda lebih mirip pertunjukan ketimbang perayaan intelektual. Ketika wisuda menjadi panggung sosial, bukan lagi ruang refleksi, maka yang dikejar bukan lagi ilmu, tetapi pengakuan.
Ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan yang seharusnya mendidik untuk berpikir, bukan sekadar untuk tampil. Maka, penting bagi kita semua—orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan—untuk mengembalikan makna wisuda pada esensinya.
Jika memang ingin merayakan kelulusan anak-anak di tingkat dasar atau menengah, bentuknya tidak harus mewah. Acara sederhana yang melibatkan guru, orang tua, dan teman sekelas justru bisa lebih bermakna dan mendidik. Alih-alih fokus pada dekorasi dan dokumentasi, acara kelulusan bisa diisi dengan refleksi belajar, pameran karya siswa, atau penampilan seni yang menunjukkan hasil proses pendidikan mereka. Anak-anak bisa diberikan ruang untuk menceritakan pengalaman belajarnya, kesulitan yang dihadapi, dan harapan masa depannya.
Dengan begitu, mereka tidak hanya mengenang hari wisuda sebagai “hari pakai toga”, tetapi sebagai momen di mana mereka dihargai karena telah tumbuh dan belajar. Inilah bentuk pendidikan yang lebih utuh: menghargai proses, bukan hanya hasil.
Sekolah memiliki posisi strategis untuk merumuskan ulang konsep wisuda. Kepala sekolah dan guru bisa menolak budaya konsumtif yang berlebihan dan mengusulkan bentuk perayaan yang lebih substantif. Sekolah bisa membatasi biaya yang harus dikeluarkan orang tua, atau bahkan menyelenggarakan acara kelulusan tanpa pungutan sama sekali.
Sebagian sekolah progresif telah memulai langkah ini. Alih-alih wisuda formal, mereka mengadakan “hari keluarga”, “pameran hasil belajar”, atau “festival kelas akhir”. Acara seperti ini lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif dari siswa. Yang terpenting, tidak menjadikan acara pendidikan sebagai beban ekonomi.
Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama adalah: apakah pendidikan hari ini benar-benar bertujuan mencerdaskan, atau sekadar menyenangkan secara visual?
Jika wisuda hanya menjadi ajang gengsi, maka kita telah melenceng jauh dari misi awal pendidikan. Sebaliknya, jika kita mampu mengembalikan wisuda ke jalur yang benar—sebagai momen reflektif, apresiatif, dan membumi—maka kita sedang menanamkan nilai yang jauh lebih penting daripada sekadar kelulusan: yaitu penghargaan terhadap proses belajar itu sendiri.
Sudah saatnya kita berhenti menjadikan anak-anak sebagai objek dalam pertunjukan sosial. Mari kita kembalikan pendidikan kepada esensinya: membentuk manusia yang berpikir, bukan sekadar tampil.
— Pendidik MA Andalusia, Sukoharjo Wonosobo