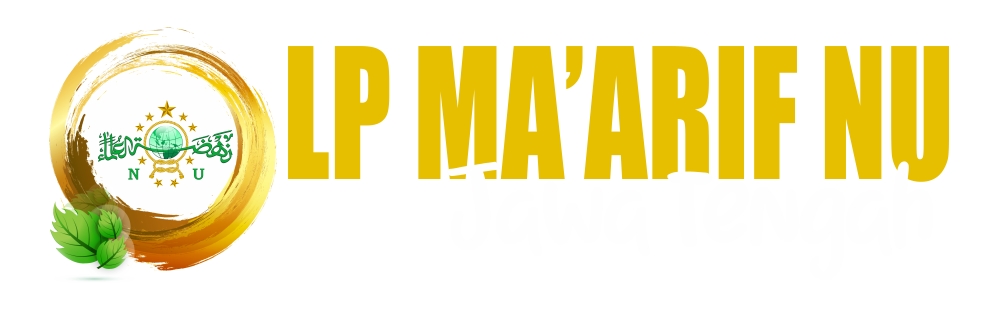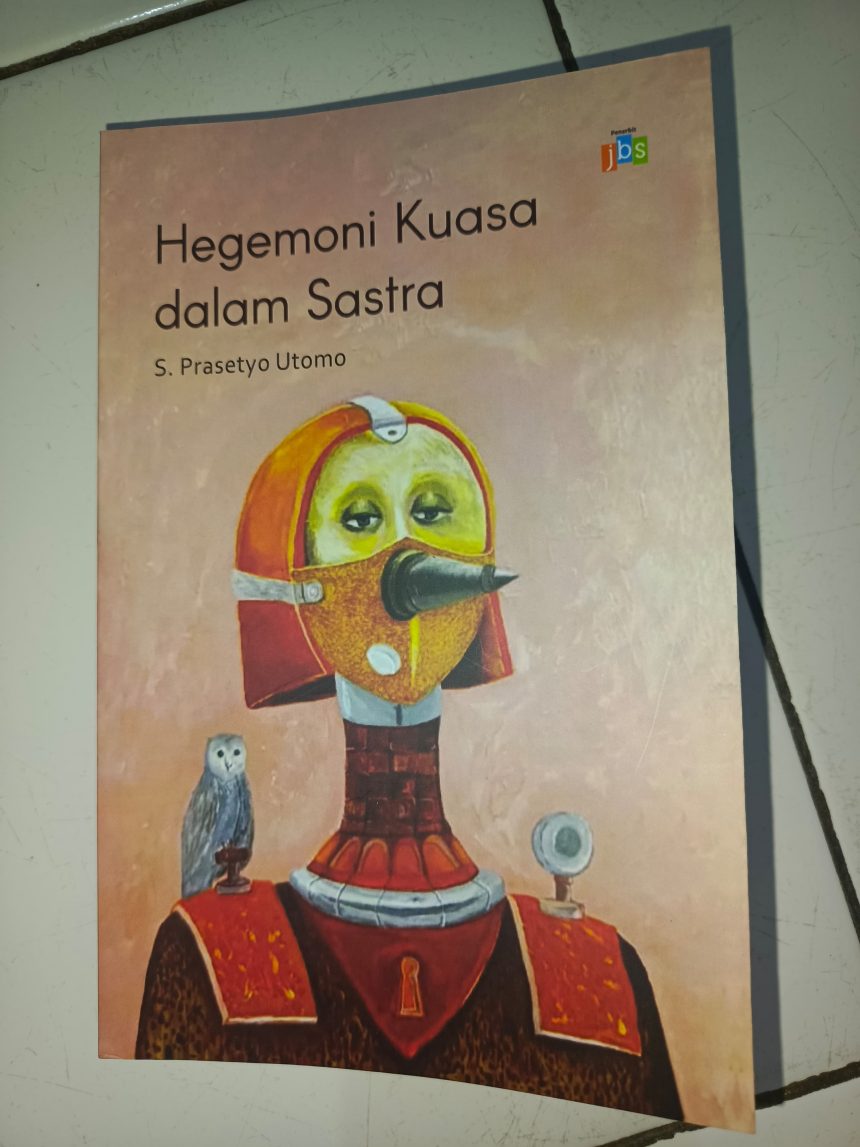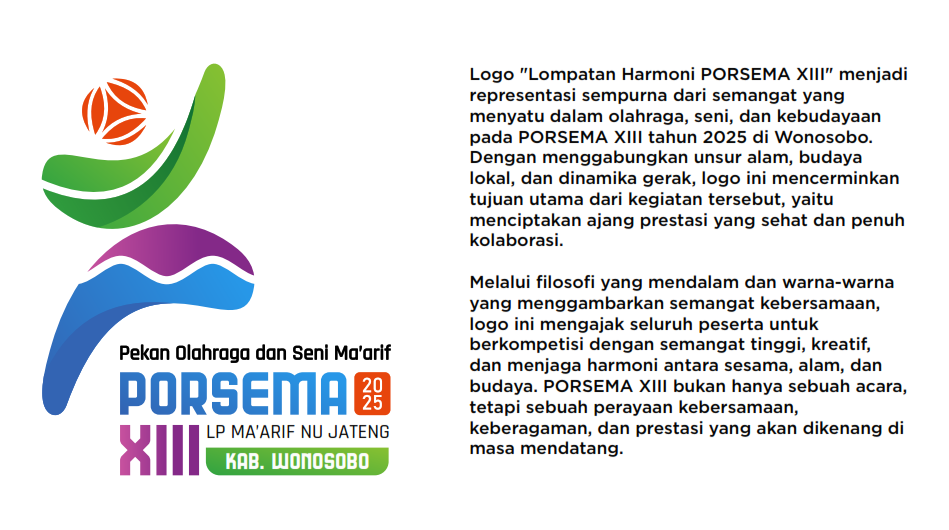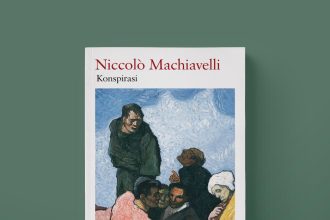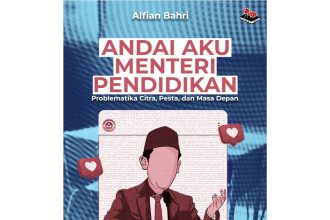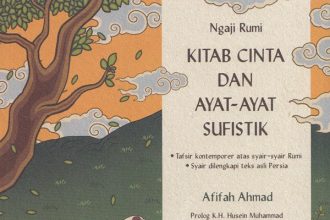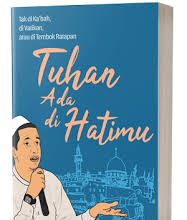Oleh: Alexander Robert Nainggolan *
Tidak dapat dipungkiri kekuasaan kerap menjadi tema besar bagi sebagian karya sastra Indonesia, terlepas dari puisi, cerpen atau novel. Segala hal yang melingkupinya dengan sebaran sudut pandang terhadap peristiwa, katakanlah sejarah yang memayunginya. Maka tak heran pula, pada sejumlah karya sastra pasang surut sejarah (politik) turut menjadi pemicu, baik sekadar pelengkap ataupun gagasan besar dari karya itu sendiri.
Dan S. Prasetyo Utomo, kritikus yang juga penggiat puisi, cerpen, novel dan esai—menyuguhkan esai-esainya dalam buku ini, yang bersentral pada bagaimana upaya sastrawan mengupas sejumlah pusat kekuasaan. Esai-esai yang terkumpul merupakan pertalian panjang terhadap kondisi terkini, baik menghidupkan lagi “sejarah” kita yang carut marut di masa lampau ataupun sekadar mememaparkan pelbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini.
Prasetyo terasa cermat menmyuguhkan setiap bagian hingga terpilah menjadi tiga bagian sesuai dengan genre karya sastra: novel, cerpen dan puisi. Bagaimana ia menjabarkan setiap karya, menguliti hal-hal yang menjadi titik pusat. Ia menyisir hampir pada sebagian novel terkini, mulai dari Laksmi Pamuntjak, Seno Gumira Ajidarma, Goenawan Mohammad, Sapardi Djoko Damono, Arafat Nur, hingga Ernie Aladjai.
Simak saja bagaimana seorang Goenawan Mohammad yang dikenal melalui puisinya, ternyata juga menulis novel pendek Surti +Tiga Sawunggaling, yang dipilah oleh Prasetyo dalam esai “Konfrontasi Kolonial dan Sprittualitas”, ia menulis:
Dalam pandangan saya, Goenawan Mohammad mengubah mitos burung sawunggalinmg ke dalam pemaknaan baru, sebuah motif untuk menghadirkan struktur narasi dan kisah yang menyentuh pembebasan spritualitas terhadap hegemini kekuasaan colonial. Lebih lanjut: Goenawan Mohammad mengarahkan daya ciptanya untuk kembali pada identitas budaya dan spritualitasnya sendiri dalam konfrontasi hegemoni kekuasaan kolonial, menjauhi jejak-jejak hibrida budaya kolonial. Ia merefleksikan pandangan dunia yang tak terkikis otoritas kolonial. (hal.47 -59)
Buku ini terdiri dari 23 esai yang telah dipublikasikan di berbagai media. Setiap esai berdiri sendiri, meskipun ketika membacanya ada semacam benang merah yang hendak dijabarkan Prasetyo: ihwal kekuasaan kelam dan mencekam. Usaha untuk memaparkan secara komprehensif bagaimana sudut sejarah direka ulang, tidak hanya menyuguhkan hal-hal baik semata namun juga manjabarkan segala tragedi yang ada di dalamnya.
Bagaimana Prasetyo menukil cerita pendek yang ditulis Sori Siregar dalam persepsinya lewat esai “Narasi Konfrontasi Hegemini Sori Siregar”:
Sori Siregar telah menciptakan narasi konfrontasi terhadap hegemoni kekuasaan, dengan jalan melancarkan kekuatan koersif, bahkan melakukan pembunuhan. Ia menarasikan sebuah perilaku kekerasan dan terorisme yang memberi pelajaran untuk melawan hegemoni kekuasaan yang merugikan rakyat dengan kekuatan koersif yang sama kejinya. (hal. 111)
Pun saat membahas dunia puisi, Prasetyo menulis esai “Satire Puisi Kebangsaan”, sebuah kritik sosial yang panjang dengan menjabarkan beberapa puisiyang ditulis penyair-penyair kita. Bagi Prasetyo:
Saya tak bisa mungkir bahwa memang berkembang pengaruh politik pragmatis dalam penciuptaan puisi. Akan tetapi, bukan berartibahwa puisi lantas diturunkan kadar estetikanya sebagai untaian Bahasa verbal yang menyerang kubu politik tertentu. Teks puisi yang mengekspresikan satire-kritik, parodi atau sindiran-menghadirkan estetika oposisi, dengan penafsiran yang tak terduga, untuk menciptakan norma-noirma pandangan yang baru. Penyair menciptakan kode-kode baru. (Hal. 119)
Pada penutup esai ini, Prasetyo menuliskan juga: Betapapun tajam kritik yang dilontarkan penyair, tidak untuk melukai siapa pun, kecuali untuk mencapai katarsis. Satire kebangsaan dalam puisi justru untuk meneguhkan kecintaan pada bangsa dan negara. Sartire mempertajam nilai dan makna dalam dunia kepenyairan. (Hal. 122)
Dan memang sebuah puisi ditulis untuk melakukan penyucian ulang, seperti melepaskan perasaan yang berkerlip, membentuk sebuah transenden baru yang perlu. Dalam bahasa Wahyu Wibowo, penyucian macam itu disebut katarsis. Dalam tubuh sebuah puisi, barangkali cuaca akan menjadi lebih gelap, padahal yang dilihat pembaca begitu terang.
Akhirnya memang sebagaimana yang pernah diungkapkan Sutardji Calzoum Bachri, bila puisi bukanlah tangan yang segera bisa mengubah atau memperbaiki realitas—yang tentunya membutuhkan waktu panjang untuk hal tersebut. Kecenderungan gemas dan kesal terhadap realitas socsial acap menggoda penyair secara terus-menerus sehingga ingin menciptakan “tangan” dalam puisi-puisinya.
Pengingat
Ada ungkapan yang terkenal dari Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy, “Jika politik bengkok, maka puisi meluruskan,”. Setidaknya hal ini menjadi pengingat, bagaimana sebuah karya sastra yang lahir memang tak pernah lepas dari sejarah dan dunia yang dipenuhi dengan kecemasan. Ia mengingatkan sebagai penanda, dengan harapan segala peristiwa kelam yang terjadi di masa lalu tak terulang lagi.
Sebagaimana yang pernah pula diungkap Nirwan Dewanto jika memang harus diakui, sejarah sastra Indonesia jadi mantap karena aksiden-aksiden politik, bukan hasil politik kebudayaan yang terus-menerus.
Dan, akhirnya memang buku ini menjadi penting, selain sebagai upaya menghidupkan dunia kritik sastra yang mulai redup—sekaligus untuk mencatat kembali dalam ingatan ihwal karya-karya yang bertebaran dalam sastra Indonesia. Sebuah karya yang membuat kita untuk menafsir lebih lama dan dalam lagi terhadap suatu peristiwa. Setidaknya, dapat membuat kita lebih kaya dan arif dalam memandang masa lalu.
Judul Buku : Hegemoni Kuasa dalam Sastra
Penulis : S. Prasetyo Utomo
Penerbit : JBS, Yogyakarta
Tahun : September 2024
Tebal : 184 halaman
Alexander Robert Nainggolan Staf Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kota Administrasi Jakarta Barat