Oleh Hamidulloh Ibda
Sembari menunggu hujan reda di titik nol Sumowono, Senin 16 Desember 2019 pukul 11.03 WIB lalu, saya membuka ingatan beberapa minggu silam pernah ditanya mahasiswa.
“Wah, ora kabeh dosen duwe Google Scholar ya, Pak. Mbah Hasyim Asy’ari duwe Google Scholar nopo boten, Pak?” tanya dia polos.
“Ojo maneh dosen, wong beberapa guru besar produk lama saja ada yang nggak punya kok,” pikirku dalam hati.
- Iklan -
Saya tak menjelaskan soal Google Scholar terlebih dulu. Namun, saya ingin dia memahami apa itu platform dari Google yang wilayahnya siber. Lalu, keharusan, atau tidak semua ilmu pengetahuan harus ada di Google atau tidak. Sebab, kini zamannya memang sudah bergeser radikal, dari konvensional menuju digital.
Saya memang pernah menjelaskan, bahwa jika ingin mengecek tingkat produktivitas dosen, akademisi, peneliti, tak perlu datang ke rumahnya dan wawancara dengan mereka. Cukup duduk ditemani kopi di rumah, dan membuka Google Scholar, lalu ketik lah nama lengkap dosen atau orang yang dimaksud. Niscaya, semua akan tampak semua, yang produktif atau pasif, akan tampak artikelnya di sana.
Memang fakta, apa saja kini kiblatnya dari internet, sedangkan Google hanya bagian dari platfom alat pencarian data. Lantaran eranya memang serba siber, wajar saja jika pelajar, guru, mahasiswa, dan dosen kita hari ini tercerabut.
Mereka belajar dari Google. Ngajinya di Youtube. Referensinya serba internet. Apa saja dianggap sebagai kebenaran ketika sudah ada di Google tanpa mau tabayun, dan mencari sumber aslinya. Titik lemah kita hari ini memang begitu. Tak hanya mahasiswa dan pelajar, dosen dan guru pun sama. Hampir semua berkiblat pada Google.
Seolah-olah, seolah-olah lo ya, Google adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Edan!
Mbah Hasyim dan Google Scholar
Kembali ke Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, pertanyaan mahasiswa saya di atas sebenarnya “punya akun” Google Scholar, bukan terindeks. Artinya, Google Scholar yang muncul sekira tahun 2004, mana mungkin Mbah Hasyim punya? Padahal, beliau wafat saja tahun 25 Juli 1947. Sedangkan Google baru muncul 4 September 1998. Beda jauh bukan?
Seiring berkembangnya zaman, Google sebagai perusahaan memiliki banyak embrio. Pada produk, Google memiliki delapan jenis, mulai dalam bidang periklanan, aplikasi pencarian, komunikasi, telepon genggam, hiburan, promosi produk Google, produk turunan, dan lainnya.
Sedangkan Google Cendekia atau dikenal Google Scholar sendiri baru menetas tahun 2004. Catatan Susrini (2009: 13), Google Scholar didefinisikan sebagai layanan yang memungkinkan pengguna malakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi. Indeks Google Cendekia meliputi jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah.
Google Cendekia menyediakan cara yang mudah untuk mencari literatur akademis secara luas. Kita dapat mencari di seluruh bidang ilmu dan referensi dari satu tempat. Seperti makalah peer-reviewed, tesis, buku, abstrak, dan artikel, dari penerbit akademis, komunitas profesional, pusat data pracetak, universitas, dan organisasi akademis lainnya.
Jadi sudah jelas, Mbah Hasyim lebih sepuh daripada Google maupun Google Scholar itu sendiri. Maka, beliau jelas-jelas tidak punya, karena beliau belajarnya bukan pada Google. Justru, yang ada adalah sitasi, kajian, artikel, riset tentang Mbah Hasyim yang dimuat atau diindeks oleh Google Scholar.
Ketika saya mengetik dengan kata kunci “KH. Hasyim Asy’ari”, muncul 16 penelusuran terkait di Google Scholar tentang KH. Hasyim Asy’ari. Seperti Hasyim Asy ari pendidikan, Hasyim Asy ari pemikiran, Hasyim Asy ari siswa kelas, Hasyim Asy ari Islam, Hasyim Asy ari pembelajaran, Hasyim Asy ari tahun, Hasyim Asy ari MTs, Hasyim Asy ari belajar, Hasyim Asy ari biografi, Hasyim Asy ari allim, Hasyim Asy ari Risalah, Hasyim Asy ari pesantren, Hasyim Asy ari ulama, Hasyim Asy ari metode, Hasyim Asy ari konsep, Hasyim Asy ari Indonesia, dan lainnya.
Data ini membuktikan, kelasnya Mbah Hasyim bukanlah dosen yang wajib memiliki Google Scholar. Mbah Hasyim ya gurunya guru. Dosennya dosen. Gurunya guru besar. Kiainya kiai. Ulamanya ulama. Beliau adalah sumber ilmu pengetahuan yang dikaji, diteliti, kemudian dijadikan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah yang terindeks Google Scholar.
Mengapa? Sebab, beliau sesuai kata kunci di atas, kelasnya sudah dikaji pemikirannya, kitabnya, biografinya, peran perjuangannya, juga lembaga yang menjadikan nama beliau sebagai nama lembaga atau sekolah.
Sebagai dosen yang sehari-hari menulis, saya memaknai bahwa dunia akademik kita memang dijajah. Mengapa? Seorang dosen jika ingin naik pangkat contohkan saja dari dosen tetap menjadi Penata Tingkat 1 (IIIB) atau Asisten Ahli, harus menulis artikel di jurnal ilmiah yang online. Begitu juga nanti ketika mau menuju Lektor, Lektor Kepala, sampai Guru Besar (Profesor), harus menulis artikel ilmiah di jurnal yang diwajibkan terindeks Sinta 1-6, Scopus, Scimago Journal & Country Rank, Thomson Reuters, dan lainnya.
Semua kiblanya dari barat, dan Kemdikbud atau Dikti belum berdaulat untuk menentukan ukuran jurnal atau publikasi ilmiah sebagai luaran dosen. Dosen yang tidak dapat menulis artikel ilmiah yang diindeks Scopus, maka sampai matek pun mereka tak bakalan bisa jadi profesor.
Dus, bagaimana dengan Mbah Hasyim? Jelas tidak perlu punya akun Google Scholar apalagi harus terindeks Scopus. Beliau tanpa punya akun Google Scholar pun sudah menjadi Hadratussyaikh. Menurut Gus Muwaffiq pun, gelar ini bukan gelar sembarangan karena Hadratussyaikh hanya diberikan kepada mereka yang “alim al-allamah”.
Pemilik gelar ini harus ngelotok Bahasa Arab, hafal Alquran, hafal kitab-kitab babon hadits dari Kutubus Sittah yang meliputi Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Bukhori Muslim, Sunan Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, Ibnu Majah, dan lainnya.
Jika ada pertanyaan, kan kita bukan Mbah Hasyim Asy’ari? Ya benar. Makanya, kita oke-oke saja harus punya akun Google Scholar, namun bukan berarti yang tidak punya Google Scholar itu bodoh dan tidak punya karya.
Hanya saja, kini dunia akademik mengharuskan demikian. Untuk punya artikel yang terindeks Google Scholar kita harus menulis dan diterbitkan di jurnal ilmiah yang berplatform OJS. Belum lagi gengsi harus terindeks di Moraref, Base, IndonesiaOneSearch, Neliti.com, Researchgate.net, Academia Edu, Issu, Garuda Ristekdikti, hingga Sinta dan Scopus.
Oleh karena itu, tugas kita sebagai akademisi, pemikir, guru, dosen, mahasiswa, dan pelajar NU harus menguasai Google termasuk Google Scholar dan mengisinya dengan konten-konten bernas dan moderat.
Sebab, kita bukan Mbah Hasyim yang memiliki gelar Hadratussyaikh tanpa harus memiliki Google Scholar terlebih dahulu. Menjadi Mbah Hasyim sangat mustahil, kita hanya bisa ndepe-ndepe untuk diakui menjadi santrinya. Tapi untuk menguasai Google Scholar, sangatlah mungkin. Benar tidak? Jika tidak kita, lalu siapa lagi?
-Penulis adalah dosen dan Kaprodi PGMI STAINU Temanggung.








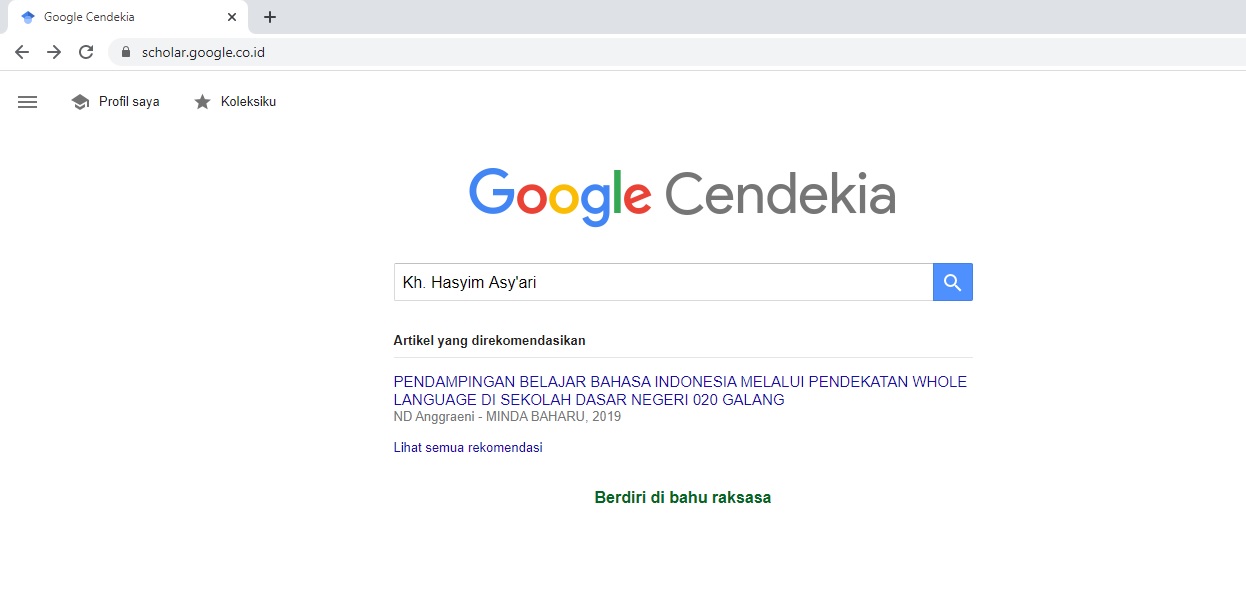








Mohon Media Ma’arif sering berhubungan sekokah2 NU daerah. Terima Kasih