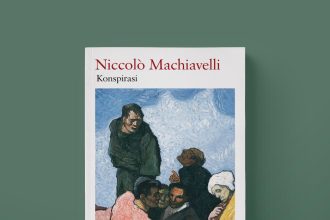Oleh: Fathorrozi
Judul Buku : Senandung Cinta dari Pesantren
Penulis : Agus Setiawan, dkk
Penerbit : Diva Press
Cetakan : I, April 2022
Tebal : 340 halaman
ISBN : 978-623-293-690-4
Sejarah telah mengukir dengan tinta emas bahwa dunia pesantren telah menghasilkan banyak karya sastra, baik berupa hikayat, kisah, cerita, serat, roman, novel, puisi, syair, hingga nadzam. Tersebutlah beberapa nama yang populer: KH. A. Mustofa Bisri, Emha Ainun Nadjib, KH. D. Zawawi Imron, Ahmad Tohari, Aguk Irawan MN, Habiburrahman El Shirazy, Ahmad Fuadi, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang jebolan pesantren yang kemudian populer dengan sebutan penulis, sastrawan, penyair, dan budayawan.
Dengan demikian, hubungan antara dunia pesantren dengan kesusastraan tidak bisa dikatakan merupakan sesuatu yang asing. Bahkan, hubungan di antara keduanya tidak dapat lagi dipisahkan. Semangat kesusastraan di pesantren masih terus berlanjut hingga saat ini. Dinamika kehidupan pesantren menjadi isu yang strategis dalam kesusastraan Indonesia. Salah satu bukti keseriusan pesantren dalam merawat tradisi kesusastraan adalah dengan hadirnya buku berjudul Senandung Cinta dari Pesantren ini. Buku ini merupakan Seri Pesantren Menulis ke-5 dalam Lomba Menulis Cerpen Tingkat Nasional yang digelar oleh Pesantren Mahasiswa An-Najah, Purwokerto, yang diasuh oleh KH. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag.
- Iklan -
Tema yang diangkat dalam buku ini adalah “Senandung Cinta dari Pesantren”. Mengenai argumen tentang tema tersebut, dijelaskan oleh KH. D. Zawawi Imron dalam Kata Pengantar bahwa dulu di pesantren tabu berbicara soal cinta. Tetapi, bila tidak didasari cinta, apa yang bisa kita lakukan? Bahkan, mengaji kepada kiai pun harus didasari dengan cinta. Cintalah yang akan menjadikan hidup lebih berwarna, mengaji lebih semangat, dan selawat lebih bergema. Bahkan, bagi Maulana Rumi, cinta melebihi semua dogma agama. Cinta hadir untuk memeluk keseluruhan ciptaan. Cinta adalah hakikat agama yang mempersatukan keseluruhan umat manusia di dalam cahaya ke-Ilahi-an (hlm. 7).
Oleh karena itu, dunia pesantren mempersepsi cinta dengan kreatif, melalui metode dan pendekatan yang khas. Kekhasan tersebut diejawantahkan dengan cinta kepada Allah, cinta kepada nabi, cinta kepada kiai, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada teman sesama santri. Sebagaimana yang tertuang pada buku ini, cinta tersebut dipersepsi dengan beragam cerita.
Salah satunya bisa kita temukan dari cerita pertama dalam buku ini yang bertajuk Samudera Hati Kiai Ngabehi karya Agus Setiawan. Ia menggambarkan keluasan cinta seorang kiai yang meski mendapat perlakuan jahat, ia tidak menanggapinya dengan emosi, justru tetap membalasnya dengan perilaku baik. Rumah Kiai Ngabehi yang pintunya selalu terbuka untuk siapa saja itu ternyata pernah dimasuki oleh beberapa orang oportunis dan penumpang gelap. Ketika ada santri yang memberi tahu hal tersebut kepadanya, ia menjawab, “Biarkan saja. Mau orang baik, preman atau bajingan, itu kan kiriman Gusti Allah juga.”
Pesantren Kiai Ngabehi seperti rumah tanpa pintu. Hampir dua puluh empat jam selalu terbuka dan menerima siapa saja. Tamu datang silih berganti. Beragam tujuan serta latar belakang. Ada tamu yang mengadu karena tercekik rentenir, janda yang minta dicarikan pengikat hati, penderita penyakit menahun yang putus asa dengan berbagai pengobatan medis, perwakilan kelompok tani yang menolak eksploitasi tambang, guru honorer yang menunggu kepastian nasib, pedagang yang minta doa penglaris, saudara seiman yang terusir dari kampung halamannya lantaran bermazhab Syiah, jemaat gereja yang menangis sebab tempat ibadahnya disegel oleh kelompok yang merasa sebagai pemilik sah kapling surga, dan lain sebagainya (hlm. 24). Kepada semua tamu tersebut, Kiai Ngabehi selalu menyambut dan menemuinya dengan senang hati dan tanpa rasa pilih kasih. Amplop yang diberikan tamu-tamu, hanya mampir sekelebat saja ke kantongnya. Isi amplop-amplop itu seringkali dibagi-bagikan untuk para santri.
Namun, meski sebegitu baiknya sosok kiai tersebut, masih saja terdapat beberapa gelintir orang yang menaruh rasa kurang suka padanya. Hal ini terbukti ketika ia menyuruh santri membuat akun resmi pondok. Unggahan foto kiai sedang menulis rajah menjadi sorotan orang-orang yang tidak menyukainya. Beberapa komentar menyayat hati berbaris di bawah unggahan foto tersebut.
“Goblok! Tampang dukun dibilang kiai.”
“Kapan lu mati, Bangsat?”
“Orderan ceramah di gereja lagi sepi, ya? Makanya, jadi dukun lagi.” (hlm. 25).
Saat si santri yang bernama Ramli itu gusar dengan membaca berjibun komentar tersebut, ia mengadu kepada Kiai Ngabehi. Kiai merespon dengan menyuruhnya mencatat nama dan alamat rumah orang-orang itu. Ramli akhirnya dengan gesit menyusuri satu persatu akun mereka, lalu mencatat nama-namanya. Ia tersenyum, rencana balas dendam akan segera terwujud.
Beberapa hari kemudian, Ramli dipanggil kiai. Kertas yang berisi daftar nama dan alamat akun hater itu diserahkan ke kiai. Namun, tak disangka, rencana balas dendam yang disusun Ramli gagal total. Ternyata kiai malah menyuruh Ramli untuk membungkus sarung di gudang untuk dikirim satu-satu ke alamat para pembenci itu.
Kisah kedalaman cinta Kiai Ngabehi ini meninggalkan pesan agung bagi para pembaca, khususnya para pemangku pesantren dan santri, agar tetap tabah dan tidak mudah tersulut emosi tatkala mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Baik ketika menerima perlakuan tersebut secara langsung, lewat perantara orang lain, atau melalui hujatan di media sosial. Melapangkan hati dan mendinginkan pikiran dalam menghadapi tindakan semacam itu merupakan solusi yang tepat. Memaafkan kesalahan orang adalah sikap bijak yang seyogianya menjadi laku hidup para publik figur.
Dan masih banyak lagi cerita lain yang tidak kalah menarik dalam buku ini. Pendek kata, 30 cerita yang terhimpun di dalam buku ini telah cukup mempresentasikan konsep cinta yang secara umum berkelindan dalam dunia pesantren. Akhirnya, semua hal yang dilakukan dengan penuh rasa cinta, maka akan berakhir dengan indah dan bahagia.***
*) Fathorrozi, penulis lepas, tinggal di YPI Qarnul Islam Ledokombo Jember.