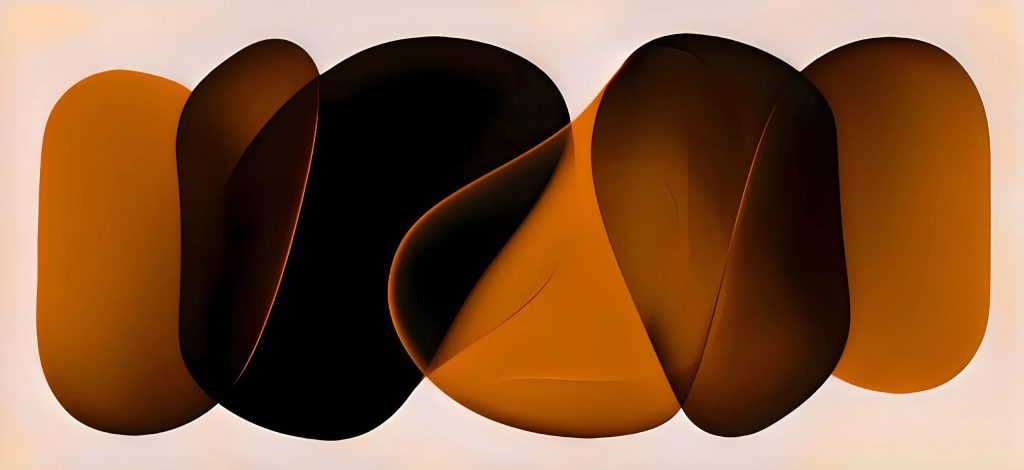Oleh : Heru Sang Amurwabumi
Getir di dada Bayu muncul ketika aroma sedap nasi gurih merayap keluar dari lubang angin-angin rumah para tetangga. Bau itu mengejek perutnya yang melilit kosong, seolah menghakimi martabat keluarganya yang lumat di pengujung hilal. Anak-anak sebayanya berlarian memikul nampan kayu dengan wajah memerah karena bangga. Bagi mereka, nampan di atas kepala adalah mahkota yang menentukan siapa yang paling mulia di hadapan Tuhan dan tetangga.
Namun, setiap kali orang-orang membicarakan hilal, bagi Bayu, yang hadir adalah sesak dada hingga membuat napasnya tersengal, tiap kali menatap tangan hampa tanpa beban hantaran. Di saat seluruh anak girang menuju tempat selamatan, ia hanya sanggup meremas ujung sarung kumal. Ia tahu bahwa ketiadaan kue apem di dapur mamaknya adalah sebuah aib yang tabu untuk dipamerkan di bawah sorot lampu langgar. Setiap tahun, jika hilal menepi, jantungnya berdegup kencang, detaknya menjadi hantaman palu yang menertawakan jemarinya yang kosong tanpa sedekah.
Bayu berdiri malu-malu, bersembunyi di balik tiang listrik, mengintip nampan-nampan yang berjejer rapi di teras langgar. Ada ayam ingkung yang montok dan tumpukan kue apem putih berseri, sementara ia hanya meringkuk dalam bayang-bayang tiang. Baginya, selamatan hari itu adalah panggung yang memamerkan kemiskinan di depan orang banyak.
- Iklan -
“Bayu! Ayo masuk!” teriak Danu sambil memikul rantang tiga susun yang sontak mengagetkan Bayu. Ia hanya meringis, sebuah senyum yang lebih mirip ringisan kesakitan, lalu berbohong bahwa ia masih menunggu mamaknya. Padahal, ia tahu mamaknya kini sedang menunduk lesu di depan tungku yang sedari pagi kehilangan lidah apinya. Tidak ada beras yang dicuci, tidak ada parutan kelapa, hanya ada kesunyian yang mengukuhkan bahwa hari ini dapur mereka telah menyerah pada keadaan.
“Mamak minta maaf, Nak,” bisik mamaknya tadi sore sambil mengelus kepala Bayu. Matanya merah. “Mamak tidak ada tepung untuk membuat apem. Mamak tidak punya nasi untuk dikirim ke langgar.”
Bayu ingat bagaimana ia hanya mengangguk pelan, lalu bergegas keluar agar mamaknya tidak melihat air matanya jatuh. Namun sekarang, berdiri di depan pintu langgar yang terang benderang, keberaniannya menciut. Baginya, Megengan yang kata orang-orang adalah selamatan pada hari saling memaafkan dan menyambut bulan suci, mendadak menjelma sebuah panggung yang memamerkan kemiskinan keluarganya di depan orang banyak.
Berkali-kali Danu berteriak memanggil, akhirnya membuat Bayu menyerah. Ia melangkah masuk dengan kepala tertunduk, duduk di pojok paling belakang, berusaha menyembunyikan diri di balik bayangan pilar kayu.
“Lho, Bayu, mana berkatmu?” suara lantang itu berasal dari Kang Laji yang sedang menghitung hantaran.
Seluruh mata di ruangan itu seolah berputar ke arahnya. Bayu merasa lantai semen langgar yang dingin tiba-tiba berubah menjadi sangat panas. Ia meremas jemari hingga kuku-kukunya memutih.
“Ketinggalan, Kang,” bisiknya lirih.
“Ketinggalan atau memang tidak membawa?” celetuk seorang anak laki-laki di barisan depan, diikuti tawa kecil dari beberapa anak lainnya.
Ustaz Mansur yang sedang merapikan sorban di depan mimbar menoleh ke arah Bayu yang gemetar. Suasana mendadak canggung. Di tengah kepungan aroma makanan yang menggoda, Bayu merasa seperti noda di kain putih yang bersih. Ia ingin lari, namun kakinya terasa terpaku pada ubin langgar.
“Sudah, sudah. Ayo kita mulai zikirnya,” potong Ustaz Mansur tenang, meski matanya tetap tertumbuk pada Bayu.
Zikir mengalun. Suara jamaah memenuhi ruangan, naik ke langit-langit, namun bagi Bayu, suara itu terasa jauh. Ia membayangkan rumahnya yang gelap. Ia membayangkan mamaknya yang mungkin sekarang sedang menangis di atas sajadah usang, merasa gagal menjadi orang tua hanya karena tidak mampu membeli segenggam tepung dan ragi.
Acara puncak selamatan Megengan adalah makan bersama. Nasi-nasi berkat itu dibuka. Aroma uap nasi yang baru matang meledak di udara. Orang-orang mulai membagi-bagikan lembaran daun pisang pengganti piring.
“Ayo, Bayu, makan yang banyak,” Kang Laji menyodorkan setangkup daun pisang berisi nasi gurih, sepotong ayam, dan dua buah kue apem.
Bayu menatap makanan itu. Lidahnya kelu. Ada rasa lapar yang hebat, tetapi ada harga diri yang lebih besar menyumbat tenggorokannya. Ia melihat teman-temannya makan dengan lahap, saling bertukar lauk, tertawa riang. Sementara itu, ia merasa setiap suapan yang akan ia ambil adalah hasil belas kasihan, bukan bagian dari perayaan.
“Saya… saya kenyang, Kang,” kata Bayu.
Ia bangkit berdiri, berpamitan dengan suara yang hampir tidak terdengar, lalu melangkah keluar dari langgar. Ia tidak tahan lagimelihat bagaimana kemiskinan membuatnya merasa terasing di rumah Tuhan sendiri.
Setengah berlari, Bayu menerobos gelap. Di atas sana, bintang-bintang yang menggantikan sang Hilal barangkali sedang memandangnya sambal tertawa. Sampai di depan rumah, ia menemukan keadaan yang sepi. Lampu minyak di ruang tamu berpijar redup.
Bayu mendorong pintu yang tidak pernah dikunci itu. Di atas meja kayu yang reyot, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku.
Ada sebuah piring retak. Di atasnya terletak sepotong kue apem yang bentuknya tidak sempurna, sedikit gosong di pinggirnya dan tidak setinggi apem-apem di langgar tadi. Di sampingnya, ada segelas air putih dan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan mamaknya yang miring.
‘Tadi Mamak bongkar celengan kaleng kita yang dulu. Cuma cukup buat membeli sedikit tepung dan gula merah. Ini Apem untukmu, Nak. Maafkan Mamak kalau Megengan tahun ini cuma begini. Mamak berangkat ke rumah Bu Bayan. Katanya beliau sudah pulang dan Mamak mau menagih upah mencuci agar besok kita bisa membeli beras untuk sahur pertama. Jangan mencariku ke sana, tunggulah di rumah saja. Selamat puasa, Anakku.”
Bayu mendekati meja. Ia menyentuh kue apem yang sudah dingin dengan ujung jarinya. Ia tahu, mamaknya pasti tidak makan demi membuat satu potong kue ini. Baginya, ini bukan tepung dan gula biasa. Ini adalah seluruh harga diri mamaknya, seluruh cintanya, dan seluruh permohonan maafnya kepada Tuhan untuk anaknya.
Tiba-tiba, sebuah langkah kaki terdengar dari arah pintu. Ustaz Mansur berdiri di sana, membawa sebuah bungkusan besar kain sarung.
“Bayu,” panggil beliau lembut.
Bayu menghapus air matanya cepat-cepat. “Ustaz? Ada apa ke sini?”
Ustaz Mansur masuk dan melihat potongan apem di atas meja, lalu tersenyum tipis. “Tadi aku mengejarmu, tapi langkahmu cepat sekali.”
Beliau meletakkan bungkusan itu di atas meja. “Di dalam ini ada nasi berkat milikku. Aku sengaja tidak memakannya di langgar karena aku ingin makan bersamamu dan mamakmu. Tapi melihat apem di meja ini…” Ustaz Mansur menjeda kalimatnya, matanya berkaca-kaca. “…aku sadar, Megengan yang paling jujur ada di rumah ini.”
“Maksud Ustaz?”
“Banyak orang membawa nampan besar ke langgar hanya untuk pamer atau menggugurkan kewajiban. Tapi mamakmu… dia memberikan yang terakhir yang dia miliki.”
Ustaz Mansur mengambil potongan apem gosong itu, membelahnya menjadi dua, dan memberikan separuhnya kepada Bayu. “Ayo makan. Kita sambut Ramadan dengan hati yang paling kaya.”
Malam itu, di bawah pendar lampu minyak yang sekarat, Bayu mengunyah kue apem paling manis yang pernah ia rasakan. Rasa pahit dari bagian yang gosong itu hilang, berganti dengan rasa hangat yang menjalar ke seluruh dadanya. Di luar, sayup-sayup terdengar suara bedug mulai bertalu-talu, menandakan panggilan Tarawih pertama akan dikumandangkan. (*)
Heru Sang Amurwabumi, Pendiri Komunitas Pegiat Literasi Nganjuk. Buku kumpulan cerpennya, Maha Pralaya Bubat (2025). Tahun 2019 terpilih sebagai emerging writer di Ubud Writers anda Readers Festival.