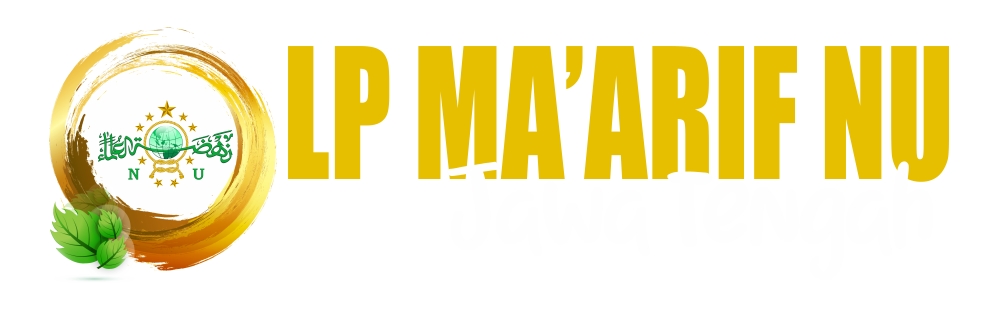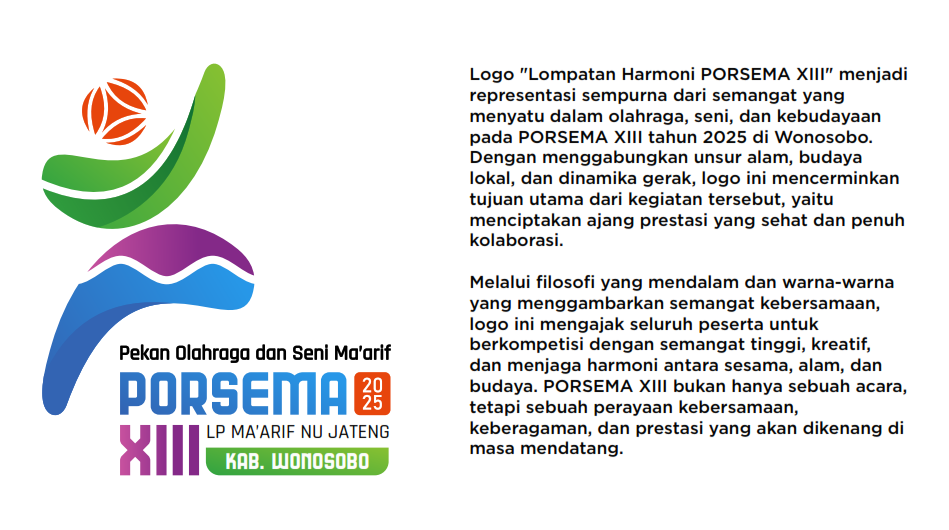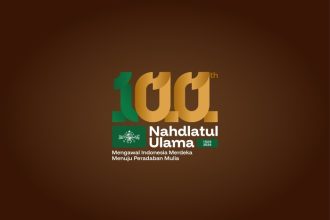*) Oleh: Tjahjono Widarmanto
/Pembuka/
Fenomena yang secara luas bisa kita amati sekarang adalah adanya kecenderungan lintas batas dalam berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. Adanya lintas batas itu ditunjukkan dengan banyaknya kemunculan lintas disiplin (interdisiplin) atau lintas studi (interstudi) dalam rahah pengetahuan, sosial, dan budaya. Kecenderungan tersebut memunculkan banyak aspek dan objek dalam kehidupan umat manusia, termasuk seni, yang mengejawantah dalam wujud multimedia dan intermedia.
- Iklan -
Teknologi digital dan teknologi informasi yang semakin canggih memegang peranan penting dalam fenomena lintas batas tersebut. Kemunculan gadget (ponsel pintar), merupakan contoh paling nyata bahwa teknologi digital dan teknologi informasi mendorong adanya lintas batas yang mewujud terciptanya multimedialitas. Gadget (ponsel pintar) diciptakan teknologi dan pada gilirannya ia menghasilkan penciptaan-pencitaan lain. Melalui piranti itu pula, manusia memasuki wilayah intermedialitas yaitu penciptaan dan pengubahan dari media satu ke media lain yang tak terduga dan tak terbayangkan sebelumnya.
Alih wahana merupakan bentuk nyata adanya lintas batas dan multimedialitas. Secara sederhana, alih wahana bisa didefinisikan sebagai pengubahan dari jenis satu bentuk kesenian ke bentuk dan jenis kesenian lain. Wahana secara harafiah berarti kendaraan; wadah. Berangkat dari makna harafiah wahana ini, maka alih wahana merupakan proses pengalihan dari satu jenis ‘kendaraan;wadah’ ke jenis ‘kendaraan;wadah lainnya. Dalam perspektif seni, wahana dimaknai sebagai medium yang dipergunakan untuk mengekspresikan, mengungkapkan, menampilkan gagasan, ide, atau perasaan. Berangkat dari uraian tersebut, maka alih wahana adalah pengubahan atau pemindahan dari sebuah bentuk seni ke bentuk seni lain, pemindahan dari sebuah media seni ke media lain.
Proses alih wahana menuntut sebuah kesediaan untuk berpikir secara multidimensional karena setidaknya melibatkan pertimbangan dua ranah dan bentuk seni yang berbeda.Dengan kata lain, alih wahana memerlukan kemampuan berpikir secara lintas disiplin yang tak dibatasi dinding-dinding formal disiplin seni dan tak boleh dibatasi dalam satu perspektif saja.
Alih wahana dalam prosesnya setidaknya mencakup tiga kegiatan yaitu penerjemahan, penyaduran, dan pemindahan. Penerjemahan yang dimaksud di sini bukan sekedar dalam makna pengalihan bahasa (translate) semata, tetapi menerjemahkan sebuah bentuk seni ke bentuk lain. Pun demikian dalam penyaduran tak semata menyadur dalam perspektif bahasa tapi pada bentuk seninya. Pengalihan pun serupa, yaitu mengalihkan dari satu bentuk dan jenis kesenian ke jenis dan bentuk seni yang lain. Kepekaan dan kebenalaran menjadi tumpuan dalam proses ini.
Dalam alih wahana diperlukan pemahaman medium yang dimanfaatkan dan digunakan untuk mengungkapkan ekspresi. Seni pada hakikatnya memiliki sifat adaptif yang memungkinkan bercampurnya antar media. Yang terpenting adalah adanya pijakan untuk ‘memahami apa saja yang berbeda dalam berbagai media itu dan bagaimana perbedaan tersebut dijembatani’. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai intermedialitas.
/Puisi dan Kemungkinan Alih Wahana/
Secara kodrati, seni memiliki adaptasi yang tinggi sehingga sangat mungkin dialihwahanakan ke dalam berbagai bentuk /media. Misalnya, puisi sebagai seni sastra yang semula teks dengan media bahasa dapat dialihwahanakan menjadi musik, dari pengindraan mata beralih ke pengindraan suara. Puisi sebagai seni sastra beralih wahana menjadi film (puisi yang di filmkan) yang menjadikannya tak hanya media bahasa tetapi juga media visual dan bunyi. Sebuah teks puisi pun sangat mungkin beralihwahana menjadi seni pertunjukan atau seni tari (sendra tari). Teks sastra berbentuk puisi dengan media aksara bisa berganti bentuk dan wujud menjadi seni pertunjukan atau sendratari dengan mengubah medianya dengan gerak dan suara. Peluang teks sastra puisi untuk alih wahana menjadi seni rupa/lukis pun cukup besar. Puisi grafis adalah contoh yang nyata.
Sebuah karya seni memiliki peluang untuk memiliki atau mengandung banyak media. Di dalam film terdapat berbagai media, ada media sastra dalam wujud naskah atau skenario, ada media suara, dan ada media visualnya. Pun dalam seni rupa, tak hanya visual, tak hanya warna tetapi juga bisa dilibatkan ‘bunyi’, ‘bau’, sesuatu yang bergerak, dan lain sebagainya. Karena dapat mengandung banyak media, maka secara logika seni dapat mberubah-ubah bentuk dan wujudnya.
Alih wahana membutuhkan mode. Secara sederhana mode dapat diartikan sebagai cara mengerjakan. Tentu saja, mode atau cara mengerjakan ini berkait pada eksplorasi yang multimodalitas (cara yang melibatkan dan mengombinasikan berbagai media). Misalnya, bagaimana mengombinasi teks sastra berupa puisi dengan imaji bunyi, dengan indera visual, audio, kinestesis, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya alih wahana secara otomatis adalah eksplorasi untuk alih mode dengan melibatkan kemungkinan kombinasi media.
Dalam proses perkembangan kesenian, sebenarnya sudah sangat lumrah jika sebuah bentuk seni mengambil unsur seni lain, baik sebagai rujukan atau sumbernya. Secara kodrati sebuah jenis kesenian membutuhkan jenis kesenian lainnya, baik sebagai acuan maupun untuk upaya proses intertekstual. Saat teknologi semakin canggih maka berbagai jenis teks (termasuk seni) bebas bergerak ke sana kemari, menggelinding ke mana-mana, berjumpalitan, dan jungkir balik untuk membentuk teks-teks lain.
Kecenderungan alih wahana sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya, kita jumpai pada tembang dalam khazanah sastra Jawa tradisional. Tembang adalah puisi Jawa klasik. Pada awalnya dicipta dalam bentuk aksara, namun kemudian “harus” dinyanyikan atau ditembangkan agar lebih nyes. Lirik tembang bisa saja dibaca lugas, tetapi kualitasnya sebagai puisi akan kurang terasa jikalau tidak ditembangkan. Dalam situasi inilah terjadi proses keterkaitan sekaligus alih wahana antara keindahan aksara—keindahan makna—keindahan bunyi. Contoh yang mirip adalah pada seni puisi di Cina dan di Arab yang menjadi seni kaligrafi yang menautkan sekaligus mengalihwahanakan keindahan aksara—keindahan makna—keindahan visual (gambar).
/Bentuk-Bentuk Alih Wahana Puisi/
Melalui paparan-paparan di atas, dapatlah diketahui bahwa setiap seni memiliki peluang besar untuk dialihwahanakan. Teks sastra berupa puisi pun memiliki peluang tersebut. Puisi sebagai salah satu bentuk seni sastra dapat dialihwahanakan menjadi berbagai seni lain. Alih wahana tersebut antara lain (1) musikalisasi puisi, (2) dramatisasi/teaterikal puisi, (3) puisi gerak (perfoming art puisi, puisi tari), (4) sinematisasi puisi (filmisasi puisi), (5) puisi rupa (puisi grafis), dan (6) instalasisasi puisi.
Musikalisasi puisi sangat mungkin dilakukan sebagai salah satu alternatif alih wahana puisi. Unsur bahasa puisi yang terkuat adalah pada bunyi, sehingga peluang puisi untuk dimusikalisasikan sangat terbuka. Musikalisasi puisi adalah alih wahana teks puisi ke seni musik. Musikalisasi puisi adalah upaya mengalihwahanakan teks puisi menjadi karya musikal. Secara sempit ada pula yang memaknai musikalisasi puisi sebagai puisi yang dinyanyikan.
Musikalisasi puisi memiliki beberapa unsur penting yang tak dapat diabaikan. Unsur-unsur tersebut adalah (1) unsur sastra (teks puisi), (2) nada dan melodi, (3) tangga nada, (4) irama/tempo, (5) penjiwaan, (6) aksentuasi penyanyi, (7) harmoni, dan (8) ekspresi.
Adapun tahap-tahap atau langkah-langkah dalam melakukan musikalisasi puisi juga membutuhkan sistematika dan kecermatan. Langkah-langkah tersebut adalah (1) menentukan atau memilih teks puisi yang akan dialihwahanakan dalam musikal; (2) menafsirkan teks puisi tersebut, baik untuk mendapatkan makna literer atau interpretasi ke warna musik yang akan dipakai, (3) mengubah teks puisi dalam bentuk partitur nada serta menentukan tangga nada untuk irama (minor biasanya untuk puisi-puisi melankolis, romantic, sedih, dll., mayor untuk puisi-puisi garang, gembira, semangat); (4) menentukan jenis musik dan alat musik; (5) menentukan pemusik dan penyanyi, dan (6) geladi.
Dramatisasi puisi atau teaterikalisasi puisi juga merupakan salah satu jenis alih wahana. Dramatisasi puisi atau teaterikalisasi puisi adalah upaya mengalihwahanakan teks puisi menjadi pertunjukan drama. Perlu dicatat, bahwa tidak semua teks puisi dapat dialihwahanakan menjadi pertunjukan drama. Teks puisi yang bisa didramakan adalah teks puisi yang (1) bersifat naratif, (2) memiliki tokoh, dan (3) mengandung tragedi.
Unsur-unsur dramatisasi/teaterikalisasi puisi adalah (1) teks puisi, (2) sutradara, (3) aktor, (4) akting dan dialog, (5) properti (setting, kostum, pencahayaan, dan (6) harmoni (keselarasan). Unsur-unsur tesebut harus mewujud dalam tampilan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut, (1) menentukan teks puisi yang akan dialihwahanakan, (2) penafsiran (baik untuk mendapatkan interpretasi literer maupun penafsiran bentuk, (3) mengubah teks puisi menjadi teks drama, (4) memilih aktor dan pendukung lain, (5) menentukan properti, dan (6) berlatih.
Alih wahana sinematisasi puisi atau filmisasi puisi tak jauh berbeda dengan dramatisasi puisi. Hanya saja tidak melalui media panggung tetapi ke bentuk film dengan aspek-aspek visual film. Sinematisasi atau filmisasi puisi memiliki tantangan yang cukup berat mengingat puisi merupakan teks sastra yang relatif pendek dan tidak memiliki alur yang utuh. Dibutuhkan penafsiran yang dalam serta imajinasi yang luas untuk mewujudkan bentuk sinematisasi puisi.
Dalam upaya mengalihwahanakan puisi menjadi sinematisasi puisi harus diperhatikan beberapa unsur penting. Unsur-unsur yang harus dicermati dalam sinematisasi puisi (filmisasi puisi) ini dikategorikan dalam dua unsur yaitu unsur naratif dan unsur sinematik.
Unsur naratif berkaitan dengan struktur-struktur penceritaan atau pembentuk naratif. Unsur naratif ini meliputi (1) tema cerita, (2) plot, (3) latar (waktu, tempat, sosial, budaya, suasana), (4) pelaku/tokoh, (5) karakter (aspek psikologis), dan (6) konflik.
Adapun unsur sinematik berkaitan dengan upaya dalam mendapatkan bentuk visual film yang meliputi (1) mise on scene (dibaca: mi song skin). Istilah ini diambil dari Bahasa Perancis yang mengandung arti “segala hal yang tampak atau terlihat dalam sebuah frame”. Hal ini berkaitan dengan properti, setting, bloking, kostum, suara, dan pencahayaan; (2) sinematografi yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan teknik pengambilan gambar dan penggabungan gambar sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Unsur sinematografi merupakan elemen visual yang meliputi framing, zooming, cahaya, pergerakan kamera, sudut kamera, pilihan lensa, pemfokusan gambar, dan pilihan warna; (3) editing yang berupa proses pemotongan, penyambungan, dan penggabungan gambar untuk dijadikan cerita yang utuh; dan (4) suara, yaitu memaksimalkan suara dan bunyi untuk mebentuk efek suasana. Unsur ini dibagi dua yaitu diegetic dan non diegetic. Diegetic adalah suara yang sumber suaranya tampak di layar (misalnya, suara aktor, suara benda yang tampak, dsb). Sedangkan non diegetic adalah suara yang sumber suaranya tak tampak di layar (misalnya, instrument, ilustrasi musik, suara efek).
Contoh sinematisasi puisi (filmisasi puisi) yang bisa kita lihat adalah film karya Mel Gibson berjudul Braveheart yang diangkat dari puisi abad 15 berjudul The Wallace, film Mulan yang dilakukan oleh Allen Gisberg penyair Amerika Serikat yang mengambil puisi China berjudul Ballad of Mulan. Pun yang dilakukan Garin Nugroho dalam filmisasi puisi Bulan Tertusuk Ilalang karya Zawawi Imron.
Upaya baru dari alih wahana yang lain dilakukan oleh Afrizal Malna ketika ia membacakan puisi-puisinya dengan disertai seni instalasi. Upaya Afrizal Malna ini bisa disebut sebagai instalasisasi puisi, yaitu alih wahana teks puisi menjadi seni instalasi.
Afrizal mengubah simbol-simbol sekaligus “peristiwa” dalam puisinya menjadi simbol baru bahkan merealisasikan simbol tersebut secara nyata melalui seni instalasi yang melibatkan media suara, cahaya, slide proyektor, benda-benda, tayangan organ tubuh, dan bunyi. Mengombinasikan teks puisi dengan seni instalasi menjadikan alih wahana puisi ke bentuk seni yang lain yang kaya interpretatif.
/4/
Akhirnya, perlu saya sampaikan bahwa bentangan-bentangan paparan di atas ini hanyalah sekedar tinjauan selintas tentang alih wahana dalam tataran teoritis. Yang terpenting bagaimana bentangan-bentangan teori ini kita implimentasikan sehingga sastra memiliki potensi yang lebih luas untuk menggapai dan menjangkau masyarakat luas.
TJAHJONO WIDARMANTO
Lahir, 18 april di Ngawi, Jawa Timur. Guru, esais dan saatrawan.. Beberapa kali menerima penghargaan di bidang kesastraan antara lain, Lima Buku Puisi Terbaik versi Hari Puisi Indonesia 2016, Penghargaan Sastrawan Pendidik 2013 dari Pusat Pembinaan Bahasa, Penghargaan Guru Bahasa dan Sastra Berdedikasi 2014 dari Balai Bahasa Jawa Timur, Penghargaan Seniman Budayawan Berprestasi Jawa Timur 2002, Pemenang Sayembara Menulis Buku Pengayaan Buku Teks kategori Fiksi 2004, 2005, 2007, 2010,2013 dan 2017, Juara II LCPI tingkat nasional Komunitas Saung 2021, Esai-Esai Terbaik di Sastra Media 2022-2023, Penulis Terbaik Majalah Media Pendidikan Jawa Tmiur 2023, sepuluh nominasi Buku Sastra Pilihan Tempo 2023.
Buku-bukunya yang telah terbit Bianglala Sastra (Kumpulan Esai Sastra, 2024), Suluk Kangen Kanjeng Nabi (2024), Dari Balik Maut Kulirik Cinta (2023), Suluk Pangracutan dari Kampung arwah (2023), Qasidah Langit, Qasidah Bumi (2023), Bersepeda dari Barat ke Utara hingga Tulang Rusukku Tumbuh Bulu (buku puisi, Alang Pustaka:2021), Kitab Ibu dan Kisah-Kisah Hujan (buku puisi, Etankali:2020), Yuk, Nulis Puisi (Diva Press, 2019), Kata dan Bentuk Kata dalam Bahasa Indonesia (2019), Biografi Cinta (buku puisi, CMG:2019), Perbincangan Terakhir dengan Tuan Guru (buku puisi, Basabasi:2018), Percakapan Tan dan Riwayat Kuldi Para Pemuja Sajak (buku puisi, Satukata:2016), Pengantar Jurnalistik; Panduan Awal Penulis dan Jurnalis (cet.ke-2, Araska Publisher, 2016), Marxisme dan Sumbangannya Terhadap Teori Sastra (Satukata;2014), Sejarah yang Merambat di Tembok-Tembok Sekolah (buku puisi, Satukata:2014), Mata Air di Karang Rindu (buku puisi, Satukata:2013), Masa Depan Sastra; Mozaik Telaah dan Pengajaran Sastra (kumpulan esai sastra, Satukata:2013), Umayi (buku puisi, satukata:2012), Nasionalisme Sastra (bunga rampai esai sastra:2011), Drama; Pengantar dan Penyutradaraannya (Lingkarsastra Tanah Kapur, 2009), Mata Ibu (buku puisi, 2010), Kidung Cinta Buat Tanah Tanah Air (buku puisi 2007), Kitab Kelahiran (buku puisi, Dewan Kesenian Jatim:2003), Kubur Penyair (buku puisi, Diva Press:2002), dan Di Pusat Pusaran Angin (buku puisi, KSRB;1997).