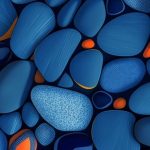*) Oleh: Tjahjono Widarmanto
Sejak kali pertama mengenal puisi, sejak itulah saya terpukau, terkejut, terperangah, terpesona bahkan tersihir olehnya. Keterpukauan, keterpesonaan, kekaguman bahkan keterkejutan itu masih saja menyihir, bahkan ketika saya sudah berkuyup sebagai penulis puisi selama 30 tahun lebih, tetap saja saat membaca sebuah puisi, bahkan saat menulis sebuah puisi, keterpukauan, keterkejutan, dan keterpesonaan itu menyergap.
Puisi telah menjadi cupu manik astagina yang membuat saya selalu ternganga. Cupu manik astagina dalam epos Ramayana merupakan kotak pandora yang di dalamnya terdapat berbagai pesona keindahan kehidupan, kebahagian, harapan, misteri sekaligus kenestapaan menjadi manusia. Cupu manik itulah yang mempesona Subali, Sugriwa dan Anjani hingga rela menjadi ‘kera’ yang selalu belajar berproses menjadi manusia dalam menjalani kehidupannya. Situasi itulah yang sepertinya menjadikan saya sebagai Subali, Sugriwa, dan Anjani.
Cupu manik astagina itulah puisi! Adalah kotak pandora yang berisikan refleksi pengalaman, pengamatan, pemikiran, penjiwaan, penghayatan, harapan, tresna, hasrat, birahi, kesia-siaan, nelangsa, cemas dan pasrah atas maut, takut sekaligus gemas dengan Tuhan, sintesis bahkan argumentasi-argumentasi atas hidup dan kehidupan, berbagai kegembiraan manusia pun penderitaan.
- Iklan -
Saat memasuki dunia kepenyairan, penyair ibarat seorang serdadu yang menghamba pada kegelisahan abadi yang dilahirkan melalui rahim kata-kata. Ia akan memasuki wilayah sunyi, dunia yang terpecah belah, dunia yang penuh kemungkinan-kemungkinan. Apalagi di situasi zaman digital yang global ini, yang menjadikan hidup, kehidupan, manusia dan kemanusiaan disergap dan dirundung tak hanya oleh perubahan, namun juga jungkir balik kejutan masa depan. Zaman yang menjadikan kehidupan dan seluruh unsur yang mewarnai eksistensi manusia menjadi terserpih-serpih dan muncrat ke mana-mana. Di sisi lain harapan untuk sebuah jagat dengan tata nilai baru yang meletakkan humanitas sebagai mahkota tampaknya semakin menjadi bayangan yang berlari runduk menjauh. Pada situasi inilah menulis puisi adalah sebuah cara untuk bernegoisasi dengan keadaan yang carut marut seperti itu.
Oleh sebab itu tak gampang menjadi penyair. Kata Zawawi Imron; menulis puisi itu hal yang mudah, namun menjadi penyair itulah yang sulit! Dengan lebih bombastis, almarhum Kriapur pernah berkata, bahwa seorang yang bercita-cita jadi penyair harus berani menjilat aspal panas. Maka, menjadi penyair tak sekedar menyangkut “jam terbang”, lebih dari itu! Seseorang yang benar-benar terpanggil menjadi penyair akan memperlakukan puisi sebagai bagian dari hidupnya bahkan menganggap puisi sebagi roh kehidupannya. Oleh karena itu tak berkelebihan kalau dengan angkuhnya Chairil berucap, yang bukan penyair dilarang ambil bagian!
Sejak berabad-abad lalu, puisi dianggap sebagai sesuatu yang istimewa bahkan nyaris suci. Di India, puisi dianggap seperti kitab suci dan disebut sebagai parajanana; penjaga kehidupan. Puisi tak hanya ditulis sebagai ekspresi personalitas yang tragis, akumulasi dari kekecewaan dan keterputusasaan atau narsis yang berlebihan, namun menjadikan ekspresi personalitas yang tragis dan segala keterputusasaan menjadi cermin untuk berkontemplasi. Segala bentuk tragedi, kekecewaan, keberputusasaan, dan segenap narsis yang berlebihan digunakan puisi untuk menggali kedalaman diri manusia sendiri. Menangkap sosok manusia yang utuh sekaligus membangkitkan pertanyaan gelisah yang tiada henti; mengapa ia harus dirumuskan dan tugas apa yang diemban oleh kehadirannya.
Lebih detil, Marcuse mengungkapkan bahwa puisi merupakan ungkapan aleinasi manusia terhadap masyarakat, alienasi terhadap dirinya sendiri, menampakkan kesadaran akan ketidakbahagiaannya, kegamangannya menghadapi dunia yang terpecah belah, membersitkan kegelisahannya menghadapi kemungkinan-kemungkinan tak terduga, harapan-harapan yang diingkari. Bahkan juga mengungkapkan dimensi manusia dan alam yang tertekan dan tertindas sekaligus mentransendir kenyataan-kenyataan pahit yang ada.
Selanjutnya, ketika saya makin suntuk menulis puisi, tak hanya ketakjuban dan keterpesonaan yang muncul, namun juga kegamangan. Kegamangan yang muncul karena saya amat menyadari bahwa keberhasilan penyair terletak pada kemampuannya menemukan bahasa. Dalam kerja kepenyairan menemukan bahasa pada hakikatnya bukan berarti sekedar mencetak kata yang sama sekali baru, namun menjadikan kata lebih bermakna, lebih privacy sekaligus universal, lebih cerah sekaligus sublim, tidak sekedar ucapan yang deras, tidak sekedar kata-kata yang berkerumun, riuh rendah, ramai namun hampa. Pendek kata, meminjam istilah Goenawan Mohamad, “Puisi adalah ihtiar agar dunia privat bisa diungkapkan dan tak boleh tertindas oleh bahasa orang ramai.”
Sebuah puisi ibaratnya adalah gema dalam menangkap dan merepresentasikan persoalan eksistensial manusia. Persoalan-persoalan eksistensial itu boleh jadi sangat abstrak bahkan abadi menjadi sebuah misteri. Tugas puisi sebagai gema adalah mengkonkritkan persoalan-persoalan eksistensial manusia tersebut. Puisi pada akhirnya merupakan gema yang merepresentasikan persoalan-persoalan eksistensial yaitu menyoal jatidiri manusia itu sendiri, mengulik hubungan dan ‘petak umpet’nya dengan Tuhannya, kemajnunannya karena cinta, ketaklukannya pada takdir, ketegangan dan kepasrahannya pada maut, dan pada akhirnya menuju ke muara penyerahan diri yang total pada Tuhan.
Pun seperti antologi-antologi puisi terdahulu, saya sering kali gelisah akan keterbatasan dan ketidakmengertian dalam mengungkapkan sesuatu, (apalagi yang bersifat misteri) dengan tuntas. Selalu saja puisi yang saya tulis, pada akhirnya hanya melahirkan lompatan-lompatan pertanyaan dan perenungan lain yang secara otomatis mengembangbiakkan fragmen-fragmen puitis baru. Dalam situasi semacam itu, tampaklah betapa berat dan payahnya mengeksplorasi, memilah, menjalin, menaut, mencipta, menemui, dan menemukan bahasa untuk mewadahi ‘kejutan-kejutan’ yang menggedor batin, rasa, dan pikir. Namun dalam situasi demikian lelah gelisah, menulis puisi adalah kewajiban sebagai salah satu alternatif jalan transendental untuk tetap menjaga eksistensi manusia agar tidak berubah wujud menjadi hewan belaka.
Puisi-puisi memang mustahil menjadi ‘jalan terang’ menelusuri persoalan-persolan eksistensial manusia, namun sebagai penyair saya menaruh harap puisi-puisi dalam kumpulan ini mampu membuat terpesona, terpukau, dan ternganga para pembacanya, setidaknya menjadikan mereka ‘tersipu-sipu’ saat membacanya.
Merayakan puisi, tidak selalu merayakan hal-hal yang menyenangkan. Bahkan dengan tegas Octavio paz dengan lantang berucap : “Puisi adalah puncak penderitaan Manusia!”
Puisi kadang hadir secara tiba-tiba melampaui kuasa penyairnya. Meledak begitu tiba-tiba. Misteri acapkali menjadi momen putika yang memantik kelahiran puisi. Seperti manusia lain, penyair selalu berhadap-hadapan dengan berbagai misteri yang meledak dalam perjalanan hidupnya, termasuk di dalamnya: derita dan tragedi. Penyair tak akan sanggup mengendalikan ledakan-ledakkan itu, apalagi menghentikannya. Ia hanya bisa mencipta ulang misteri tersebut dengan tafsir makna menurut dirinya sendiri. Ia hanya bisa membungkus dan membingkiskan momen tersebut melalui diksi dan eksplorasi bahasa agar ‘ledakan-ledakan’ tersebut bisa dirasakan dan dihayati oleh pembacanya.
Ledakan-ledakan misteri derita dan rragedi itu tetap saja menjadi rahasia, pun bagi pembaca saat membacanya. Acap kali diksi dan bahasa memasuki diri penyair bersamaan dengan ledakan-ledakan itu dalam dirinya. Datang begitu saja, berlimpahan, berjejalan, kadang halus seperti hembusan angin menyusup di jendela. Tak sedikit yang berduyun-duyun datang dengan penuh hiruk pikuk. Ada yang tiba-tiba mengedor-gedor sambil menghardik. Kadang seperti mimpi yang harus ditafsir, bahkan bisa sebagai slide peristiwa-peristiwa. Diksi dan bahasa yang berduyun itu semacam riak ombak yang menciumi pantai. Segala diksi dan bahasa yang datang itu tentu saja tergantung pada pembedaharaan dan keterbacaan penyairnya. Tak mungkin ruang kosong mampu menampung limpahan riak ombak yang berduyun-duyun itu.
Menulis puisi tidaklah selalu menuliskan hal-hal yang membahagiakan. Puisi bisa saja adalah hantu, kuntilanak, atau genderuwo yang menggendong segala hal ikhwal takut bahkan tragedi yang menggendong cemas. Puisi tak selalu hadir di pagi yang girang, melainkan bisa sebagai orkesta malam yang larut dan ngambang dalam derita. Ia derita dengan sedikit cinta. Ibu segala tragedi, ayah segala petaka dunia. Pun, saudara kembar segala rupa kejut, kecut, sangsi, serta busuk yang murung. Ia adalah bejana edan yang menampung tubuh sial. Penampung segala tinja untuk meludahi seluruh suka cita. Bukan sarang jiwa yang dengan segala lembut mengharap dan berharap cinta serta pinta disematkan. Bukan! Ia adalah penghardik sekaligus pemanggil derita, segala sakit, dan kejut dan menggendongnya pergi ke segenap mata angin. Persis peti mati penyimpan jasad yang dimummikan tanpa roh.
Pendek kata, puisi adalah arwah gentayangan yang menghardik kita! Nikmati, hardikannya!
*) Tjahjono Widarmanto, adalah Penulis, penyair, dan guru yang tinggal di Ngawi. Salah satu buku puisinya “ Percakapan Tan dan Riwayat Kuldi Para Pemuja Sajak” meraih salah satu lima buku puisi terbaik versi Hari Puisi Indonesia (HPI) 2016.