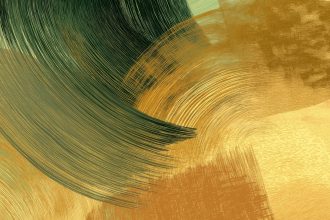Oleh Muhammad Muzadi Rizki
Saat ini, kita tengah dihadapkan dengan suatu realitas ruang publik baru bernama ruang siber (cyberspace). Ruang di mana di dalamnya memunculkan ragam platform media baru. Platform media baru ini kemudian berperan mengakomodir saling terkoneksi, bisa berdiskusi, hingga menuangkan gagasan opini secara bebas dan tak terbatas. Dampak dari kebebasan tersebut menjadikan kita semua dibanjiri informasi tiada henti.
Adalah netizen, entitas yang berperan sebagai pemasok segala informasi. Mereka terjun sebagai subyek aktif di dalam jaringan platform media tersebut. Jika menilik sikap praksisnya, dalam hemat saya netizen terbagi pada dua tipologi. Yakni, “netizen positif” dan “netizen negatif”. Netizen positif, yaitu warga internet yang menyebarkan konten/komentar memuat ajakan kebaikan. Sementara, netizen negatif diartikan sebagai warga internet yang kerap menggulirkan banalitas kekerasan (verbal/nonverbal) di media sosial.
Pada awal kemunculan, kondisinya sebenarnya steril, tidak terkontaminasi oleh apa pun. Ia hanyalah sebuah bentuk ruang, tanpa memiliki otoritas untuk mencapai keinginan ideal. Seiring berjalannya waktu, pembawa citra baik atau buruk ruang siber berasal dari pihak eksternal (netizen). Ketika netizen negatif berpenetrasi, di titik inilah musabab ruang siber berubah jadi kolam yang keruh, penuh sengkarut dan tidak sehat. Di dalamnya mengandung mobilitas ujaran kasar, perundungan, umpatan, gempuran hoaks, hingga hinaan.
- Iklan -
Salah satu peristiwa mutakhir yang membuat geger ruang publik adalah Ibu Negara, Iriana Jokowi dihina, direndahkan martabatnya oleh seorang netizen. Peristiwa itu terjadi seusai Ibu Iriana Jokowi berfoto dengan istri Presiden Korea Selatan, Kim Kun-hee di gelaran G20 Bali. Narasi yang dilontarkan sangatlah tidak etis, maknanya seolah-olah memposisikan Bu Iriana sebagai pembantu istri Presiden Korea Selatan tersebut.
Selain itu, media sosial juga dipenuhi orang-orang tanpa rekam jejak keilmuan agama yang jelas, tiba-tiba mengklaim dirinya sebagai ustaz atau mubalig. Mereka yang baru belajar sedikit dalil agama pun sangat berani bersuara membahas persoalan hukum-hukum keagamaan. Realitas keriuhan itu semua, harus segera disikapi. Hal tersebut supaya ruang publik media sosial tidak runyam berkepanjangan.
Arti Penting Tidak Tahu dan Diam
Kita adalah makhluk spesifik yang ditakdirkan berakal. Secara fitrah, fungsionalisasi akal mampu mengenali kebenaran serta cakap membedakan antara hak & batil. Akal juga berfungsi mengikat objek ilmu yang didapatkan. Meski dalam kadar tertentu, kesanggupan setiap otak dalam menyimpan ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Boleh jadi, prosesi mengikat hanya berlaku pada disiplin ilmu A. Adapun disiplin ilmu B tidak mampu terjangkau untuk diikat, disimpan di memori otak.
Dari uraian di atas mengartikan bahwa kita secara sadar, hakikatnya telah mafhum sejauh mana kapasitas keilmuan diri pribadi. Apakah baru disiplin ilmu A, atau baru menguasai disiplin ilmu B. Saya, misalnya, secara sadar mengakui bahwa ihwal ilmu kedokteran bukanlah bagian dari kapasitas pengetahuan yang saya kuasai. Maka, ketika ada suatu pembicaraan yang berlingkup ilmu kedokteran, saya tidak akan ikut campur dan memilih untuk diam.
Nabi dalam beberapa riwayat selalu memberi pesan menohok agar membiasakan diri menjaga lisan dengan baik. Sebab perannya sangat vital, keselamatan manusia tergantung dari pengamalan lisan itu sendiri. Lisan dalam tilikan masa kini, tentu tidak seliteral hanya bersifat verbal, akan tetapi lisan kita adalah jari jemari yang dimiliki, ia bisa jadi sangat tajam lewat pembuatan caption atau nada komentar.
Hal yang ingin saya tekankan di sini adalah, kita itu sadar akan kapasitas keilmuan yang dimiliki, maka mari merefleksikan diri. Mari coba kembalikan peran akal secara luhur. Yakni, jika akal hanya menjangkau disiplin ilmu A, tidak usah lantas memaksa menafsiri disiplin ilmu lainnya ke publik. Cara demikian sejatinya hanya menjatuhkan pada pendiskursusan pengetahuan yang sesat. Publik disuguhi pelbagai informasi tak valid.
Peran akal yang luhur niscaya menstimulus untuk menerapkan sikap bijak. Bijak yang dimaksud, ia cenderung akan diam bila berhadapan dengan keilmuan yang bukan digelutinya.
Semua itu berawal dari kesadaran ‘tidak tahu’ dikarenakan bukan ranah keilmuan, kemudian ‘diam’ adalah jalan yang dipilihnya. Secara rasionalitas, prinsip tidak tahu memang berbanding lurus dengan sikap diam. Sebab, bagaimana mungkin mau berbicara sesuatu, sedangkan dasar keilmuannya saja tidak dikuasai.
Tidak tahu bukanlah manifestasi dari bodoh. Justru, hal tersebut merupakan wujud ketawadukan dan kehati-hatian. Dengan memupuk prinsip tidak tahu lantas diam, kita telah memenangkan pertarungan melawan nafsu dan ego pribadi. Dampaknya, kita terhindar dari perilaku sok tahu. Lajur konten dan komentar nir-etika juga tidak eksis lagi di media sosial. Alhasil, media sosial kembali pada tatanan meneduhkan dan menebar kesejukan.
Orang bijak berkata, “diam adalah emas”. Namun sebagian orang kini, telah kehilangan emas itu akibat daya magis media sosial. Karena itu, kita sebagai subyek aktif yang arif, sudah semestinya menyadarkan akan hal tersebut. Menggali potensi, mengarahkan untuk cerdas dan berprinsip dalam bermedia sosial. Ini menjadi penting. Jika sendi-sendi etika distribusi informasi terkawal dengan bijak, keselarasan dan stabilitas sosial niscaya bakal terwujud di ruang publik. (*)
Muhammad Muzadi Rizki, penulis lepas, peminat kajian moderasi, keberagaman dan kebangsaan.