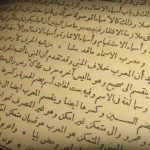Oleh Setyaningsih
Jagat memang memberi tanda Idulfitri atau Lebaran satu Syawal lewat alam raya, tetapi manusia memiliki tanda lain bernama uang. Maka di sepanjang jalan harfiah dan jalan (konon) menuju kesucian, dibukalah lapak dadakan “Tukar Uang Baru” yang sama pentingnya dengan pembukaan pintu maaf. Hati dan pikiran yang tidak tampak dibawa ke babak baru bersamaan dengan hal yang sangat terlihat: uang.
Uang adalah memori biografis manusia-manusia berlebaran. Tradisi di kampung pada masa kecil menempatkan istilah ‘pitrah’—pengucapan dengan huruf “p” dan bukan “f”. Dulu, tentu belum ada amplop-amplop komersil bergambar Elsa dari Frozen atau merek dagang Oreo atau Frisian Flag. Orangtua memiliki tujuan bersedekah—uang sebagai bagian dari ekspresi beragama. Anak-anak kecil tetap menganggapnya sebagai hiburan dan kebahagiaan tanpa perlu berpikir serius uang sebagai bentuk ekspresi beragama.
Ingat saja Lupus bocah dalam serial Lupus: Duit Lebaran (2002) garapan Hilman dan Boim. “Lupus, Pepno, dan Iko Iko memang udah lama punya rencana Lebaran muter-muter kompleks. Mau bersilaturahmi. Tapi tujuan mereka rada komersil. “Lebaran ini, kita harus bisa ngumpulin duit, dari rumah ke rumah,” usul Pepno waktu masih puasa dulu. […] Nah, itulah kenapa Lupus nggak mau diajak ber-Lebaran ke rumah Oom Jay, kakak Mami yang paling tua.” Anak-anak tahu, orang paling perhitungan soal uang sekalipun bisa mendadak loyal pada momentum Lebaran. Bukan Lupus jika tidak tahu malu, kocak, sekaligus sial. Uang Lupus dari safari kompleks tenyata jauh lebih sedikit dari uang adiknya, Lulu, yang didapat dari Om Jay.
- Iklan -
Uang atribut yang nyaris sama penting dengan mukena, sarung, masjid, ketupat dan opor, atau bahkan kitab suci. Lebaran manusia modern hampir selalu difondasi oleh kebutuhan-kebutuhan atas uang; makanan melimpah, renovasi rumah, kendaraan baru, salam tempel, Tunjangan Hari Raya (THR), bingkisan Lebaran, oleh-oleh mudik, biaya tol, atau liburan-Lebaran keluarga.
Ada humor sufistik “Darwis dan Pengemis” (2001) yang pernah disusun oleh Sapardi Djoko Damono. Alkisah, seorang darwis pergi ke rumah mandi selama beberapa jam dan mendapati pelayanan baik. Namun, darwis tidak memiliki uang sekepeng untuk membayar kenikmatan mandi. Darwis pun bertaruh harga diri dan berdoa kepada Tuhan, “Ya, Tuhan, robohkanlah saja rumah mandi ini sehingga hamba-Mu ini tidak menjadi malu lantaran tidak bisa membayar.”
Jadi, robohlah rumah mandi itu dan darwis selamat karena keluar di saat yang tepat. Kemiskinan si darwis masih diuji saat bertemu pengemis di luar rumah mandi. Pengemis meminta uang sekepeng dan darwis menjawab dengan humor satire bahwa Tuhan saja tidak punya uang, apalagi si darwis. Andai Tuhan punya uang, tentu tidak bakal dirobohkan rumah mandi itu. Uang adalah kuasa paling sadar atas keberadaan manusia di hari Lebaran.
Dilarang Lebaran
Ada semacam aturan tidak tertulis bahwa orang yang tidak punya uang dilarang Lebaran. Beban sosial membayangi saat tidak bisa merayakan Lebaran dengan layak dalam konteks uang sebagai modal sosial menyukseskan perayaan. Lingkungan tempat tinggal sering dengan sadar menciptakan standarisasi Lebaran dalam aneka bentuk konsumsi. Siapa punya uang, ia paling berhak membeli Lebaran.
Sebaliknya, Joko Pinurbo justru menuliskan realitas Lebaran yang melankolis tak beruang dalam puisi imajinatif “Baju Bulan” (2013). Seperti ini bunyi larik-lariknya, Bulan, aku mau Lebaran. Aku ingin baju baru./ tapi tak punya uang. Ibuku entah di mana sekarang,/ sedangkan ayahku hanya bisa kubayangkan./ Bolehkah, bulan, kupinjam bajumu barang semalam?/ Bulan terharu: kok masih ada yang membutuhkan/ bajunya yang kuno di antara begitu banyak warna-warni/ baju buatan. Bulan mencopot bajunya yang keperakan,/ mengenakannya pada gadis kecil yang sering ia lihat/ menangis di persimpangan jalan.
Joko Pinurbo menampilkan bulan sebagai representasi ketinggian atau puncak religius. Ada keajaiban dan berkah dari langit bagi gadis kecil sebatang kara di muka bumi. Bulan dengan bajunya yang kuno menjadi sindiran atas gemerlap duniawi. Lebaran selalu berkisar di seputar uang, baju, dan keluarga. Gadis kecil dalam puisi bahkah tidak memiliki satu pun dari ketiganya. Angan baju baru menjelma setitik cahaya ketika Lebaran mulai menuntut keinginan yang lebih besar dan harus diberesi dengan uang.
Mungkin, Tuhan memang tidak punya uang saat Lebaran. Otoritas Tuhan selesai pada sebulan penuh puasa lewat janji pahala dan surga. Uang dimiliki oleh keluarga, perusahaan, selebritas, bapak, ibu, om, tante, kakek, dan nenek. Uang harus berada di genggaman tangan. Lebaran dan uang membentuk kepastian bersama, “Ada uang, ada lebaran”.
–Setyaningsih, Penulis Kitab Cerita 2 (2021)