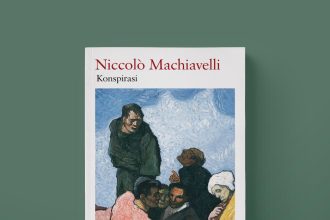Oleh Setyaningsih
Judul : Second Sister
Penulis : Chan Ho-Kei
Penerjemah : Reita Ariyanti
Penerbit : Gramedia
Cetak : Pertama, 2021
Tebal : 632 halaman
ISBN : 9786020646572
Berlatar di Hongkong dengan tipikal kebanyakan manusia hari ini: menjadi warga negara internet dan media sosial, Chan Ho-Kei menggarap Second Sister (2021) sebagai fiksi teknologis di tengah konflik psikologis manusia modern. Kesepian bisa saja seperti nasib, tapi menautkannya di jagat maya tetap sebuah pilihan. Di sini, berganti gawai lebih sering dan cepat daripada berganti kaus kaki. Rumor kehidupan pribadi seseorang tersebar begitu cepat seperti penyakit flu. Berkomentar di media sosial bisa semudah melahap pangsit panas.
Chan Ho-Kei mengawali cerita dengan kejadian pelecehan seksual di kereta berbuntut bunuh diri remaja perempuan bernama Siu-Man. Penghakiman datang dari warganet, entah keberadaan mereka sungguhan atau hanya rekayasa. Nga-Yee, kakak perempuan Siu-Man menyewa seorang detektif ‘bawah tanah’ berjuluk N. Sekejap, N memang tampak urakan, tidak berempati, dan berantakan. N lebih senang menyebut dirinya ‘Peretas Topi Putih’ untuk menyembunyikan identitas paling penting dari publik—pendiri perusahaan perangkat lunak Isotope Technologies sekaligus orang berpengaruh di Silicon Valley. Dari apartemen kumuh dan tidak mencolok, N memberikan konsultasi perangkat lunak dan keamanan data, “Seperti ketika bank mempekerjakan tukang kunci untuk mencari tahu apakah lemari besi mereka bisa dibobol,” (hlm. 425).
- Iklan -
Dalam sikap dingin yang cenderung mengesampingkan emosionalitas, justru N berhasil menyibak tekanan psikologis orang-orang yang ditemuinya. Di kasus bunuh diri Siu-Man, siapa pun berpotensi jadi tersangka. Konflik bertumpuk; kesepian karena kehilangan ibu, kelabilan masa remaja, keresahan percintaan, pertemanan, persaingan di sekolah, dan ketakutan-trauma komentar jahat. Justru hal-hal ini tidak dipahami Nga-Yee, satu-satunya kakak dan keluarga Siu-Man yang kehadirannya seperti orang asing. Di belakang kasus kematian Siu-Man, tersibak kejahatan dunia cyber yang lebih gawat dan sistematis: kejahatan seksual, bisnis informasi pribadi, situs gosip jahat.
Pilihan hidup N sebenarnya tampak sebagai paradoks. Ia memilih menyepi dan menangani kasus-kasus orang-orang yang tidak ‘berdaya’ secara status sosial ataupun ekonomi. Saat ia menciptakan perangkat teknologis untuk menyokong kepentingan modern, tidak ada tanggung jawab moral membereskan dampak di belakang. Kekayaan dan reputasi mengusik. Karena N menjadi orang yang paling tahu teknologi digital, ia justru paling sadar efek paling buruk yang justru diabaikan orang yang sekadar ‘menggunakan’.
Kejahatan Teknologi Manusia
Teknologi mengubah seseorang dengan sederhana ataupun radikal. Namun, cara berbicara, gaya bahasa tulis, atau kebiasaan sehari-hari selalu akan meninggalkan karakter khas. Seorang bisa merekayasa dirinya di balik akun palsu atau bersembunyi dalam nama samaran. Saat menyelidiki teman sekolah Siu-Man, Violet To, N sangat sadar gaya konvensional yang cenderung sulit dihilangkan teknologi secanggih apa pun, “Menurutmu bahasa kehilangan karakter individunya saat daring, Miss Au? Aku kasih contoh: Violet anak yang kutu buku, jadi bahkan surel penuh ancaman yang dia kirim ke adikmu dibuka dengan nama adikmu dan ditandatangani dengan pantas. Bahkan pesan-pesan di Line pun kalimatnya lengkap dan tanda baca dibubuhkan dengan cermat. Saat menggunakan elipsis, jumlah titiknya pasti tepat, tak lebih dan tak kurang” (hlm. 520).
“Kegilaan teknologi mengakarkan dirinya di mana-mana,” begitu kata Heidegger yang dikutip oleh Nicholas Carr dalam The Shallows (2011) yang membabar dampak internet dan cara hidup digital bagi mental (kemanusiaan) dan kebiasaan tubuh. Ada kesenangan dan kemudahan tentu saja. Teknologi memesona, menyilaukan, juga sekaligus menenggelamkan persepsi, pemikiran, emosi yang muncul hanya melalui kontemplasi dan refleksi. Kebiasaan kognitif terkikis di antara bit-bit informasi online. Hoaks berbaur tidak kentara dengan fakta. Keterampilan-keterampilan baru seperti melakukan banyak percakapan sekaligus bisa dilakukan melalui pelbagai media (sosial).
Teknologi memang sanggup mengakomodasi tindakan sosial sekaligus mencipta-memperparah konflik psikologis. Teknologi sering dianggap memicu kejahatan dan mematikan. Tapi di era orang-orang ingin tampil secara digital dengan ambisi selalu ingin menjadi ‘pakar’ dan komentator reaksioner atas orang lain, bukankah cukup memastikan bahwa setiap orang punya naluri untuk berbuat jahat? Bukan teknologi yang kejam dan merampas hak hidup, tapi para manusia penggunanya.
*Setyaningsih, tinggal di Boyolali. Pekerja buku di Penerbit Babon. Penulis Kitab Cerita 2 (2021)