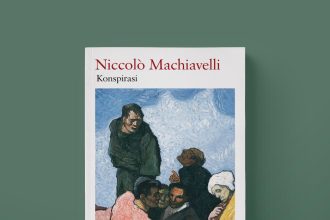Oleh: Joko Priyono*
Judul : Aku Klik maka Aku Ada: Manusia dalam Revolusi Digital
Penulis : F. Budi Hardiman
Penerbit : Kanisius
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 279 halaman
ISBN : 978-979-21-7039-9
Terbit : Pertama, Agustus 2021
Andaikan masih hidup, Alexander Graham Bell, –penemu telepon pada abad ke-19,– itu mungkin sangat murung melihat realitas saat ini. Ia akan bertanya-tanya kenapa evolusi dari telepon sampai pada teknologi sentuh layar melahirkan beragam masalah dalam kehidupan manusia. Teknologi tersebut menjadi paradoks. Di satu sisi memberikan kemudahan untuk manusia baik itu interaksi, kemudahan dalam akses informasi dan pengetahuan, serta efektivitas perkerjaan. Di sisi lain sengkarut masalah seperti banjir informasi, kabar bohong, pengetahuan semu, hingga banalitas menjadi warna dunia digital saat ini.
F. Budi Hardiman mengajak kita untuk melakukan tilikan secara mendalam dengan pendekatan filosofis tentang apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Itu sebagai upaya untuk mencari kebenaran, keindahan dan kebaikan dalam fase keberjalanan era digital. Perkembangan teknologi saat ini setidaknya telah melahirkan sebuah spesies baru bernama Homo digitalis, istilah yang digagas oleh filsuf kelahiran Uruguay, Rafael Capurro pada 2017 lalu. Mungkin terekesan berlebihan, tapi itu nyata dalam menggambarkan akan peralihan digital secara evolusioner dari keberadaan Homo sapiens.
- Iklan -
“Homo digitalis bukan sekadar pengguna gawai. Ia bereksistensi lewat gawai. Eksistensinya ditentukan oleh tindakan digital, yakni: uploading, chatting, posting, dan – tentu saja – selfie” (hlm. 30-31). Gawai bagi banyak orang menjadi barang tak boleh ditinggalkan. Selalu dibawa ke mana dan kapan saja. Kebutuhan pokok bukan berkutat pada tiga perkara mendasar: sandang, pangan, papan. Namun, ada satu hal lagi bernama gawai. Kecenderungan manusia dalam tujuan eksistensi menguatkan akan bujuk rayu tiap lorong gawai membawa manusia dalam pertaruhan diri.
Kita menginsyafi zaman ini berada pada situasi pasca kebenaran. Istilah itu sebagai terjemahan “post truth”, dua kata pada tahun 2016 dinyatakan sebagai istilah pada tahun tersebut oleh Oxford Dictionary, dengan pengertian: keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan keyakinan pribadi. Kemenduaan yang dilahirkan dari teknologi digital, salah satunya membawa pada beberapa konsekuensi pada perjalanannya. Mulai dari fanatisme, berita bohong (hoaks), keterasingan diri, lemahnya demokrasi, dan sikap banalitas diri.
“Di ruang digital pesan-pesan mengalir dan berubah sangat cepat. Fakta pun kehilangan stabilitasnya, tergerus oleh komentar-komentar yang tidak terhenti, sehingga berbagai pertanyaan itu tidak pernah cocok dengannya” (hlm. 53). Kondisi tersebut kemudian diperparah kehadiran kelompok dengan sengaja memanfaatkan ruang digital untuk berbuat pengaruh baik kepentingan ekonomi, politik, hingga ideologi. Mereka membuat skema kabar bohong dan misinformasi untuk mengelabuhi warganet. Kabar bohong kerap menjadi pusat perhatian dengan narasi penuh sensasional dan kehebohan.
Belum lagi, pada aras lebih lanjut, saat kepentingan politik mengedepankan ruang digital sebagai panglima. Mereka bebondong-bongong membuat strategi terkait politik pasca kebohongan lengkap dengan para pendengung (buzzer), yang tiap saat menjalankan tindakan demi tindakan untuk menggiring opini. Tak peduli apa yang dilakukan itu menyakiti maupun menjatuhkan pihak lain. Fanatisme mudah tumbuh dan berkembang baik berwujud ketidakberpikiran dan kebencian. Contoh kasus di Indonesia dari situasi tersebut salah satunya adalah saat perhelatan pemilihan umum.
Pandemi Covid-19 dianggap banyak orang sebagai proses percepatan transformasi digital. Di berbagai kalangan mulai terbiasa menggunakan jenis perangkat untuk pertemuan secara dalam jaringan (daring). Namun, apakah percakapan itu dengan sendirinya menjadikan kehidupan digital tertata dan berjalan dengan baik? Tentu, tidak. Arus kehidupan yang semakin kompleks ini setidaknya menambah tantangan dalam era ini. “Sosok dalam forum digital itu diringkas menjadi idea atau konten komunikasi yang kehilangan ketakterdugaan yang biasanya dapat ditimbulkan oleh situasi interkorporeal” (hlm. 194).
Di tahun 2020, Netflix merilis sebuah film berjudul The Social Dilemma. Film dokumenter dengan melibatkan beberapa perusahan besar terkait teknologi informasi dan komunikasi tersebut menyajikan fakta yanag tak terduga akan kenyatan dalam dunia digital. Bahwa masalah-masalah yang hadir dan kait kelindan di dunia digital di mata praktisi, para ahli, dan pelaku di industri teknologi merasa kewalahan membendungnya. Kompleksitas yang muncul dalam dunia digital pada akhirnya menjadi pertaruhan baru dalam kehidupan umat manusia.
Lantas, apa yang semestinya dilakukan untuk memperbaiki agar manusia memperlakukan teknologi digital sebagaimana cara menyangsikan ala Descartes, “Cogito ergo sum” (aku berpikir, maka aku ada) bukan sebatas pada “I browse” yang berujuk pada “Aku klik, maka aku ada”?. Beberapa hal yang disampaikan F. Budi Hardiman di dalam bab terakhir rasanya perlu menjadi renungan bersama. Masing-masing adalah: keberanian, kejujuran, dan keugahariaan (pengendalian diri). “Ketiganya diperoleh, jika manusia qua pengguna transenden terhadap sistem, karenanya dengan cara itu ketiganya terwujud sebagai keutamaan” (hlm. 246).
*Bergiat di Lingkar Diskusi Eksakta. Penulis Buku Sains, Kemajuan, dan Kemanusiaan.