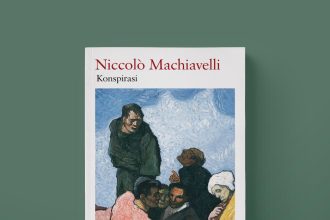Oleh: Ikhlaqul Qudus
Judul Buku : Yasima Ingin Jadi Juru Masak Nippon
Penulis : Edy Firmansyah
Penerbit : Cantrik Pustaka, Yogyakarta
Cetakan : I, Agustus 2021
Tebal : 132 halaman
ISBN : 978-623-6063-18-7
Ada banyak manfaat buat kita ketika mempelajari sejarah. Selain bisa lebih kritis menyikapi laju zaman, belajar sejarah juga dapat dijadikan sumber inspirasi untuk menghadapi hari depan. Dengan lain kata, mempelajari sejarah dapat membimbing kita agar tidak mengulangi hal yang buruk di masa lalu. Itulah mengapa Soekarno selalu mewanti-wanti dengan akronim Jas Merah; jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Sayangnya, pelajaran sejarah kerap kali membosankan. Masih umum anggapan bahwa belajar sejarah berarti menghafal materi-materi sejarah, seperti; tanggal, tahun, nama tokoh, dan nama tempat. Hafalan seolah menjadi patokan ‘resmi’ mempelajari sejarah. Akibatnya pelajaran sejarah seringkali membuat kita pening dan mengantuk. Seolah-olah lebih menyiksa daripada matematika.
- Iklan -
Lantas bagaimana membuat sejarah agar menjadi suatu hal yang menarik dan bisa dinikmati tanpa mengernyitkan dahi? Salah satunya dengan mencoba membaca karya fiksi sejarah.
Fiksi sejarah adalah dunia rekaan yang menggunakan peristiwa sejarah di masa silam, saat pengarangnya belum lahir, minimal peristiwa 50 tahun ke belakang, sebagai latar tempat dan waktu dengan mengkondisikan cerita agar pembaca seolah-olah berada di antara peristiwa yang diceritakan itu. Banyak pengarang yang melakukannya. Beberapa nama pengarang yang bisa disebut yang telah menelurkan fiksi sejarah adalah Pramoedya Ananta Toer dengan tetralogi pulau burunya (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca), YB. Mangunwijaya (Burung-Burung Manyar), dan yang terbaru Iksaka Banu (Semua Untuk Hindia dan Teh dan Pengkhianat). Nama-nama pengarang yang saya sebut itu menggunakan latar masa kolonialisme dalam fiksinya.
Meski tentu saja fiksi sejarah tidak bisa dijadikan referensi sejarah, namun setidaknya dapat menjadi jembatan untuk mencintai sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan. Para pengarang yang kemudian memasukkan data sejarah menjadi cerpen atau novel, barangkali akan menarik minat orang untuk mulai kembali membaca dan mencintai sejarah. Minimal sejarah tidak lagi dibaca dengan dingin dan berjarak, melainkan memiliki ikatan emosional. Terutama sejarah kolonialisme di wilayah kita tinggal.
Nah, Edy Firmansyah dengan buku kumpulan cerita pendeknya ini mencoba menulis cerita pendek dengan latar sejarah kolonialisme di Madura. Pengarang kelahiran Pamekasan itu mungkin bukan satu-satunya pengarang yang mencoba menggunakan sejarah kolonialisme di Madura sebagai latar cerita. Sebab mungkin banyak pengarang sebelum dia yang telah mencobanya dan saya belum sempat membacanya.
Melihat dari makin bertumbuhnya pengarang Madura yang tinggal dan berproses di Madura, Edy Firmansya lewat buku ini seolah mencoba menempuh jalan lain. Jika kebanyakan cerpenis yang berasal dari pulau garam mengangkat tema yang tak jauh dari carok, kekerasan, budaya lokal, dan harga diri, Edy Firmansyah memilih mengangkat tema kolonialisme di Madura. Tempat dia lahir dan ari-arinya ditanam.
Dalam 14 cerita dalam buku yang diterbitkan Cantrik Pustaka itu, Edy Firmansyah memasukkan unsur sejarah masa kolonial Belanda hingga Jepang di Madura. Ada tiga periode yang menjadi fondasi utama kumpulan cerita pendek bersampul putih tulang itu; masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, dan masa pasca kemerdekaan, terutama upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaannya dengan membonceng NICA.
Dalam masa pendudukan Belanda ia menggarap merebaknya peredaran candu di Madura, tentang pergundikan, tentang perburuan hewan liar, dan wabah kusta. Pada masa pendudukan Jepang, ia menggarap Jugun Ianfu. Sedangkan pasca pendudukan Jepang ia menggarap peristiwa pembantaian di depan masjid Jamik Pamekasan di tahun 1947 yang dilakukan Belanda.
Setidaknya ada tiga cerita yang mengambil latar Peristiwa pembantaian laskar Madura di depan masjid Jamik pamekasan di tahun 1947 itu, yakni; Vanisse Meertruida dari Zoutlanden, Perburuan Agustus 1947, dan Magasin Terakhir Sang Penembak Jitu. Dalam cerpen Vanisse Meertruida dari Zoutlanden tokoh yang digunakan adalah orang Belanda yang digambarkan menjunjung tinggi kemanusiaan (Vanisse dan Joop Roeting). Sedangkan pada Perburuan Agustus 1947 tokohnya adalah orang Madura (Ladrak) yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan Soekarno-Hatta. Pada Magasin Terakhir Sang Penembak Jitu tokohnya adalah kakak beradik yang berbeda haluan ideologi. Sang Kakak adalah tentara perjuangan sedangkan adiknya memilih menjadi pasukan NICA.
Tiga cerita pendek tersebut seolah mengingatkan kita bahwa demi mempertahankan kemerdekaan banyak sekali kepahitan dan derita yang dialami oleh nenek moyang kita. Bahkan hingga bertaruh nyawa. Sialnya, tak sedikit peristiwa sejarah yang menjadi pijakan bagi jatuh bangunnya sebuah masyarakat kerap dilupakan. Seperti peristiwa pembantaian di depan Masjid Jamik, Pamekasan itu. Dulu kuburan massal para laskar Madura itu berada tepat di depan masjid Jamik Pamekasan. Di bawah patung garuda (sebelum dipindah ke TMP Panglegur). Kini tempat itu menjadi tempat nongkrong anak-anak muda.
Namun dari 14 cerita pendek dalam buku setebal 132 halaman itu nyatanya tidak semua memakai sejarah kolonialisme di Madura sebagai latar. Setidaknya ada dua cerita yang tidak berada dalam tiga periode yang saya sebutkan di atas. Yakni, Kutukan Film Perang dan Sang Paraji. Meski demikian bukan berarti kedua cerita itu tak memiliki kandungan sejarah. Justru sebaliknya, dua cerita pendek itu juga bagian dari sejarah di Madura. Pada Kutukan Film Perang, misalnya, cerita itu meski digarap dengan realisme magis, menceritakan kembali mengenai peristiwa konflik tentara dengan masyarakat saat pembangunan Waduk Nipah di tahun 90an. Pada Sang Paraji latar yang digunakan adalah periode tahun 1960-an, tepatnya saat pembersihan orang-orang yang dituduh komunis sedang marak dan seolah jadi mimpi buruk.
Sampai di sini, terbitnya buku kumpulan cerita pendek ini layak diapresiasi. Kehadirannya seolah memberi angin segar pada pengarang muda, Madura khususnya, yang baru akan merintis karir atau sedang meniti karir, bahwa meski tak ada yang baru di bawah matahari, selalu ada celah untuk membuat karya yang segar. Ternyata tema soal Madura tidak melulu tentang carok, konflik budaya lokal dengan modernitas, dan harga diri. Ternyata tema kolonial pun memungkinkan untuk digarap. Asal dikelola dengan teknik yang bagus setiap karya pasti mengesankan. Salah satunya buku ini.
*Ikhlaqul Qudus adalah mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Madura. Aktivis PMII dan beraktivitas sebagai jurnalis kampus di Majalah Activita. Tinggal di Pamekasan. Menulis resensi buku.