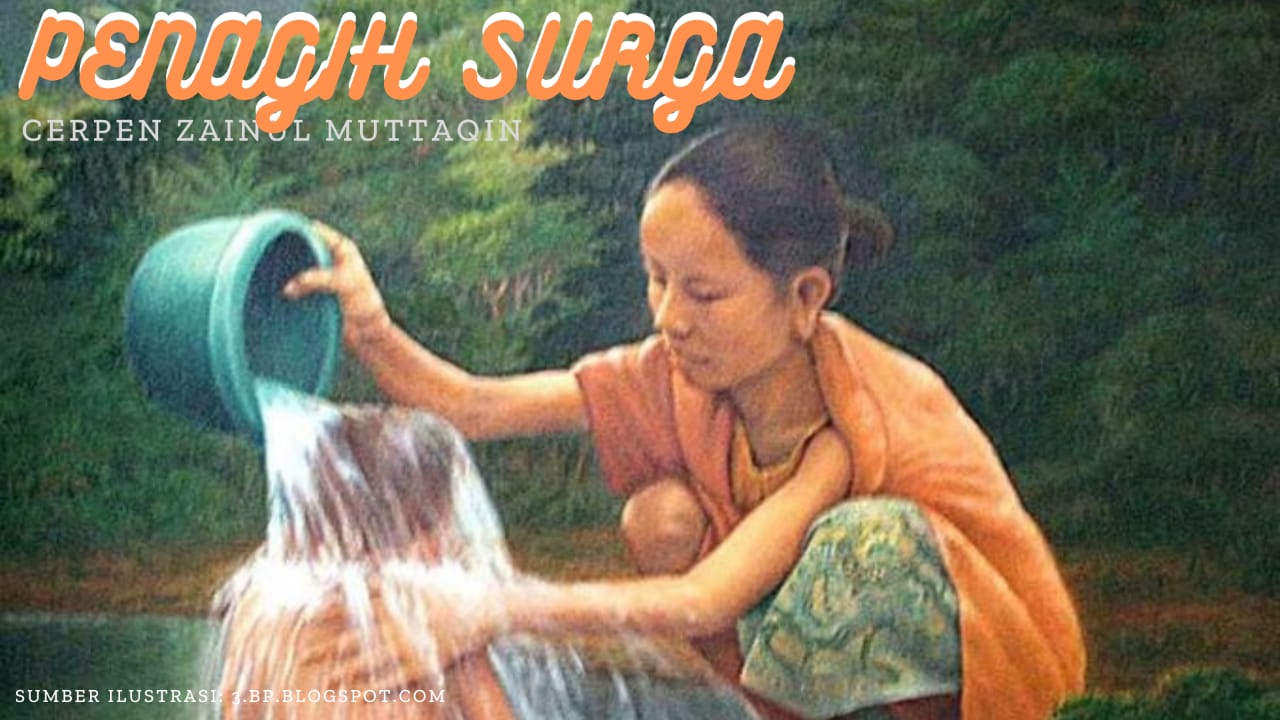Cerpen Zainul Muttaqin
Tubuh Murakkab diseret, hendak diceburkan ke dalam telaga api. Laki-laki muda, dengan tulang belulang serupa batang lidi itu berusaha melepas diri, berontak dari genggaman tangan lelaki-lelaki bertubuh besar, tinggi, kekar, berwajah beringas yang terus menerus menariknya untuk dilemparkan ke dalam telaga api tanpa tepi. Lidah api terjulur-julur bagai lidah mencecap bibir, siap menghisap para pendosa. Dalam sekali hisap, telaga api itu bisa membuat kulit mengelupas sampai tinggal tulang belulangnya saja.
Murakkab tidak memiliki kemampuan melepas diri, hanya sanggup berteriak, dalam getar tubuh yang ketakutan Murakkab bertanya, “Apa pantas manusia suci seperti saya dilempar ke telaga api itu? Tidak pantas kalian perlakukan saya seperti ini!” Tidak dijawab pertanyaan sekaligus kekesalan Murakkab itu. Justru tubuh-tubuh serupa bayangan itu kian beringas, ingin segera melempar tubuh Murakkab ke dalam telaga api.
“Masih ada kotoran di tubuhmu, untuk itulah tubuhmu harus dibasuh terlebih dulu.” Terdengar oleh Murakkab suara itu, serupa bisik di telinganya. Tetapi ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, sebab tubuh-tubuh serupa bayangan itu tidak terlihat membuka mulut sejak tadi. Mereka tetap memegang tubuh Murakkab, seperti sedang menunggu perintah untuk menceburkannya ke dalam telaga api tanpa tepi itu.
- Iklan -
Satu hal yang tak dapat dimengerti oleh Murakkab, bertanya-tanya ia dalam dirinya sendiri, kenapa harus telaga api yang saya terima? Saya dijanjikan istana surga apabila selalu menuruti semua perkataan ibu, dan selama ini, selama saya hidup sudah saya lakukan itu. Apa mungkin hanya ibu saya yang tidak punya surga di telapak kakinya? Tubuh Murakkab bergetar dalam ketakutan yang teramat melihat api dalam telaga itu berkobar, menyala, cahayanya berkilau-kilau dengan warna merah besi berkarat, pekat, siap menyerap tubuhnya untuk menyatu ke dalamnya.
“Satu kesalahan yang kau lupa, dan ingatlah kesalahan apa itu. Karena satu kesalahan itu, kau harus diceburkan ke dalam telaga api itu selama satu abad.” Lagi-lagi Murakkab mendengar bisik itu, terdengar jelas di telinganya.
Pikirannya baru mencoba mengingat peristiwa apa yang membuatnya harus diceburkan ke dalam telaga api itu, Murakkab sudah dilempar ke dalam mulut api itu, berteriak menahan panasnya api telaga, tiada terkira panasnya. Kulit tubuh Murakkab mengelupas dalam sekejap, dalam sekejap pula kulit tubuhnya itu kembali seperti sedia kala, lalu mengelupas lagi dan begitulah seterusnya yang akan dirasakan Murakkab selama satu abad.
Tubuh Murakkab dililit api. Dalam kondisi seperti itu, ia belum menemukan potongan ingatan soal dosa yang membuatnya dilahap api dalam telaga. Malah ia menemukan potongan ingatan soal kebaikan demi kebaikan yang ia kerjakan, sangat sulit mencari di mana letak kesalahan Murakkab karena sejak ustaz ngajinya dulu bilang, “Surga seorang anak terletak di telapak kaki ibu, berbuat baiklah pada ibumu jika ingin menghuni surga, jangan sekali-kali mengatakan ‘ah!’ pada ibumu.”
Sepengetahuan warga Tang-Batang masa kecil Murakkab memang dihabiskan dengan merawat sang ibu. Tidak sedikit pun ia mengeluh, apalagi sekadar cemberut karena harus rela menjaga ibunya yang sedang tergolek di atas ranjang, lumpuh sejak Murakkab berumur delapan tahun. Murakkab dikenal baik perangainya, bisa dibilang cuma ia satu-satunya anak yang tak terdengar ribut dengan ibunya sendiri.
Memijit pergelangan kaki sang ibu dilakukan oleh Murakkab setiap pagi, selalu dikerjakan dengan ketulusan yang tak dibuat-buat. Murakkab menyiapkan sarapan, menanak sendiri, bahkan ia sendiri yang mencari cara bagaimana agar dapur tetap mengepul sehingga ibunya tak kelaparan. Berbagai cara dilakukan oleh Murakkab demi menghidupi sang ibu dan dirinya sendiri. Ia bekerja serabutan, apa saja dilakukan asal bisa dapat uang, dan yang terpenting lagi pekerjaan itu dilakukan dengan cara halal.
Tinggal berdua di rumah berupa gubuk reyot setelah ayahnya meninggal ditelan gelombang laut, dalam gelap malam hari ketika laki-laki uzur itu tetap nekat berlayar sekalipun ia sendiri tahu ombak sedang ganas, siap menelan setiap perahu yang berlayar. Hal itu dilakukan semata-mata demi menghidupi keluarga, demi tanggung jawabnya sebagai lelaki, sebagai kepala rumah tangga yang selalu harus siap memberi makan anak-istrinya di rumah.
Hingga tahlilan tujuh hari selesai digelar tidak ditemukan juga jasad Masrakib, ayah Murakkab itu. Menurut orang-orang, bisa jadi jasad Masrakib sudah dimakan ikan paus, atau mungkin sudah menjadi bangkai dan tubuhnya sudah tercerai-berai karena saking lamanya mengendap di dalam perut laut. Murakkab berada dalam rangkulan ibunya, menangis tersedu-sedu, meronta-ronta ingin mencari ayahnya ke laut.
Sejak itu kondisi tubuh Mastini, ibu Murakkab itu pelan-pelan digerogoti berbagai macam penyakit sampai akhirnya ia hanya bisa tergolek di atas ranjang. Hari-hari berikutnya Mastini semakin lemah, sudah tidak sanggup untuk sekadar menggeser tubuhnya sendiri. Murakkab menjadi satu-satunya harapan Mastini, satu-satunya anak yang diharap bisa merawatnya hingga ajal menjelang.
Murakkab seperti yang diharapkan ibunya. Ia menjadi tulang punggung sekaligus perawat bagi ibunya. Menggendong ibunya ke kamar mandi, Murakkab berjalan terpiuh-piuh bagai detak jantung yang melemah. Terharu Mastini memiliki satu anak lelaki begitu setia, tulus, dan tak sedikit pun mengeluh merawatnya hingga bertahun-tahun sampai saat ini, sampai Murakkab beranjak dewasa, memasuki usia dua puluh satu tahun.
Kekaguman ditunjukkan juga oleh warga kampung. Dalam setiap obrolan pagi hari, sambil menyelisik kutu, perempuan-perempuan itu selalu berkata, “Semoga anak saya sama seperti Murakkab, menjadi anak berbakti pada ibunya. Anak seperti itu sudah pasti kelak akan menjadi penghuni surga.”
Murakkab baru saja lewat di depan perempuan-perempuan yang duduk berbanjar di depan rumahnya itu. Lelaki muda itu sedang memikul kayu, berjalan menundukkan kepala, pertanda memberikan salam hormat kepada perempuan-perempuan itu. Mereka semakin kagum saja dengan tingkah laku Murakkab. Tidak sangka akhlak Murakkab sedemikian baik, pikir mereka dalam tempurung kepalanya.
Karena kekaguman itulah mereka kerap datang berkunjung ke rumah Murakkab, menengok Mastini dengan membawa rempah-rempah, gula, kopi, beras diberikan kepada Murakkab dengan harapan anak-anak mereka bisa sama persis dengan Murakkab. Tidak hanya itu, pernah ada seorang ibu hamil meminta Murakkab mengusap perutnya, berharap usapan tangan Murakkab menjadi doa bagi anaknya agar menjadi anak saleh seperti Murakkab.
Sebagian warga kampung kerap membawa nama Murakkab ketika mereka cekcok, atau pun bertengkar hebat dengan anaknya sendiri. Saat anak mereka menentang, bahkan mengumpat karena keinginannya tak sanggup dituruti oleh sang ibu, maka dengan tegas, lantang suaranya, si ibu akan berkata di depan wajah anaknya, “Tirulah Murakkab, ia tak pernah meminta apa pun dari ibunya, malah ia banyak memberi pada ibunya. Anak seperti Murakkab kelak diganjar surga, dan kamu bisa jadi diganjar neraka. Ingat itu!”
Andai saja warga kampung tahu satu cerita ini, maka dapat dipastikan mereka akan semakin takjub dengan Murakkab. Kejadian ini tidak pernah diceritakan kepada siapa pun, termasuk ibunya. Suatu hari Murakkab sudah siap menghidangkan sarapan pagi pada ibunya, lengkap dengan lauk pauknya. Murakkab mengangguk saat ibunya bertanya, apa kamu sudah makan? Padahal tak sebutir pun nasi masuk ke dalam perut Murakkab pagi itu.
Sesungguhnya ia bisa saja sarapan pagi, tapi ia tahu nasi yang ada di dapur hanya cukup untuk dimakan sang ibu sore harinya. Tak mungkin ia sarapan pagi, bisa-bisa ibunya yang tidak akan makan sore harinya. Hal seperti ini terjadi berulang-ulang, Murakkab selalu memilih mengalah, lebih baik lapar ketimbang melihat ibunya sendiri kelaparan. Murakkab berpikir, saya masih bisa menahan lapar, tapi apa ibu yang sudah sakit seperti itu sanggup menahan lapar?
Bertahun-tahun Murakkab habiskan waktu hanya untuk merawat sang ibu sampai akhirnya Murakkab meninggal di usia muda, dua tahun setelah ibunya yang lebih dulu dijemput Izrail, selepas azan subuh. Itulah mengapa ia terkejut mendapati dirinya, dalam ruang gelap, dalam kondisi bagai seorang maling yang diseret-seret hendak diceburkan ke dalam telaga api. Untuk itu pula, ia kerap bertanya, kenapa api yang diberikan pada saya? Saya mestinya mendapat surga sebagaimana yang dijanjikan.
Satu potongan ingatan itu kini baru berada dalam kepala Murakkab. Tubuh laki-laki muda itu mendidih dalam telaga api, tidak terperi sakitnya yang terus menerus, berulang-ulang hingga tiba di mana ia akan diangkat dari dalam telaga api itu. Mengingat peristiwa itu, Murakkab baru sadar bahwa ia pernah cekcok dengan ibunya, sebuah pertengkaran kecil yang tak disengaja. Bahkan Murakkab sendiri meminta maaf, memohon ampun pada ibunya dengan jawaban sebatas anggukan kepala oleh ibunya. Pertengkaran itu terjadi selepas magrib. Bulan baru muncul dari balik dekapan awan kala itu.
Pertengkaran kecil itu dimulai oleh Mastini saat ia memanggil anaknya, Murakkab itu. Berkali-kali Murakkab dipanggil tidak menyahut, kesal Mastini karena panggilannya tak digubris oleh Murakkab. Beberapa saat kemudian Murakkab muncul dengan membawa tasbih, berputar-putar di tangan kanannya. Mulutnya berkomat-kamit, zikir sehabis salat.
“Ada apa, Bu? Saya tidak menyahut karena sedang salat. Ah! Ibu mengganggu konsentrasi salat saya saja.” Mastini diam tidak menanggapi perkataan anaknya. Ditekan suara Murakkab, agak kasar di akhir kata-katanya itu.
Semula Mastini berniat minta tolong pada Murakkab, ia ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Sudah sejak tadi ia menahannya, tetapi melihat tingkah Murakkab seperti itu, ia jadi urung. Terlebih Murakkab bilang kalau ia tidak akan turun dari atas sajadahnya jika tidak dipanggil barusan, ia ingin menunggu azan isya. Lebih-lebih waktu antara magrib ke isya adalah waktu istijabah, demikian kata Murakkab pada ibunya.
“Kau sudah tahu alasannya, mengapa kau harus berada dalam telaga api itu selama satu abad.” Murakkab mendengar suara itu lagi, tanpa pernah tahu siapa yang berkata. Dalam telaga api itu, tubuh Murakkab dikunyah hingga menjadi butiran-butiran debu. Tubuh Murakkab kembali utuh beberapa saat kemudian, lalu dililit lagi oleh api telaga, dibakar bersinambung. Secara terus-menerus pula Murakkab berucap, dalam keadaan tubuh yang lebur menjadi arang, “Mana surga saya?” ***
Pulau Garam, Oktober 2017-2020
*Zainul Muttaqin lahir di Garincang, Batang-Batang Laok, Sumenep. Kini bertempat tinggal di Pamekasan Madura. Alumnus Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep. Cerpen-cerpennya dimuat di pelbagai media lokal dan nasional. Buku kumpulan cerpennya; Celurit Hujan Panas (GPU, Januari 2019). Email; lelakipulaugaram@gmail.com